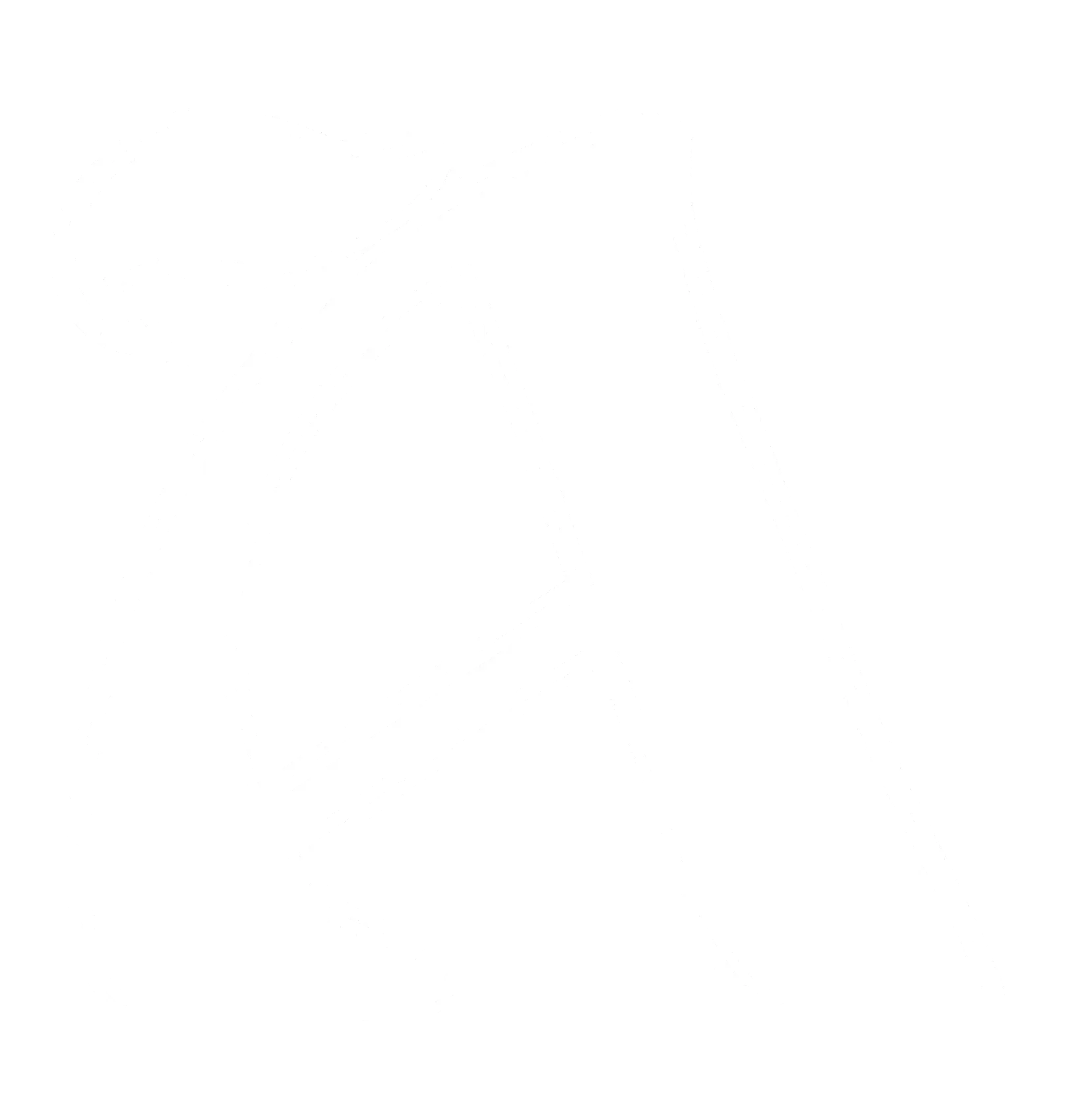Mendudukkan Nalar Penyelenggaraan Kementerian Haji dan Umrah

Editor: Khansa Nadira
Kabar Baru, Opini— Pemisahan urusan haji menjadi kementerian mandiri di Indonesia semula disambut sebagai fajar baru bagi manajemen ibadah rukun Islam kelima ini. Harapannya sederhana namun fundamental: hadirnya institusi yang fokus, lincah, dan mampu menjawab kerumitan logistik serta diplomasi transnasional. Namun, setelah berjalan, publik justru disuguhi pemandangan yang paradoksal. Alih-alih melahirkan terobosan manajerial yang revolusioner, kementerian baru ini tampak masih terjebak dalam nalar birokrasi lama yang lebih memuja aspek kosmetik daripada esensi operasional. Kritik nalar atas penyelenggaraan haji hari ini harus dimulai dari satu pertanyaan mendasar: apakah kementerian ini hadir untuk melayani jemaah atau sekadar memperpanjang rantai seremoni kenegaraan?
Nalar penyelenggaraan haji saat ini cenderung bias pada dimensi seremonial. Kita menyaksikan energi kementerian yang begitu besar terserap untuk agenda-agenda simbolis mengenai keberhasilan administratif yang sejatinya merupakan standar minimum pelayanan. Di balik keriuhan simbolis tersebut, aspek-aspek fundamental seperti mitigasi krisis di Masyair (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), standardisasi kualitas katering yang setara di setiap maktab, hingga diplomasi perlindungan hukum jemaah di Tanah Suci justru kerap terabaikan. Nalar yang bekerja adalah nalar “penyelenggara acara” (event organizer), bukan nalar “manajemen risiko” yang sangat krusial dalam operasi massa berskala jutaan orang.
Persoalan ini kian meruncing ketika kita menelisik lebih dalam struktur vertikal kementerian. Kehadiran Kementerian Haji seharusnya membawa kejelasan garis komando yang lebih tajam hingga ke tingkat tapak. Namun, realitasnya, pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) di tingkat provinsi dan Kantor Departemen (Kadep) di tingkat kabupaten/kota masih menyisakan lubang besar dalam pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Terdapat kegagapan dalam mendefinisikan mana yang menjadi wewenang pusat dan mana yang menjadi otonomi daerah dalam urusan haji. Ketidakjelasan ini berisiko menciptakan inefisiensi anggaran dan birokrasi. Tanpa regulasi turunan yang presisi terkait kewenangan operasional, instansi di daerah hanya akan menjadi “perpanjangan tangan administratif” yang pasif, menunggu instruksi pusat tanpa keberanian melakukan inovasi layanan lokal berbasis kebutuhan jemaah masing-masing daerah.
Lebih jauh lagi, kegagapan nalar ini berdampak pada macetnya konsolidasi multisektoral. Penyelenggaraan haji bukan kerja tunggal satu kementerian, melainkan orkestrasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan untuk urusan istitha’ah kesehatan, Kementerian Perhubungan untuk mobilitas udara, Kementerian Luar Negeri untuk diplomasi kuota dan perlindungan warga negara, hingga sektor perbankan untuk manajemen dana. Namun, dengan nalar yang masih bersifat sektoral dan berpusat pada seremoni, Kementerian Haji tampak kesulitan berperan sebagai konduktor dalam orkestrasi besar ini. Komunikasi yang dibangun kerap bersifat koordinatif di atas kertas, tetapi lemah dalam eksekusi lapangan. Akibatnya, ketika terjadi persoalan pelik seperti keterlambatan transportasi atau penumpukan jemaah di Muzdalifah, ego sektoral kembali muncul karena tidak adanya integrasi komando yang solid sejak awal.
Seharusnya, Kementerian Haji beralih dari nalar birokrasi administratif menuju nalar manajemen ekosistem. Dalam nalar ini, kementerian tidak perlu lagi terlalu disibukkan oleh urusan teknis-seremonial yang dapat didelegasikan atau diotomatisasi. Fokus utama harus diarahkan pada penguatan diplomasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk menjamin hak-hak jemaah Indonesia, serta penguatan sistem pengawasan terhadap vendor penyedia jasa di Tanah Suci. Di tingkat domestik, Kanwil dan Kadep harus diberikan kewenangan yang jelas untuk melakukan pembinaan jemaah secara berkelanjutan sepanjang tahun, bukan hanya saat musim haji tiba. Mereka harus berfungsi sebagai pusat informasi dan perlindungan, bukan sekadar loket pengumpulan berkas.
Kita perlu mengingatkan bahwa haji bukan sekadar perpindahan orang dari satu negara ke negara lain, melainkan ibadah suci yang melibatkan harkat dan martabat bangsa. Jika kementerian ini masih terjebak pada gaya kerja yang memprioritaskan citra daripada substansi, transformasi kelembagaan ini hanya akan menjadi beban baru bagi APBN tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan. Reformasi nalar birokrasi haji harus segera dilakukan: mengembalikan fokus pada hak-hak fundamental jemaah, memperjelas garis kewenangan di daerah, serta membangun sistem komunikasi multisektoral yang integratif. Tanpa itu, Kementerian Haji hanyalah struktur baru yang memikul beban lama.
Penulis adalah Mohammad Iqbalul Rizal Nadif, Pengurus PB PMII.


 Insight NTB
Insight NTB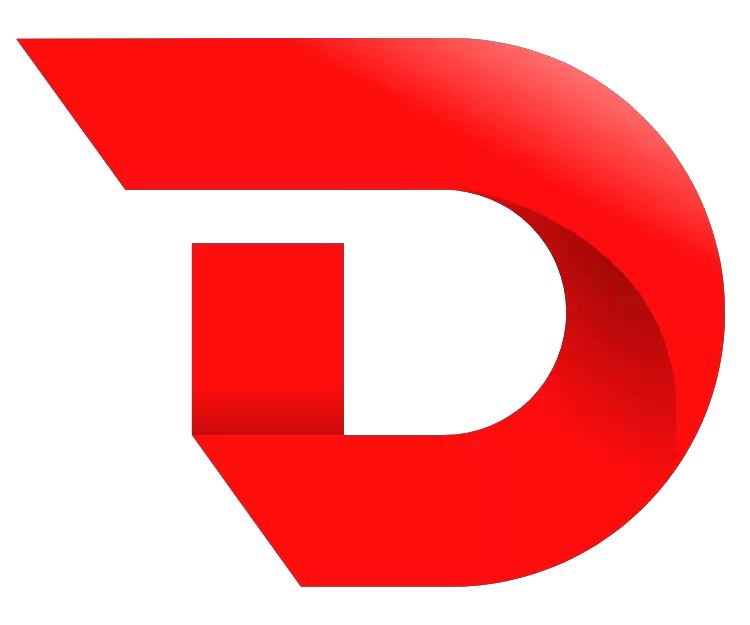 Daily Nusantara
Daily Nusantara Suara Time
Suara Time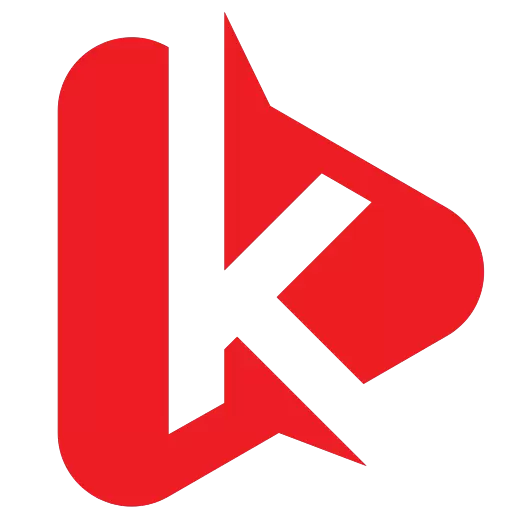 Kabar Tren
Kabar Tren Portal Demokrasi
Portal Demokrasi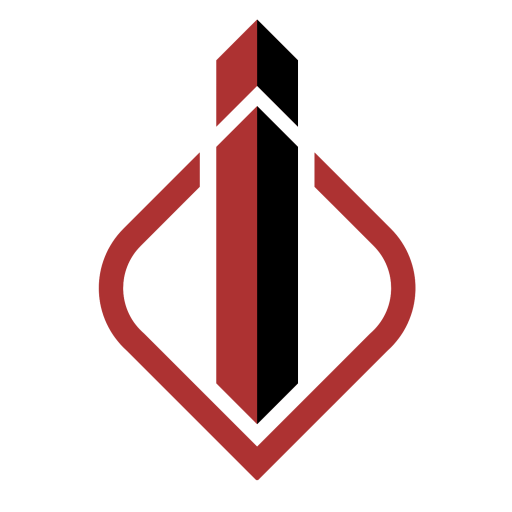 IDN Vox
IDN Vox Lens IDN
Lens IDN Seedbacklink
Seedbacklink