Menyibak Agenda Terselubung Delegitimasi Soekarno dan Pesantren

Editor: Khansa Nadira
Kabar Baru, Opini — Kita lihat akhir akhir ini media sosial diramaikan dengan upaya mengkerdilkan Bung Karno dan upaya mengkerdilkan pesantren dan kyai kyai. Seperti adanya upaya yang sistematis untuk menyerang kelompok yang memiliki basis ideologi yang kuat.
Dari fenomena beberapa bulan ini sepertinya ada upaya upaya untuk mendegradasi kelompok kelompok yang memiliki basis ideologi yang kuat Seperti adanya upaya desoekarnoisasi dan depesantrenisasi.
Maka dari itu kiranya perlu untuk didalami secara lebih serius dan objektif.
Soekarno dan Upaya Delegitimasi
Kontroversi bermula dari wacana revisi buku sejarah nasional. Beberapa pejabat menyebut perlunya menyusun “sejarah resmi” versi pemerintah agar publik memiliki acuan tunggal. Ide ini segera menuai kritik dari sejarawan dan publik luas. Kekhawatirannya sederhana tapi mendasar: ketika negara berperan terlalu jauh dalam mengurasi narasi masa lalu, sejarah berisiko berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Dalam konteks ini, nama Soekarno muncul sebagai tokoh paling rentan terhadap “penataan ulang” makna. Ia bukan hanya pendiri republik, tetapi juga simbol ideologi kebangsaan yang menekankan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan semangat nonblok. Menyentuh Soekarno berarti menyentuh fondasi nilai Indonesia sendiri. Karena itu, setiap upaya merevisi sejarahnya — apalagi tanpa transparansi — hampir selalu dibaca publik sebagai gejala politik, bukan akademik.
Sementara itu, di lapisan media sosial, terjadi gelombang besar konten yang menyudutkan citra Soekarno. Dalam tiga bulan terakhir, video-video pendek di YouTube, TikTok, hingga Reels Instagram kerap memuat judul sensasional seperti “Rahasia Gelap Soekarno yang Disembunyikan Negara” atau “Fakta yang Dihapus dari Buku Sejarah!”.
Formatnya seragam: cepat, dramatis, dan dangkal. Narasi disusun dengan potongan klip, narator misterius, dan musik tegang. Fakta sejarah diambil secara parsial, dilepaskan dari konteks sosial-politik zamannya, lalu diakhiri dengan kesimpulan bombastis. Algoritma platform pun memperkuat efeknya: semakin memancing emosi, semakin tinggi peluang video itu direkomendasikan ulang.
Hasilnya, publik tidak lagi membedakan antara sejarah dan sensasi. Dalam waktu singkat, Soekarno direduksi menjadi karakter yang bisa dikomentari seenaknya — bukan tokoh sejarah yang layak ditelusuri secara kritis. Inilah yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai “delegitimasi simbolik”: penghancuran makna melalui banjir informasi yang tampak bebas tapi sebenarnya diarahkan oleh logika algoritmik dan motif politik.
Soekarno bukan sekadar individu dalam sejarah. Ia adalah ide. Ide tentang kebangsaan, tentang kemerdekaan yang bukan hadiah, tentang kemandirian di hadapan kekuatan asing. Karena itu, setiap upaya untuk melemahkan makna Soekarno selalu punya implikasi ideologis.
Kita tahu, sejarah sering kali ditulis ulang ketika rezim berganti. Tetapi di era digital, “penulisan ulang” itu tidak lagi memerlukan buku pelajaran baru; cukup dengan ribuan konten pendek yang dikirimkan ke gawai setiap hari. Pola yang muncul terlihat sistematis meski tanpa pusat komando tunggal: isu dipilih (biasanya yang paling kontroversial); konteks dihapus; dikemas secara emosional; lalu diamplifikasi oleh akun-akun dengan afiliasi ideologis tertentu.
Hasil akhirnya sama: Soekarno tampil sebagai sosok yang perlu “direvisi” — baik oleh negara maupun oleh netizen.
Sulit menampik bahwa sebagian besar konten yang mendegradasi Soekarno juga berakar pada motif ekonomi. Sensasionalisme menjual. Nama besar Soekarno mudah menarik klik dan komentar. Namun, ketika motif ekonomi bertemu dengan kepentingan politik, hasilnya bisa jauh lebih serius: terbentuknya opini publik yang salah arah.
Jika dibiarkan, distorsi seperti ini dapat melahirkan generasi muda yang mengenal Soekarno bukan sebagai pemikir kebangsaan, tetapi sekadar “tokoh lama dengan masa lalu gelap”. Ini bukan sekadar kehilangan figur, tapi kehilangan arah — karena dari Soekarnolah bangsa ini belajar makna kemerdekaan yang sejati.
Soekarno pernah berkata, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya.” Kalimat itu kini terasa ironis ketika jasa dan gagasan beliau justru menjadi sasaran serangan simbolik yang tak berkesudahan.
Alih-alih memperkaya pemahaman sejarah, banyak konten justru menjadikan sejarah sebagai bahan olok-olok atau alat politik jangka pendek. Ini bukan sekadar kesalahan informasi — ini adalah kemunduran budaya berpikir. Kita menyaksikan bagaimana ruang digital yang seharusnya mencerdaskan, justru menjadi tempat dekontruksi nilai-nilai bangsa.
Pesantren, NU, dan Serangan Tajam
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, ruang publik Indonesia ramai oleh perdebatan tentang representasi pesantren, kiai, dan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu target utama wacana. Sementara framing di media massa dan media sosial menampakkan kecenderungan yang berulang: memilih potongan simbolik, menghapus konteks budaya, dan mengulangi narasi yang merendahkan martabat institusi tradisional.
Jika dilihat bersamaan, pola-pola ini memberi indikasi adanya agenda yang setidaknya operasionalnya bersifat terstruktur dalam menghasilkan delegitimasi publik terhadap NU dan kultur pesantren.
Peristiwa penting yang menjadi titik fokus publik akhir-akhir ini adalah kontroversi terkait sebuah episode program televisi Trans7 yang menampilkan potongan-potongan kehidupan pesantren. Tayangan itu menuai kecaman luas dari PBNU dan jaringan pesantren karena dianggap mempresentasikan tradisi penghormatan santri dan figur kiai dengan cara yang merendahkan, menonjolkan unsur materi (mis. klaim “kiai kaya menerima amplop”) tanpa memberikan konteks budaya dan historis. PBNU menyampaikan protes keras dan menuntut pertanggungjawaban media tersebut.
Reaksi publik di media sosial mengikuti dengan cepat: tagar boikot, repost potongan video, meme, dan opini yang memojokkan kiai serta praktik pesantren menjadi viral—segera mengubah narasi lokal menjadi isu nasional dan menempatkan NU pada posisi defensif. Ajakan boikot dan seruan protes itu membuat isu makin melebar dan memperkuat dampak delegitimasi di mata publik tertentu.
Di sisi lain, lembaga negara dan opini publik yang lebih luas memproduksi tulisan dan analisis yang mengkritik cara media memotret pesantren—menegaskan bahwa pemotongan konteks budaya menghasilkan kesalahpahaman serius. Kementerian Agama dan institusi keagamaan menuliskan esai yang memperingatkan tentang framing negatif dan perlunya konteks dalam peliputan soal pesantren dan kyai.
Lebih jauh lagi, PBNU menyatakan akan menempuh jalur hukum terkait tayangan tersebut, sebuah langkah yang menandai dampak nyata (bukan sekadar reaksi sosial) dari framing yang dipersoalkan.
Pola Framing: Mekanisme Operasional Delegitimasi
Dari sejumlah kasus dan debat publik, terdapat pola framing yang berulang. Pertama Seleksi Simbol dan Adegan. Produsen konten memilih elemen visual/tekstual yang paling mudah membangkitkan emosi (amplop, fasilitas, ritual penghormatan) lalu menekankan ketidaksesuaian antara simbol keagamaan dan tuduhan materialisme. Kedua Fragmentasi Konteks. Adegan diambil terpisah dari konteks ritual, sosiologis, atau historis sehingga makna aslinya berubah—dari penghormatan jadi eksploitasi, dari tradisi jadi feodalisme.
Ketiga Amplifikasi Algoritmis. Konten viral yang memancing kemarahan mendapat engagement tinggi dan kemudian direkomendasikan lebih luas oleh platform, memperbesar persepsi bahwa narasi negatif adalah pandangan mayoritas. Keempat Eksploitasi Kekurangan Literasi Publik. Rendahnya literasi media dan budaya membuat potongan narasi mudah dipercayai dan menyebar cepat tanpa koreksi kontekstual.
Motif Terselubung
Motivasi di balik pola delegitimasi ini bisa beragam dan seringkali tumpang tindih. Hal ini dapat dianalisa dengan nenggunakan beberapa karakteristik. Pertama Politik dan Persaingan Pengaruh. NU sebagai aktor sosial-keagamaan besar memiliki basis massa yang signifikan—melemahkan citranya bisa menggeser keseimbangan kekuatan ideologis dan politik. Kedua Komersialisasi Media. Sensasionalisme menjual; menonjolkan konflik budaya/agama mendatangkan clicks dan iklan.
Ketiga Kultur Modernitas vs Tradisi: Diskursus yang menilai tradisi sebagai penghalang kemajuan memberi legitimasi intelektual pada narasi yang meremehkan praktik keagamaan tradisional. Keempat Akun Ideologis / Buzzer: Aktor non-media (akun yang berpola terkoordinasi) dapat memanfaatkan momen untuk mempercepat penyebaran narasi tertentu.
Jika pola tersebut dibiarkan, beberapa konsekuensi nyata akan muncul: erosi kepercayaan terhadap institusi tradisional (NU/pesantren), meningkatnya polarisasi antara kelompok yang mempertahankan tradisi dan kelompok modernis/sekuler, serta normalisasi tafsir sejarah dan budaya yang instrumental untuk tujuan politik sesaat.
Apakah ada agenda sistematis? Berdasarkan bukti yang ada: pola-pola framing dan penyebaran sangat konsisten sehingga memberi kesan operasi yang terstruktur—yang penting dibedakan adalah apakah ada satu pusat komando. Data yang tersedia menunjukkan operasionalitas yang terkoordinasi secara tidak formal: kesamaan taktik (pemotongan konteks, seleksi simbol), penggunaan platform yang sama untuk amplifikasi, dan munculnya narasi berulang oleh aktor berbeda. Ini memenuhi syarat fungsi sistematis (hasil yang diulang dan konsisten) meski tidak selalu menunjuk pada evidensi satu pusat pengendali.
Fenomena framing negatif terhadap NU dan pesantren selama tiga bulan terakhir menunjukkan pola yang sistematik dalam hasil (delegitimasi dan degradasi citra). Walau bukti tentang satu komando terpusat belum final, efek kumulatif dari potongan-potongan narasi, amplifikasi algoritmis, dan pengulangan oleh berbagai aktor menciptakan sebuah agenda de-fakto yang berdampak pada legitimasi institusi tradisional. Menghadapi fenomena ini memerlukan kombinasi klarifikasi kontekstual, literasi publik, dan tata kelola etika media yang lebih kuat.
Penulis adalah Muhammad Sutisna, Co Founder Forum Intelektual Muda.
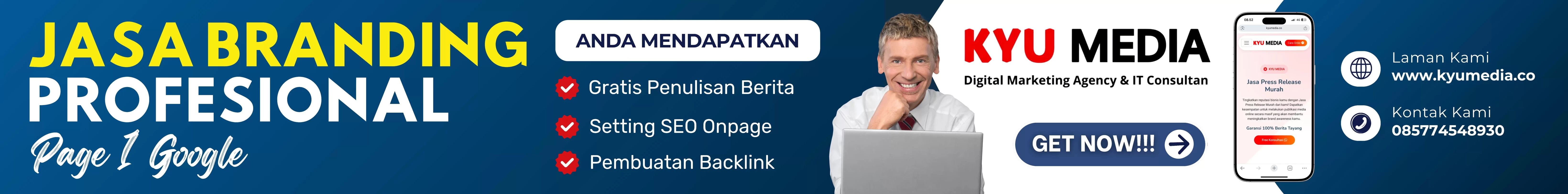

 Insight NTB
Insight NTB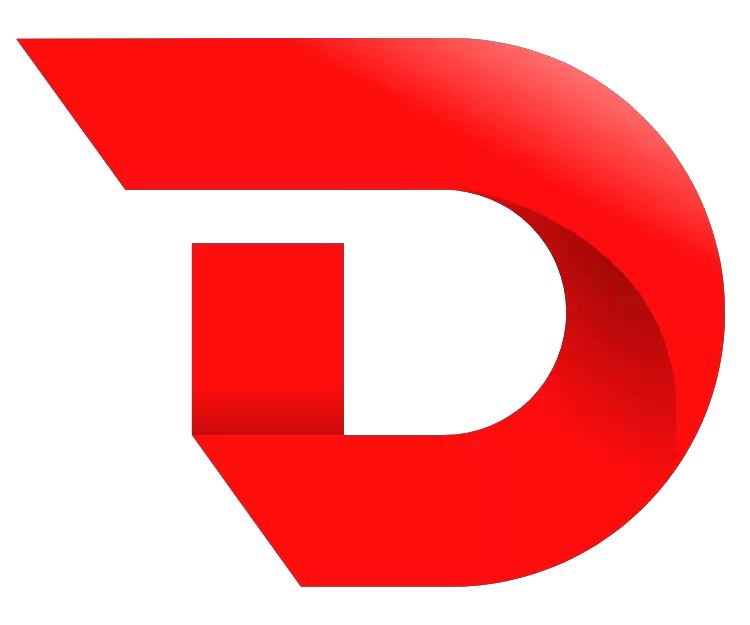 Daily Nusantara
Daily Nusantara Suara Time
Suara Time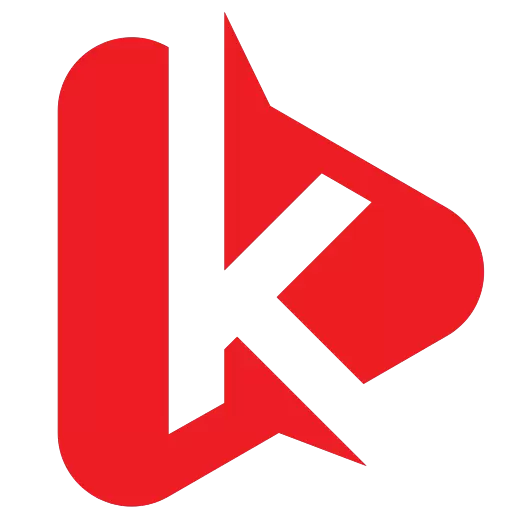 Kabar Tren
Kabar Tren Portal Demokrasi
Portal Demokrasi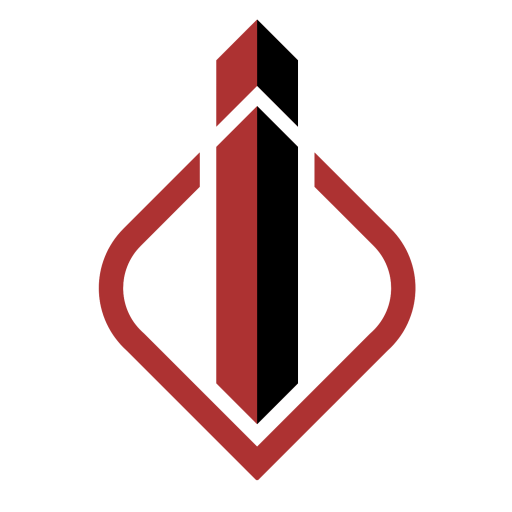 IDN Vox
IDN Vox Lens IDN
Lens IDN Seedbacklink
Seedbacklink





















