Menatap Ekonomi Indonesia 2025: Optimisme dan Tantangan

Editor: Bahiyyah Azzahra
Penulis : Harry Yulianto (Akademisi STIE YPUP Makassar)
Kabar Baru, Opini – Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Asia Tenggara. Pada beberapa dekade terakhir, stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan konsumsi domestik, dan bonus demografi menjadi fondasi penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Namun, memasuki tahun 2025, perjalanan ekonomi Indonesia akan dihadapkan pada dua sisi mata uang: optimisme yang didorong oleh potensi besar dan tantangan yang timbul dari dinamika global maupun domestik.
Pada sisi optimisme, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, digitalisasi sektor ekonomi, serta transisi menuju energi terbarukan. Komitmen tersebut bertujuan menciptakan daya saing yang lebih tinggi dan memperkuat keberlanjutan ekonomi. Selain itu, bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan produktivitas nasional jika diiringi oleh investasi di sektor pendidikan dan kesehatan.
Namun, tantangan juga tidak dapat diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, seperti perlambatan pertumbuhan Tiongkok, ancaman resesi di negara maju, dan risiko geopolitik, dapat memengaruhi perdagangan dan investasi di Indonesia. Di dalam negeri, isu kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan daya saing sumber daya manusia juga masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tulisan ini akan mengupas bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada, serta mengatasi tantangan untuk memastikan ekonomi nasional tetap tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2025. Artinya, setiap rencana atau kebijakan yang dibahas untuk tahun 2025 harus memiliki dimensi inklusif dan berkelanjutan agar perekonomian tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, baik di masa kini maupun masa depan.
“Perekonomian yang sehat bukan hanya tentang pertumbuhan angka, tetapi juga tentang bagaimana pertumbuhan itu merata dan berkelanjutan“, merupakan kutipan dari Joseph Stiglitz (Ekonom Peraih Nobel Ekonomi Tahun 2001) yang menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui angka-angka pertumbuhan, tetapi juga pada bagaimana manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat dan bagaimana pertumbuhan tersebut tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.
Perspektif Stiglitz dapat menjadi landasan untuk membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil Indonesia dalam menjaga inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi pada tahun 2025. Pada konteks ini, inklusivitas berarti memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang berada di daerah tertinggal atau rentan, dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan ekonomi, seperti akses ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang berkualitas.
Sementara itu, keberlanjutan ekonomi mengacu pada pertumbuhan yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, penggunaan sumber daya alam, dan keberlanjutan sosial untuk generasi mendatang. Perspektif ini mengarahkan Indonesia untuk mengintegrasikan isu-isu seperti transformasi energi hijau, inovasi teknologi, serta penguatan sektor UMKM sebagai bagian dari strategi ekonomi.
Optimisme
Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur, digitalisasi ekonomi, dan transisi energi terbarukan sebagai prioritas strategis untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung distribusi logistik dan efisiensi ekonomi. Menurut teori ekonomi klasik, infrastruktur merupakan public good yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan menarik investasi (Barro, 1990). Pada konteks Indonesia, langkah ini relevan untuk menghadapi tantangan geografis yang luas dan beragam, di mana konektivitas menjadi kunci integrasi pasar domestik.
Digitalisasi sektor ekonomi sebagai inisiatif lain yang signifikan. Pada teori ekonomi modern, digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan mendorong inovasi (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Pemerintah, melalui agenda transformasi digital, seperti Making Indonesia 4.0, berupaya mempercepat adopsi teknologi di sektor industri, UMKM, dan layanan publik. Digitalisasi tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti ekonomi berbasis platform dan fintech, yang telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Transisi menuju energi terbarukan sebagai langkah penting untuk keberlanjutan ekonomi. Mengadopsi teori Green Economy dari Pearce et al. (1989), langkah ini bertujuan menciptakan pertumbuhan yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Fenomena perubahan iklim dan komitmen global terhadap dekarbonisasi membuat Indonesia tidak hanya melihat transisi energi sebagai kewajiban lingkungan, tetapi juga peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Melalui kebijakan seperti Energy Transition Mechanism (ETM), pemerintah dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan energi bersih.
Bonus demografi juga menjadi faktor optimisme yang penting dalam ekonomi nasional. Menurut teori transisi demografi (Coale & Hoover, 1958), ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) tinggi, maka ada potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi mutlak. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sementara sistem kesehatan yang baik memastikan produktivitas tetap tinggi. Laporan Bank Dunia (2022) menyebutkan bahwa kualitas pendidikan dan kesehatan Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an.
Fenomena yang melatarbelakangi berbagai inisiatif optimisme meliputi globalisasi ekonomi, revolusi teknologi, dan perubahan dinamika lingkungan hidup. Pada lanskap global yang semakin kompetitif, inisiatif tersebut diharapkan dapat memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar regional dan global. Dengan mengintegrasikan investasi strategis pada infrastruktur, digitalisasi, energi hijau, serta pendidikan dan kesehatan, maka Indonesia tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, namun juga membangun fondasi keberlanjutan untuk masa depan.
Tantangan
Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya di tengah dinamika global dan domestik. Ketidakpastian ekonomi global, seperti perlambatan pertumbuhan Tiongkok, memberikan dampak signifikan karena negara tersebut merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Berdasarkan teori dependency oleh Prebisch dan Singer (1950), perekonomian negara berkembang sering kali sangat bergantung pada negara maju atau mitra dagang utama untuk ekspor komoditas. Ketika Tiongkok memperlambat impor bahan mentah, seperti batu bara dan kelapa sawit, Indonesia mengalami tekanan pada neraca perdagangan, yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan sektor komoditas.
Ancaman resesi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan kawasan Uni Eropa, juga menjadi faktor risiko besar. Pada model Mundell-Fleming untuk ekonomi terbuka, fluktuasi di negara maju dapat memengaruhi aliran modal dan nilai tukar di negara berkembang seperti Indonesia. Pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju, seperti kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve, sering kali menyebabkan arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga dapat melemahkan nilai tukar rupiah dan menekan cadangan devisa.
Dinamika risiko geopolitik, seperti konflik di Ukraina atau ketegangan di Laut Cina Selatan, juga memengaruhi stabilitas ekonomi global. Pada konteks Indonesia, risiko geopolitik dapat meningkatkan volatilitas harga komoditas, terutama energi dan pangan, yang berdampak pada inflasi domestik. Teori cost-push inflation menjelaskan bahwa kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga input seperti energi dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan.
Di sisi domestik, kesenjangan ekonomi tetap menjadi tantangan serius. Menurut teori Kuznets Curve, kesenjangan sering kali meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi sebelum akhirnya menurun. Namun, di Indonesia, distribusi kekayaan masih sangat timpang, dengan Gini Ratio yang cukup tinggi, sehingga mencerminkan adanya ketimpangan dalam pendapatan dan akses terhadap peluang ekonomi. Kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan inklusif, karena sebagian besar masyarakat tidak dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi.
Pengangguran, khususnya di kalangan muda, juga menjadi pekerjaan rumah besar. Menurut teori Human Capital oleh Becker (1964), kualitas tenaga kerja sangat menentukan daya saing ekonomi suatu negara. Namun, Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin terdigitalisasi. Laporan World Bank (2021) menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga, sehingga dapat menurunkan daya saing sumber daya manusia.
Fenomena tersebut ditunjukkan adanya transformasi struktural ekonomi yang belum optimal. Sektor manufaktur, yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi menurut teori industrialisasi (Rostow, 1960), mengalami stagnasi, sedangkan sektor informal tetap mendominasi. Kurangnya inovasi dan investasi dalam sektor teknologi tinggi, juga membatasi potensi daya saing global Indonesia.
Beberapa tantangan tersebut menunjukkan perlunya respons kebijakan yang terintegrasi. Pemerintah perlu mengelola risiko global dengan memperkuat ketahanan ekonomi domestik, seperti diversifikasi pasar ekspor dan stabilisasi nilai tukar. Di sisi lain, peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui reformasi pendidikan dan pelatihan kerja, serta penguatan kebijakan redistribusi ekonomi, menjadi kunci untuk mengatasi tantangan domestik. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, Indonesia dapat mengatasi tantangan tersebut serta memanfaatkan peluang untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Arah Strategis
Arah strategis Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2025 perlu berfokus pada pengelolaan peluang dan tantangan melalui pendekatan yang holistik dan berbasis bukti. Arah strategis dapat dijabarkan dengan mengintegrasikan teori-teori ekonomi, kebijakan berbasis praktik terbaik, dan pemahaman tentang fenomena ekonomi global serta domestik.
Pertama, Indonesia dapat memanfaatkan peluang dari bonus demografi. Menurut teori Demographic Dividend (Bloom & Williamson, 1998), peningkatan proporsi penduduk usia produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika diiringi oleh investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah perlu memperkuat sistem pendidikan melalui reformasi kurikulum yang berorientasi pada keterampilan abad ke-21, seperti literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja menghadapi transformasi digital.
Kedua, digitalisasi sektor ekonomi merupakan strategi kunci untuk meningkatkan daya saing. Menurut teori Endogenous Growth (Romer, 1990), inovasi teknologi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) menjadi pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Dengan memperluas akses internet, meningkatkan literasi digital, dan mendorong adopsi teknologi di sektor UMKM, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dari ekonomi digital. Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2022) menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai nilai USD 360 miliar pada tahun 2030, sehingga menjadikannya salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional.
Ketiga, transisi menuju energi hijau sebagai peluang serta kebutuhan untuk keberlanjutan ekonomi. Teori Green Growth (OECD, 2011) menekankan pentingnya menciptakan pertumbuhan yang mengurangi jejak karbon dan memperbaiki kualitas lingkungan. Pemerintah dapat mempercepat transisi energi hijau melalui insentif fiskal untuk investasi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, serta menghapus secara bertahap subsidi bahan bakar fosil. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi konvensional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi hijau.
Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan daya saing rendah harus diatasi melalui kebijakan redistribusi dan penguatan institusi. Berdasarkan teori Kuznets Curve, pertumbuhan ekonomi sering kali meningkatkan kesenjangan pada tahap awal pembangunan. Kebijakan fiskal yang progresif, seperti pajak berbasis kekayaan dan penguatan jaring pengaman sosial, diperlukan untuk menciptakan inklusivitas. Di sisi lain, untuk meningkatkan daya saing, pemerintah harus memperkuat iklim investasi dengan menyederhanakan regulasi, memperbaiki infrastruktur logistik, dan memastikan stabilitas makroekonomi.
Arah strategis juga harus merespons tantangan global, seperti ketidakpastian geopolitik dan perubahan iklim. Diversifikasi pasar ekspor dapat menjadi salah satu cara mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Tiongkok. Menurut teori Comparative Advantage (Ricardo, 1817), Indonesia harus fokus pada pengembangan sektor-sektor dengan keunggulan kompetitif, seperti agribisnis berkelanjutan dan industri berbasis sumber daya.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, Indonesia dapat mengatasi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang untuk membangun perekonomian yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. Arah strategis ini tidak hanya akan membawa pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada angka, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis secara sosial serta lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada masyarakat akan memperkecil kesenjangan sosial, menciptakan harmoni di tengah keberagaman, dan meningkatkan solidaritas antarwarga. Pada konteks lingkungan, fokus pada energi terbarukan dan keberlanjutan akan memastikan bahwa sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), di mana keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan menjadi pilar utama pembangunan.
Bagi generasi emas, arah strategis ini memberikan harapan masa depan yang lebih baik: peluang untuk berkembang dalam ekosistem yang mendukung inovasi, kewirausahaan, dan kreativitas, tanpa mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan demikian, arah strategis ini tidak hanya membangun pondasi ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis, serta memastikan warisan yang layak bagi generasi mendatang.
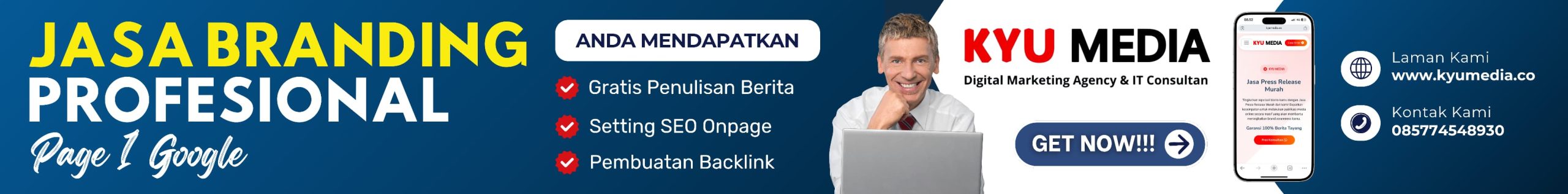

 Beritabaru.co
Beritabaru.co Serikatnews.com
Serikatnews.com Suaratime.com
Suaratime.com Kabartren.com
Kabartren.com Sabdaguru.com
Sabdaguru.com Dailynusantara.com
Dailynusantara.com Portaldemokrasi.com
Portaldemokrasi.com Seedbacklink.com
Seedbacklink.com

























