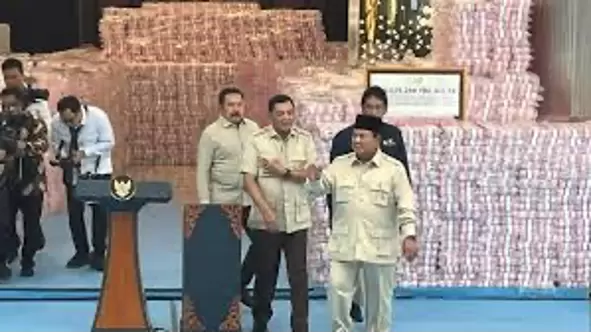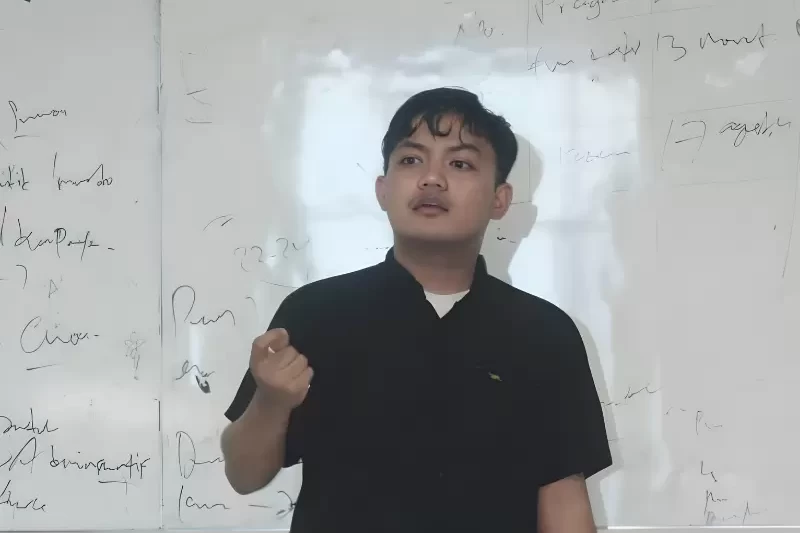Redenominasi: Siapkah Kita Memangkas Tiga Nol Rupiah?

Editor: Bahiyyah Azzahra
Kabar Baru, Kolom – Mari kita lihat realitanya, Anda sedang membayar belanja bulanan di swalayan. Nota yang keluar mencetak angka Rp 1.250.000 untuk sekeranjang barang yang tidak terlalu banyak. Atau, coba lihat harga properti yang dengan mudah mencapai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Deretan nol yang begitu panjang telah menjadi pemandangan sehari-hari yang seolah tidak terelakkan, dan membanjiri setiap transaksi kita.
Wacana pemotongan tiga nol pada mata uang Rupiah, atau redenominasi, kembali mencuat sebagai jawaban atas “kepadatan” angka tersebut. Gagasan ini sering kali diusung dengan janji efisiensi dan penyederhanaan sistem keuangan. Ide yang terdengar sederhana dan elegan di atas kertas, bukan?
Namun, di balik janji kemudahan tersebut, tersembunyi sebuah pertanyaan kritis yang tidak boleh lagi kita diamkan. Sudah siapkah kita, sebagai sebuah bangsa, untuk melompat dari konsep menuju eksekusi? Kesiapan, bukan sekadar wacana, namun menjadi kunci yang akan menentukan apakah langkah besar ini berakhir sebagai prestasi atau justru petaka.
Tantangan Infrastruktur Digital
Ibaratkan tugas raksasa untuk mengubah ‘DNA’ seluruh sistem keuangan digital secara bertahap namun terintegrasi. Setiap mesin EDC, aplikasi mobile banking, platform e-commerce, hingga software akuntansi perusahaan harus dikonversi secara serentak ke dalam kode Rupiah yang baru. Ini bukan hanya ganti label, melainkan operasi bypass jantung finansial nasional. Mampukah infrastruktur digital kita yang masih memiliki ketimpangan, bertransformasi dalam satu malam?
Dibalik perubahan kode tersebut, tersembunyi biaya fantastis yang harus ditanggung suatu pihak. Bank dan pelaku usaha akan mengeluarkan dana besar untuk pembaruan sistem, yang pada ujungnya bisa dibebankan kepada konsumen melalui biaya admin atau kenaikan harga. Konsep “there’s no such thing as a free lunch” dari ekonom Milton Friedman (1962) mengingatkan, setiap kebijakan pasti ada yang menanggung biayanya. Lantas, siapkah kita membayar “makan siang” yang tidak murah ini?
Masa transisi di mana uang lama dan baru beredar bersamaan justru menjadi zona bahaya yang paling kritis. Mengutip teori “The Law of Instrument” atau “Maslow’s Hammer” (Abraham Maslow, 1966), di mana jika satu-satunya alat yang ada adalah palu, setiap masalah akan dilihat sebagai paku. Dalam kekacauan transisi, masyarakat akan kesulitan membedakan alat mana yang valid, berpotensi memicu kesalahan hitung dan penipuan. Bukankah kita sedang membuka pintu bagi kekacauan transaksional yang justru ingin kita hindari?
Ujian Literasi dan Psikologi Publik
Ujian pertama terjadi di dalam benak masyarakat, melawan trauma kolektif terhadap kata “pemotongan”. Banyak yang langsung teringat sanering di era Soekarno tahun 1965, di mana uang dipotong nilainya secara paksa. Padahal, redenominasi hanya memotong nominalnya, bukan nilainya, sebagaimana prinsip “Nominal Illusion” yang diulas oleh Eldar Shafir dan Amos Tversky (1997). Namun, bisakah logika mengalahkan memori kelam yang telah berpuluh tahun mengendap?
Tantangan berikutnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari direktur hingga ibu-ibu di pasar tradisional. Teori “Diffusion of Innovations” Everett Rogers (1962) mengingatkan bahwa adopsi inovasi selalu lambat bagi kelompok akhir, yang rentan tertinggal. Kampanye satu arah dari pusat tidak akan memadai; diperlukan pendekatan dari mulut ke mulut yang menyentuh level akar rumput. Bagaimana meyakinkan masyarakat yang terbiasa dengan transaksi konvensional bahwa nilai uang mereka tetap sama, meskipun nominalnya berubah?
Bahaya terbesar justru datang dari kesuksesan itu sendiri, yakni: ilusi bahwa semua barang menjadi sangat murah. Fenomena psikologis “Money Illusion” yang digagas Irving Fisher (1928) memperingatkan bahwa orang cenderung terpaku pada nilai nominal, bukan nilai riil. Persepsi “harga kecil” dapat memicu euforia belanja tidak terkendali, yang justru memanaskan ekonomi dan memicu inflasi. Akankah kita terjebak dalam pesta belanja semu yang berujung pada kenaikan harga yang sangat nyata?
Kerangka Hukum dan Pengawasan
Transisi ini membutuhkan kepastian hukum yang mutlak, bukan hanya regulasi yang setengah hati. Filosofi “the rule of law, not of men” yang dipopulerkan A.V. Dicey (1885) menekankan bahwa semua pihak, dari pemerintah hingga rakyat, harus tunduk pada hukum yang jelas. Tanpa payung hukum yang kokoh dan rinci, ruang untuk penyimpangan dan ketidakadilan akan terbuka lebar. Sudah siapkah kita merancang undang-undang yang mampu mengantisipasi setiap celah keributan di lapangan?
Keberhasilan juga bergantung pada ketegasan para penjaga pasar. Bank Indonesia, OJK, maupun kepolisian harus berfungsi layaknya “the visible hand” yang dikemukakan Oliver E. Williamson (1975), turun tangan aktif mengawasi biaya transaksi dan mencegah pembulatan harga. Tanpa pengawasan yang proaktif dan sanksi yang tegas, niat mulia penyederhanaan bisa berbalik menjadi pesta spekulasi dan penipuan. Mampukah institusi tersebut membangun sistem pengawasan yang mampu meminimalisir ruang bagi penyimpangan?
Namun, otoritas pusat memiliki keterbatasan jangkauan. Di sinilah peran “social accountability” yang dikembangkan World Bank (2000-an), menjadi krusial dengan melibatkan organisasi masyarakat dan LSM sebagai mata dan telinga di lapangan. Kehadiran mereka dapat melaporkan pelanggaran, memantau harga, dan menjadi jembatan komunikasi dengan masyarakat akar rumput. Bukankah partisipasi publik inilah yang akan menjadi tameng terakhir dari kekacauan harga di pasar maupun warung tradisional?
Pelajaran dari Negeri Lain: Kesuksesan dan Kegagalan
Kisah sukses Vietnam menjadi bukti nyata pentingnya persiapan yang matang. Mereka tidak terburu-buru, melainkan menjalani masa transisi panjang selama 9 tahun (2003-2012) dengan edukasi bertahap. Seperti prinsip “the whole is greater than the sum of its parts” dalam teori Gestalt Psychology (Max Wertheimer, 1912), kesuksesan redenominasi Vietnam lahir dari sinergi seluruh elemen masyarakat yang terencana. Sudahkah kita mempelajari pelajaran berharga tentang kesabaran dari negara tetangga ini?
Sebaliknya, Zimbabwe menjadi contoh kelam bagaimana redenominasi dapat berubah menjadi bencana. Kebijakan ini justru diterapkan saat hiperinflasi, tanpa didukung fundamental ekonomi yang kuat. Seperti teori “Gresham’s Law” (Thomas Gresham, 1858), di mana uang yang nilainya buruk mengusir uang yang nilainya baik, kepercayaan publik menjadi punah dan mata uang baru langsung menjadi sampah. Adakah jaminan kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, mengingat kerentanan sistem ekonomi kita?
Inti pelajaran dari kedua negara tersebut sangat jelas. Teori “Credibility Revolution” (Olivier Blanchard, 2014) menyatakan bahwa kebijakan moneter hanya berhasil jika dipercaya publik. Redenominasi bukan hanya operasi teknis, melainkan ujian kredibilitas nasional yang membutuhkan pondasi ekonomi sehat dan modal sosial yang kuat. Bukankah membangun kepercayaan jauh lebih sulit, daripada hanya memangkas angka nol?
Langkah Strategis ke Depan: Prasyarat Kesiapan
Redenominasi bukan hanya proyek prestisius, melainkan operasi nasional yang kompleks. Seperti teori “The Tipping Point” Malcolm Gladwell (2000), kesuksesan kebijakan kritis bergantung pada detail persiapan yang matang di semua lini. Tanpa kesiapan sistemik yang menyeluruh, niat mulia penyederhanaan justru berisiko menjadi bumerang yang dapat memicu kekacauan. Masih relevankah kita memprioritaskan kebijakan ini, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi?
Obsesi pada pertanyaan “kapan” pelaksanaan harus segera dialihkan kepada “bagaimana” mekanisme yang tepat. Filsuf China kuno, Confucius pernah berkata, “The man who moves a mountain begins by carrying away small stones“, kesempurnaan terletak pada persiapan detail kecil. Setiap tahapan dari konversi digital hingga edukasi pedagang kaki lima harus dirancang dengan prinsip keadilan dan transparansi. Bukankah lebih baik menunda demi kesempurnaan, daripada tergesa-gesa dan menuai bencana?
Edukasi berkelanjutan dan grand design yang komprehensif merupakan prasyarat mutlak sebelum kapal redenominasi kita berlayar. Seperti pesan Peter Drucker dalam “The Effective Executive” (1966), “Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things“, kita harus memastikan tidak hanya efisien dalam eksekusi, tapi efektif dalam memilih strategi yang tepat. Maukah kita bersama memulai dari langkah pertama yang benar, sebelum terjerumus dalam lubang kesia-siaan? Oleh karena itu, langkah pertama yang paling strategis dengan membentuk tim independen yang terdiri dari pakar ekonomi, teknologi, dan komunikasi untuk menyusun peta jalan redenominasi secara komprehensif, disertai skenario mitigasi risiko yang matang.
Penulis : Harry Yulianto, Akademisi STIE YPUP Makassar
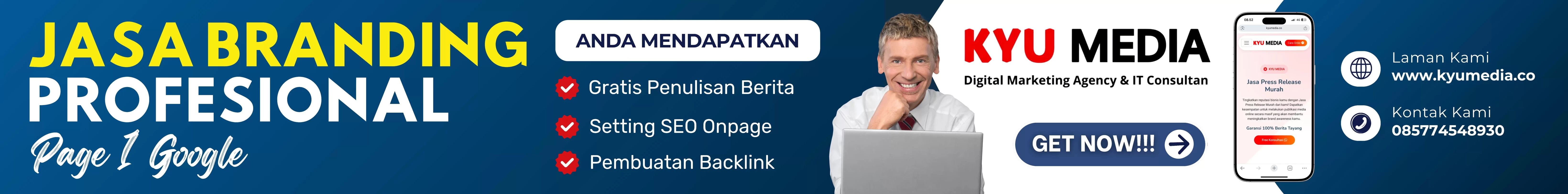

 Insight NTB
Insight NTB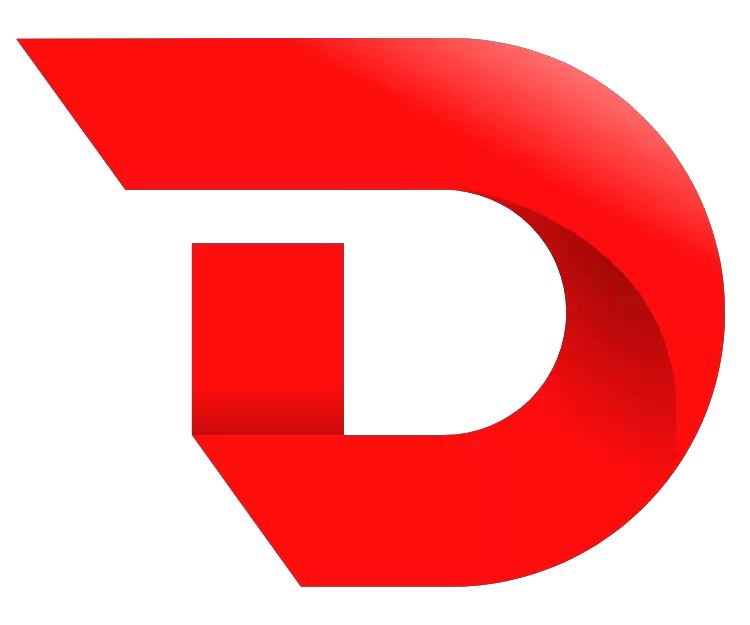 Daily Nusantara
Daily Nusantara Suara Time
Suara Time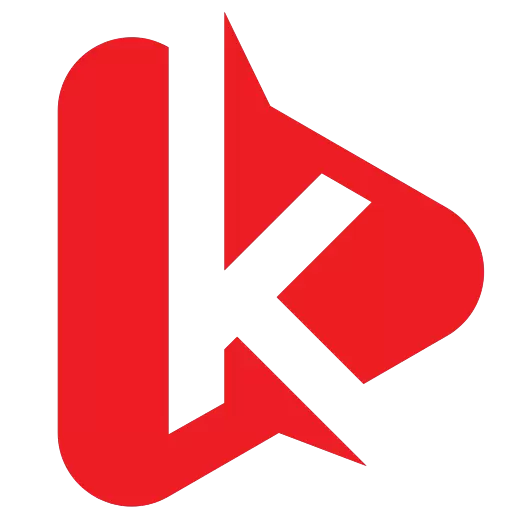 Kabar Tren
Kabar Tren Portal Demokrasi
Portal Demokrasi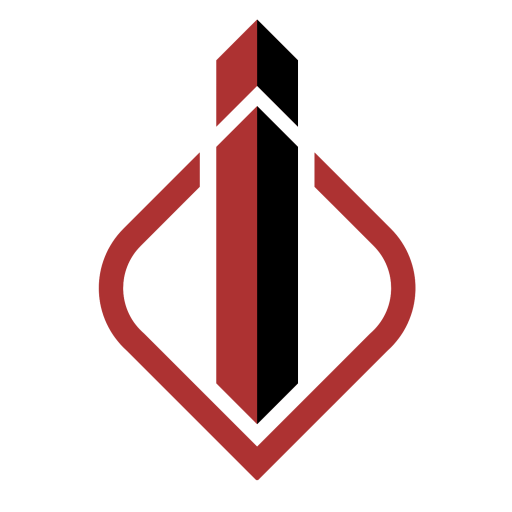 IDN Vox
IDN Vox Lens IDN
Lens IDN Seedbacklink
Seedbacklink