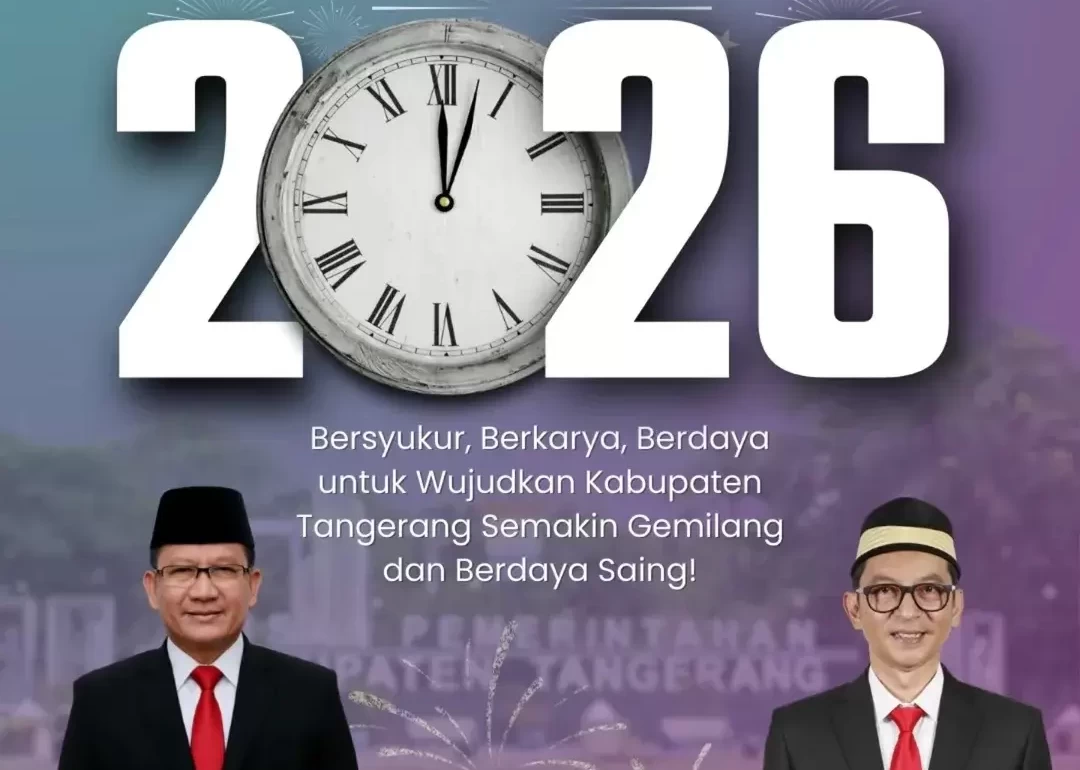Matinya Prinsip Cover Both Side Media dan Distorsi Makna Kyai Pesantren

Editor: Khansa Nadira
Kabar Baru, Opini — Belakangan ini, publik dikejutkan oleh tayangan Xpose Uncensored Trans7 yang menggambarkan kehidupan pesantren dan sosok kyai dalam bingkai yang keliru dan merendahkan.
Dalam tayangan itu, muncul adegan santri yang bersikap sangat hormat kepada kyai, hingga disertai komentar bahwa tradisi tersebut merupakan bentuk feodalisme dan relasi sosial yang timpang.
Bahkan muncul pernyataan bahwa kyai yang kaya seharusnya memberi amplop kepada santri, bukan sebaliknya.
Narasi semacam ini segera memicu protes luas dari warga Nahdlatul Ulama, alumni pesantren, dan masyarakat luas yang memahami nilai luhur tradisi kepesantrenan.
Mereka menilai tayangan itu tidak hanya melecehkan figur kyai, tetapi juga mengaburkan makna adab, tabarruk, dan penghormatan yang menjadi inti pendidikan pesantren.
Masalah utama dari tayangan semacam ini bukan sekadar persoalan etika jurnalistik, tetapi lebih dalam lagi menyangkut kesesatan berpikir yang lahir dari ketidakpahaman terhadap konteks sejarah dan budaya pesantren.
Media mainstream, dalam logika pencarian sensasi dan rating, sering kali tergelincir pada kesalahan mendasar, mereduksi tradisi yang luhur menjadi tontonan yang dangkal.
Penghormatan santri kepada kyai, yang dalam khazanah pesantren dipahami sebagai ekspresi adab dan spiritualitas, direduksi menjadi simbol feodalisme dan transaksi sosial.
Cara pandang seperti ini mencerminkan cara berpikir yang miskin konteks, di mana logika modernitas yang serba rasional dan transaksional diterapkan secara sembrono terhadap tradisi yang bersifat spiritual dan simbolik.
Dalam dunia pesantren, hubungan antara santri dan kyai tidak dibangun atas dasar materi, tetapi atas dasar adab, ilmu, dan keberkahan.
Istilah tabarruk mencari keberkahan dari guru bukan berarti menjadikan kyai sebagai sosok yang harus disembah, melainkan menegaskan bahwa ilmu dan keteladanan seorang guru membawa pengaruh rohaniah bagi muridnya.
Santri memberi amplop atau hadiah bukan karena relasi kuasa, tetapi sebagai bentuk rasa syukur dan cinta.
Penghormatan secara fisik, seperti menunduk atau bersikap sopan, bukanlah tanda penindasan, melainkan pengakuan bahwa ada sesuatu yang suci dalam proses belajar, yaitu keberkahan ilmu yang tidak bisa dibeli atau dipertukarkan
Kesalahan lain yang sering dilakukan media adalah menggeneralisasi. Beberapa adegan dipilih secara sepihak, diambil dari konteks parsial, lalu digeneralisasi sebagai cerminan seluruh dunia pesantren.
Padahal, pesantren di Indonesia sangat beragam, ada yang tradisional, modern, hingga pesantren berbasis teknologi. Masing-masing memiliki tradisi dan sistem yang khas.
Mengambil satu potongan realitas lalu mengklaimnya sebagai gambaran keseluruhan adalah bentuk penyederhanaan yang menyesatkan.
Inilah bentuk kesesatan berpikir kedua yang muncul: menyamakan keberagaman tradisi spiritual dengan satu pola yang tampak ekstrem di layar kaca.
Sejarah mencatat bahwa pesantren telah menjadi benteng moral, pusat penyebaran Islam, dan lembaga pendidikan yang melahirkan ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin bangsa.
Pesantren adalah ruang di mana ilmu, adab, dan spiritualitas bertemu. Di sana, seorang santri diajarkan untuk menghargai proses, menundukkan ego, dan menata hati.
Dalam konteks itu, penghormatan terhadap kyai bukanlah bentuk penindasan, tetapi sebuah latihan batin untuk memuliakan ilmu dan menundukkan hawa nafsu.
Jika media gagal memahami esensi ini, maka yang terjadi adalah distorsi makna dan pelanggengan stereotip bahwa pesantren adalah ruang keterbelakangan.
Tanggung jawab media mestinya lebih besar dari sekadar mengejar perhatian publik. Media memiliki kewajiban etis untuk memahami konteks sosial-budaya sebelum menayangkan isu sensitif, apalagi menyangkut lembaga keagamaan dan nilai tradisi.
Kritik tentu sah dan perlu, tetapi harus disampaikan dengan perspektif yang adil dan riset yang memadai. Menghadirkan narasumber yang kompeten, memahami terminologi khas pesantren seperti tabarruk, adab, dan keberkahan, serta menempatkan praktik budaya dalam konteks spiritualitas Islam adalah langkah minimal yang seharusnya dilakukan.
Kasus tayangan Trans7 ini mestinya menjadi pelajaran penting bagi media massa di Indonesia.
Di era digital yang penuh kompetisi, etika penyiaran dan tanggung jawab sosial tidak boleh dikorbankan atas nama sensasi. Logika rating tidak boleh menyingkirkan logika moral.
Pesantren bukanlah komoditas hiburan; ia adalah institusi peradaban yang telah berabad-abad menjadi bagian dari identitas bangsa.
Menyalahartikan tradisinya berarti memutus ingatan kolektif bangsa terhadap nilai-nilai luhur yang membentuk wajah Islam Indonesia—Islam yang beradab, santun, dan moderat.
Kita berharap, ke depan, media mainstream lebih berhati-hati dalam menarasikan dunia pesantren. Bukan dengan memolesnya secara romantik, tetapi dengan menampilkan keseimbangan antara fakta dan nilai. Pesantren perlu dilihat bukan sebagai fenomena eksotik atau relik masa lalu, melainkan sebagai ruang hidup yang terus beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan akar spiritualnya.
Media harus belajar menghormati cara berpikir dan cara hidup yang berbeda, terutama yang bersumber dari tradisi panjang keilmuan Islam Nusantara. Karena ketika media gagal memahami adab, maka yang terjadi bukan hanya kesalahan informasi, tetapi juga penghancuran makna.
Pesantren tidak memerlukan pembelaan emosional; ia telah berdiri kokoh lebih dari seribu tahun dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara.
Yang perlu diperbaiki adalah cara pandang media yang tergesa-gesa menilai tanpa memahami, yang melihat hormat sebagai tunduk, dan keberkahan sebagai transaksi.
Itulah telikungan berpikir yang sesat, kesalahan mendasar yang lahir dari arogansi modernitas terhadap tradisi. Dan selama media masih terjebak dalam pola pikir seperti itu, mereka akan terus gagal memahami kebijaksanaan yang hidup di balik dinding-dinding pesantren.
Penulis adalah Mohammad Iqbalul Rizal Nadif, Pengurus PB PMII
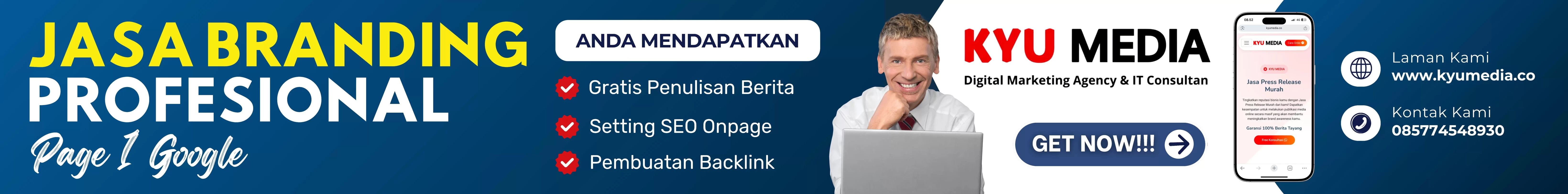

 Insight NTB
Insight NTB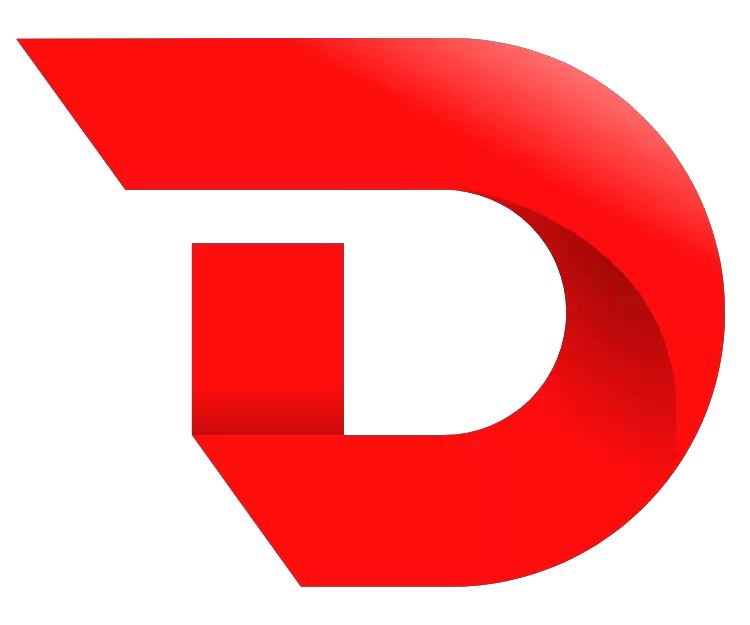 Daily Nusantara
Daily Nusantara Suara Time
Suara Time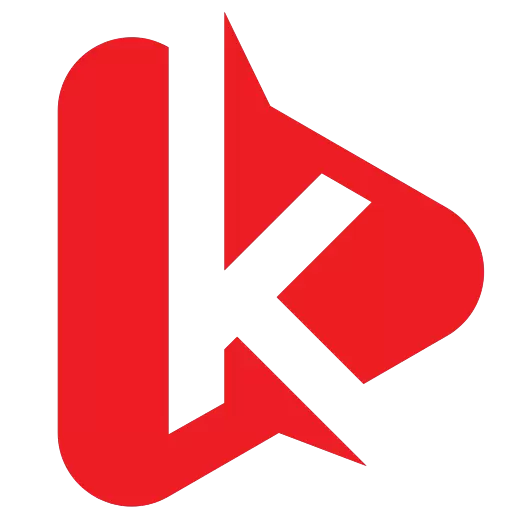 Kabar Tren
Kabar Tren Portal Demokrasi
Portal Demokrasi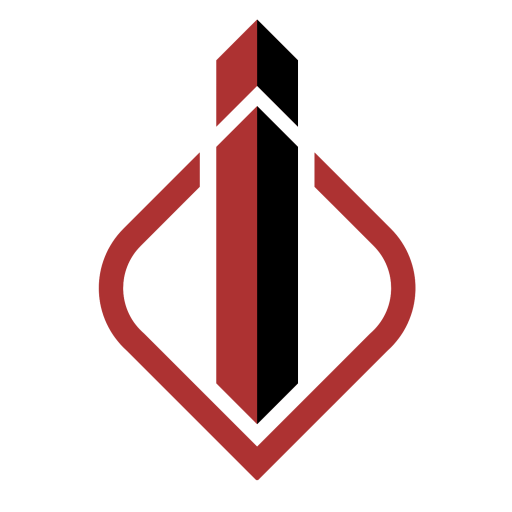 IDN Vox
IDN Vox Lens IDN
Lens IDN Seedbacklink
Seedbacklink