Dari Masjid ke Pabrik: Etos Baru Ekonomi Turki

Editor: Khansa Nadira
Kabar Baru, Opini — Seratus tahun lalu, Turki dikenal sebagai “orang sakit Eropa”—julukan sinis Barat bagi Kekaisaran Ottoman menjelang keruntuhannya. Kini, seratus tahun kemudian, Turki kembali mencuri perhatian. Bukan karena kejatuhannya, melainkan karena kebangkitannya. Negeri yang dulu menjadi pusat khilafah Islam kini tampil sebagai negara industri menengah dengan ekonomi dinamis, teknologi mandiri, dan diplomasi yang percaya diri. Dalam dua dekade terakhir, Turki berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi regional yang disegani.
Pertanyaannya: apakah kebangkitan ekonomi Turki sekadar cerita pembangunan nasional, atau tanda kebangkitan baru dalam pandangan dunia Islam?
Awal abad ke-21, Turki hampir runtuh. Krisis keuangan 2001 membuat inflasi menembus 70 persen dan sistem perbankan kolaps. Namun, dari situ justru lahir momentum kebangkitan. Ketika Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berkuasa pada 2002, pemerintah melakukan reformasi struktural besar-besaran: menata fiskal, menekan utang luar negeri, dan mendorong wirausaha kecil-menengah. Hasilnya luar biasa. Dalam satu dekade, produk domestik bruto meningkat tiga kali lipat, ekspor melonjak dari 36 miliar dolar AS menjadi lebih dari 150 miliar, dan sektor industri, otomotif, tekstil, teknologi pertahanan, menjadi tulang punggung ekonomi. Namun, keberhasilan ini tidak hanya lahir dari kebijakan ekonomi. Ia juga ditopang oleh etos baru: semangat kerja yang berakar pada nilai Islam; disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai amanah.
“Macan Anatolia” dan Etika Kerja Muslim
Pertumbuhan ekonomi Turki tidak hanya digerakkan oleh korporasi besar di Istanbul, tetapi oleh para pengusaha daerah yang religius di Anatolia Tengah—Kayseri, Konya, Gaziantep. Mereka dijuluki Anatolian Tigers: kelompok wirausahawan Muslim yang menggabungkan semangat kapitalisme modern dengan moralitas Islam. Mereka berbisnis bukan sekadar mencari laba, melainkan menanam nilai keberkahan (barakah).
Kultur ini mencerminkan pandangan dunia Islam tentang ekonomi. Dalam Islam, kekayaan bukan tujuan, melainkan amanah yang harus dikelola adil dan memberi manfaat bagi sesama. Prinsip tawhid (keesaan Tuhan) menuntut keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara efisiensi dan etika. Maka, ketika kerja dipahami sebagai ibadah, produktivitas bukan lagi semata tuntutan ekonomi, tapi juga panggilan spiritual. Di sinilah letak keunikan kebangkitan Turki.
Ekonomi sebagai Jalan Peradaban
Turki modern tidak menolak modernitas, tetapi menolak kehilangan jati diri di tengahnya. Setelah masa sekularisasi keras di era Mustafa Kemal Atatürk, kini muncul upaya untuk menyatukan kembali agama dan pembangunan.
Ekonomi menjadi alat untuk membangun martabat bangsa, bukan sekadar mesin pertumbuhan. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan cendekiawan Muslim Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi tentang unity of knowledge—integrasi antara wahyu dan akal, antara iman dan ilmu.
Pemerintah Turki mendorong industri bernilai tambah tinggi dan investasi di bidang teknologi. Dari kendaraan listrik hingga drone militer Bayraktar yang diekspor ke lebih dari 30 negara, Turki membangun kemandirian teknologi dengan semangat nasionalisme religius.
Ekonomi, dalam konteks ini, menjadi wujud jihad produktif—perjuangan untuk mencapai kemandirian dan kemuliaan bangsa tanpa meninggalkan nilai keadilan.
Antara Spirit dan Kekuasaan
Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, Turki memadukan politik Islam moderat dengan nasionalisme modern. Masjid dan pabrik tumbuh beriringan, doa dan produksi berjalan seirama. Namun, kebangkitan ini tidak lepas dari paradoks. Kritik terhadap otoritarianisme dan ketimpangan sosial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup. Pandangan dunia Islam mengajarkan keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan, antara pembangunan dan pemerataan.
Turki kini menghadapi tantangan baru: inflasi tinggi, pelemahan mata uang lira, dan jurang ekonomi yang melebar antara kota dan desa. Di sinilah ujian sejati kebangkitan itu—apakah ia akan bertahan sebagai kebijakan moral, atau sekadar menjadi kapitalisme baru dengan cita rasa religius.
Moralitas di Tengah Modernitas
Dalam Islam, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi dari keberkahan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa “bukan kekayaan yang membuat seseorang kaya, melainkan hati yang merasa cukup.”
Turki berusaha menyeimbangkan modernitas dengan spiritualitas. Di banyak kota, pusat industri baru berdiri tak jauh dari masjid-masjid besar. Pekerja menunaikan salat berjamaah di sela jam kerja. Suasana ini menggambarkan harmoni antara iman dan produktivitas.
Etika Islam memberi fondasi moral yang kuat: kerja keras tidak boleh mengorbankan keadilan, dan kemajuan ekonomi harus membawa kemaslahatan sosial. Prinsip ini menjadi pembeda antara ekonomi berbasis nilai dan ekonomi yang sekadar mengejar angka.
Pelajaran bagi Dunia Islam
Kebangkitan ekonomi Turki mengandung pelajaran penting bagi dunia Islam. Banyak negara Muslim kaya sumber daya alam, tetapi miskin dalam visi pembangunan. Turki menunjukkan bahwa iman dan rasionalitas bisa berjalan bersama.
Fazlur Rahman pernah menulis bahwa umat Islam membutuhkan “rekonstruksi intelektual” agar nilai wahyu dapat diterjemahkan ke dalam konteks modern. Malik Bennabi menambahkan, kebangkitan bangsa Muslim baru akan terjadi ketika mereka mengubah mentalitas konsumtif menjadi produktif.
Turki, dengan segala kelebihannya dan kekurangannya, sedang menjalani proses itu. Ia berusaha membangun sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika; tidak hanya modern, tetapi juga bermakna.
Menjemput Peradaban Baru
Dari masjid ke pabrik, Turki menunjukkan bahwa agama dan kemajuan bukan dua kutub yang berlawanan. Iman bisa menjadi energi produksi; spiritualitas bisa menuntun modernitas. Kebangkitan ini tentu belum sempurna. Tantangan ekonomi dan politik masih panjang. Tetapi arah geraknya jelas: menuju model pembangunan yang berpijak pada moralitas, nasionalisme, dan kemandirian.
Penulis adalah Muhamad Syahrus Sobirin, Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Kajian dan Stratejik Global, Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia.
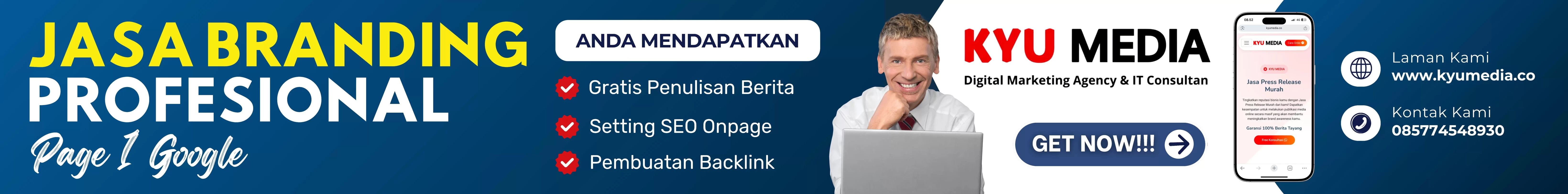

 Insight NTB
Insight NTB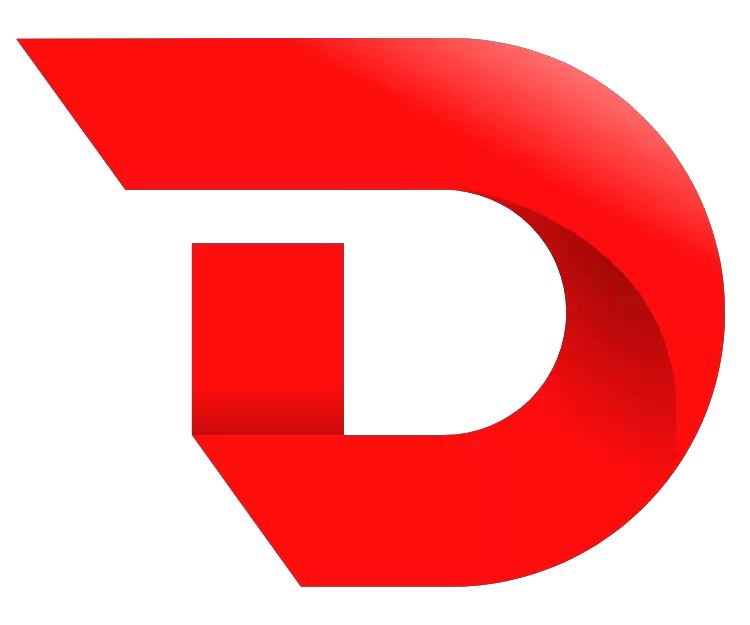 Daily Nusantara
Daily Nusantara Suara Time
Suara Time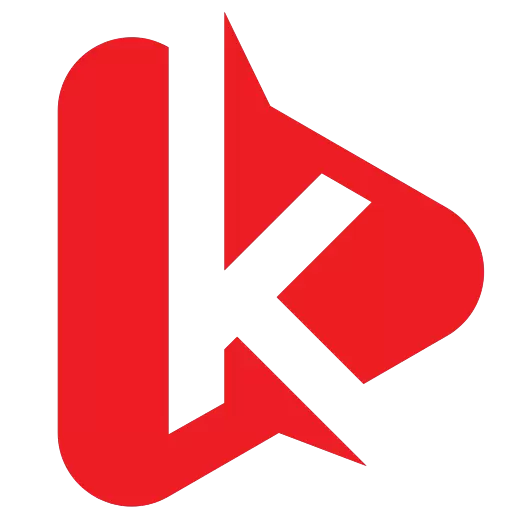 Kabar Tren
Kabar Tren Portal Demokrasi
Portal Demokrasi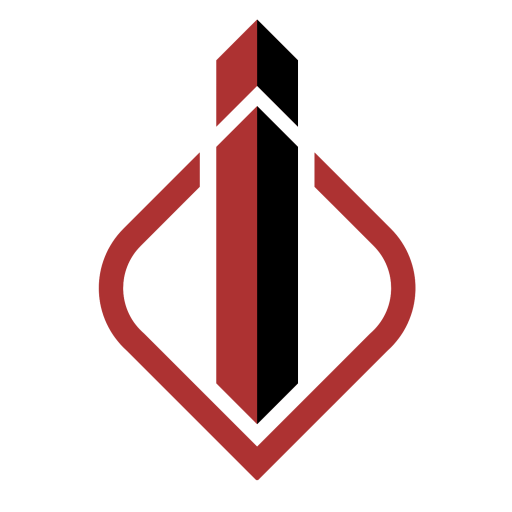 IDN Vox
IDN Vox Lens IDN
Lens IDN Seedbacklink
Seedbacklink





















