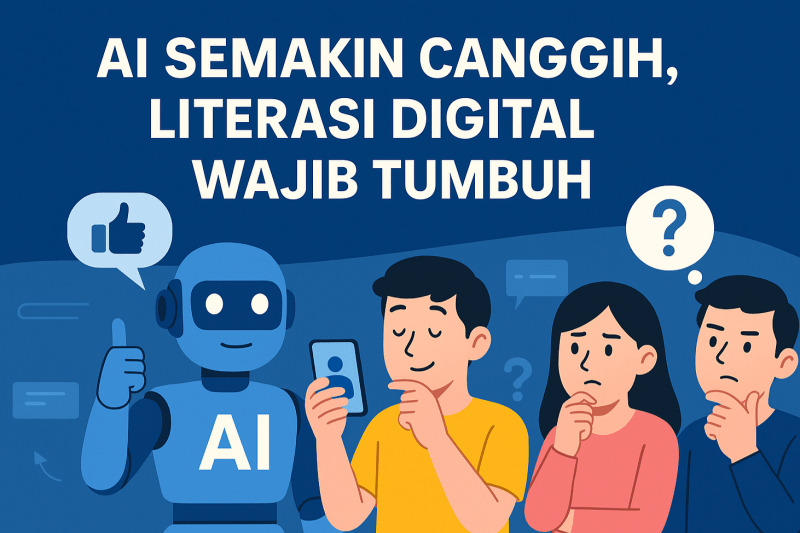Kagetan atas Humor: Potret Krisis Literasi Presidium Angkatan Muda NU

Editor: Khansa Nadira
Kabarbaru – Tulisan ini saya tujukan kepada Rizki Abdul Rahman Wahid, sosok yang mengatasnamakan diri sebagai Presidium Angkatan Muda NU, yang kemarin melaporkan Pandji Pragiwaksono ke polisi akibat materi stand up comedy-nya di forum Mens Rea. Dalih yang digunakan adalah bahwa lelucon Pandji dinilai merendahkan, memfitnah, menimbulkan kegaduhan di ruang publik, dianggap berpotensi memecah belah bangsa, bahkan menimbulkan keresahan, khususnya bagi kalangan muda Nahdliyin.
Terus terang, saya sangat heran. Bukan semata karena pelaporannya saja, melainkan karena kemarahan yang begitu cepat, reaktif, dan berujung pada kriminalisasi ekspresi. Rasa penasaran itulah yang kemudian membawa saya untuk mencari tahu: siapa sebenarnya Rizki Abdul Rahman Wahid ini? Mengapa sebuah jokes yang konteksnya jelas berada di forum komedi ia tanggapi sedemikian rupa?
Setelah saya searching, beberapa hal justru membuat saya tersenyum geli. Dari nama si pelapor, langsung mentriger ingatan saya keseseorang tokoh besar yang juga dari kalangan kita, KH. Abdurrahman Wahid—Gus Dur—Presiden Republik Indonesia ke-4, mantan Ketua Umum PBNU, sekaligus tokoh NU yang dikenal luas sebagai maestro humor. Gus Dur bukan hanya piawai melontarkan jokes, tetapi menjadikan humor sebagai instrumen kritik sosial, politik, bahkan teologis. Tak heran jika banyak tokoh kemudian menulis dan mengarsipkan humor-humor Gus Dur dalam bentuk buku. Dari sanalah kita belajar satu hal penting: kritik paling tajam sering kali justru datang dari gelak tawa, bukan dari teriakan.
Di titik ini, saya teringat ungkapan orang Madura: “orengah tak koat ka nyamannah”–manusianya tidak kuat atas namanya. Ungkapan ini lazim dipakai untuk menyindir seseorang yang besar namanya, tetapi kecil kelapangan pikirannya. Maaf jika terdengar keras, tetapi dalam konteks ini, rasanya cukup relevan.
Rasa penasaran saya pun berlanjut. Allah karim, tak lama kemudian saya menemukan akun Instagram yang bersangkutan. Foto profilnya mengenakan almamater PMII. Artinya terang: ia adalah kader PMII. Sekilas, saya mengangguk—ohh, cocok. Dalam tradisi intelektual, saling kritik di antara sesama kader PMII adalah hal yang lumrah, bahkan niscaya. Kritik bukan barang haram; ia justru vitamin bagi dialektika kaderisasi.
Namun, alih-alih mereda, kegelisahan saya justru kian memuncak. Bagaimana mungkin seseorang yang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Angkatan Muda NU, yang ternyata juga kader PMII—organisasi yang lahir dari rahim tradisi kritis dan kebebasan berpikir—ketika berhadapan dengan jokes bernuansa kritik terhadap pemerintah atau institusi negara, respons refleksnya bukan dialog, bukan bantahan intelektual, melainkan laporan polisi?
Di titik inilah pertanyaan itu tak lagi sederhana. Ia menjelma menjadi kegelisahan ideologis: sedang berada di mana nalar kritis yang selama ini dielu-elukan dalam forum-forum kaderisasi? Dan sejak kapan ketidaknyamanan terhadap kritik diselesaikan dengan kriminalisasi, bukan dengan adu gagasan?
Dari situ, saya menarik satu kesimpulan yang barangkali pahit, tetapi sulit dihindari: besar kemungkinan yang bersangkutan tidak pernah benar-benar membaca—atau setidaknya mempelajari—pemikiran dan gaya komunikasi tokoh-tokoh NU dan PMII itu sendiri. Ia tampak asing dengan tradisi intelektual rumahnya sendiri.
Mari kita jujur. NU memiliki sejarah panjang dalam merawat kritik melalui humor. Gus Dur adalah contoh paling gamblang. Bagi Gus Dur, humor adalah cara paling manusiawi untuk membongkar kekuasaan yang pongah, kebijakan yang timpang, serta moral publik yang munafik. Ia menertawakan dirinya sendiri, keluarganya, NU, bahkan presidennya. Sebab bagi Gus Dur, humor adalah bentuk kecerdasan, bukan ancaman bagi persatuan.
Begitu pula Mahbub Djunaidi, Ketua Umum PB PMII pertama. Ia adalah jurnalis, pemikir, sekaligus aktivis HAM yang menjadikan satire sebagai senjata utama. Mahbub mengkritik negara, militer, dan elit politik bukan dengan makian kosong, melainkan dengan kelakar yang membuat pembaca tertawa sekaligus tersadar. Dalam karya-karyanya—Kolom Demi Kolom, Asal Usul, Angin Musim, dan berbagai tulisan lainnya—Mahbub menunjukkan bahwa kritik tidak harus galak untuk menjadi radikal. Kritik bisa jenaka, cair, dan tetap menghantam tepat sasaran.
Komitmen Mahbub terhadap hak asasi manusia pun sangat kentara dalam pelbagai tulisan-tulisannya. Ia tidak berhenti pada keluhan atau sekadar menunjuk masalah, tetapi mengajak pembaca berpikir, merefleksi, bahkan bercermin. Inilah tradisi PMII yang sesungguhnya: kritis, berjarak dengan kekuasaan, tetapi tetap beradab dan berbudaya.
Karena itu, sungguh miris menyaksikan polah sebagian angkatan muda hari ini—minim literasi, tetapi penuh keberanian semu. Sedikit-sedikit merasa paling nasionalis, paling menjaga persatuan, lalu sibuk mencari muka dengan gaya sok pahlawan di hadapan pemerintah. Padahal, pada akhirnya, yang terjadi justru mempermalukan diri sendiri dan, lebih jauh lagi, mencoreng citra jam’iyyah.
Saya ini NU kultural sejak dalam kandungan—maklum, saya orang Madura—dan juga kader PMII Jember. Dari posisi itu, saya bisa membaca arah dan maksud dari tindakan semacam ini. Dan sungguh, bok ya jangan kebangetan. Jangan membawa-bawa nama NU hanya untuk menjustifikasi reaksi kagetan terhadap kritik yang dibungkus komedi.
Perlu diingat, apa yang disampaikan Pandji di ruang publik adalah bagian dari hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Lagi pula, materi stand up yang ia bawakan bukan barang baru. Ia sudah lama menjadi perbincangan publik dan dinarasikan berulang kali oleh media arus utama seperti Tempo, Kompas, dan lainnya. Jika ingin berbeda pendapat, silakan. Tetapi kriminalisasi ekspresi jelas bukan solusi.
Jika konten tersebut masih berada dalam koridor komedi ala stand up, maka problem utamanya sejatinya bukan terletak pada muatan kritik atau pada siapa objek kritik itu diarahkan. Persoalannya justru berada pada cara pandang dan tingkat literasi humor kita sendiri yang bermasalah. Tidak setiap kritik harus disikapi dengan pasal, apalagi diakhiri dengan laporan polisi.
Gus Dur pernah berujar—kurang lebih—bahwa humor tertinggi adalah kemampuan menertawakan diri sendiri. Bukan hanya kekurangan dan keburukan, melainkan juga ironi serta paradoks yang melekat pada diri, keluarga, daerah, bahkan negara.
Di titik itulah sesungguhnya kedewasaan publik diuji. Apakah kita cukup lapang untuk merespons kritik dengan nalar dan dialog, atau justru tergelincir pada kecenderungan membungkam melalui instrumen hukum. Humor, dalam konteks ini, bukan ancaman bagi wibawa negara, melainkan cermin untuk menguji sejauh mana demokrasi dan kebebasan berpikir masih diberi ruang untuk bernapas.
Maka, saran saya kepada Sahabat Rizki Abdul Rahman Wahid, sebelum sibuk melapor ke aparat, ada baiknya belajar kembali. Belajar tentang pemikiran dan gaya komunikasi para tokoh NU dan PMII. Kenali corak berpikir mereka. Pelajari bagaimana mereka berdialog dengan kekuasaan dan publik—yang hampir selalu dibalut humor, satire, dan kelakar. Sebab mereka paham betul, kritik yang paling berbahaya bagi kekuasaan adalah kritik yang membuat orang tertawa, lalu berpikir.
Sebagai penutup, izinkan saya mengingatkan satu pepatah para aktivis yang terasa sangat relevan hari ini: “Jika kau ingin menyampaikan kebenaran kepada seseorang, sampaikanlah dengan tawa sambil sedikit menari. Sebab tanpa itu, untaian katamu akan menjelma pedang yang tajam, dan ia mungkin akan membunuhmu dengan cara membabi buta tanpa ampun.”
Penulis adalah Nor Khamila Pengurus Kordinator Cabang Kopri Jawa Timur


 Insight NTB
Insight NTB Suara Time
Suara Time Lens IDN
Lens IDN Daily Jogja
Daily Jogja Jalan Rakyat
Jalan Rakyat Idealita News
Idealita News AYO Nusantara
AYO Nusantara Seedbacklink
Seedbacklink