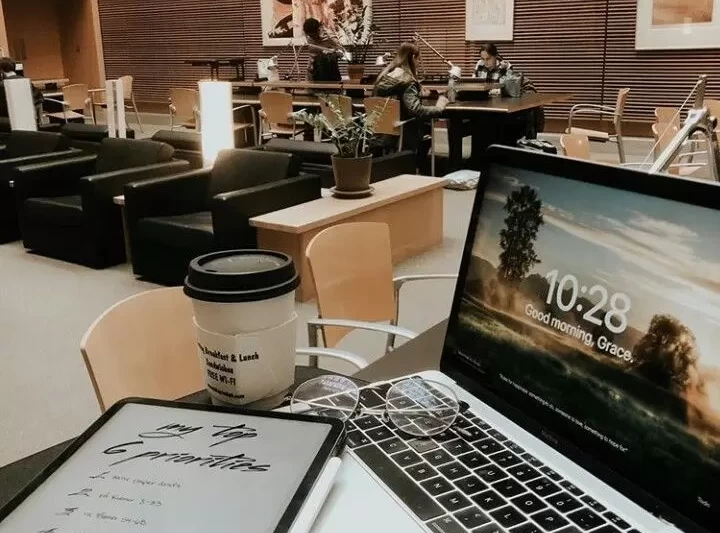Mitos Dua Periode yang Tak Pernah Tuntas: Ironi Demokrasi di Bumi Reyog

Editor: Khansa Nadira
Kabar Baru, Opini — Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada 7 November 2025, kembali mengguncang panggung politik daerah. OTT yang menjerat sang bupati karena dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo bukan sekadar kasus hukum biasa, tetapi juga babak baru dari drama panjang politik Ponorogo yang seakan dikutuk oleh “mitos dua periode”. Kasus ini menandai ironi besar: ketika seorang pemimpin yang sempat dianggap berhasil mematahkan mitos tersebut justru harus tumbang bukan karena kekalahan politik, melainkan karena jerat hukum.
Sejak pemilihan kepala daerah digelar secara langsung oleh rakyat, Ponorogo memang dikenal dengan dua mitos politik yang tak kalah kuat dari realitas sosialnya. Pertama, mitos “dua periode” yang menyebut tak ada satu pun bupati yang mampu menjabat dua kali berturut-turut. Sejak era Bupati Muhadi Suyono, kemudian Bapak Amin, hingga H. Ipong Muchlisoni, semua berhenti di periode pertama. Kedua, mitos “etan–kulon kali”, yang membelah Ponorogo secara sosial dan geografis. Wilayah timur dan barat Sungai Sekayu dianggap bergantian melahirkan pemimpin. Dua mitos ini hidup di benak masyarakat dan seolah menjadi hukum tak tertulis dalam politik lokal.
Mitos itu sempat dianggap patah pada Pilkada 2024 ketika Sugiri Sancoko kembali dipercaya rakyat untuk memimpin Ponorogo bersama Lisdyarita. Kemenangan itu disebut banyak pihak sebagai sinyal perubahan, sebagai pembuktian bahwa masyarakat telah dewasa dalam berdemokrasi dan mulai meninggalkan “kutukan” politik masa lalu. Namun ironi muncul ketika kepemimpinan periode keduanya belum genap setahun, Sugiri harus berurusan dengan KPK akibat dugaan korupsi terkait mutasi dan promosi jabatan. Publik pun kembali dihadapkan pada kenyataan pahit: mitos dua periode mungkin tak terbantahkan bukan karena kekuatan mistis, melainkan karena lemahnya integritas dan tata kelola pemerintahan di tubuh kekuasaan lokal itu sendiri.
Kasus ini menegaskan bahwa dalam politik lokal, mitos dan realitas sering kali berjalan berdampingan. Mitos lahir dari pengalaman kolektif masyarakat; ia menjadi semacam cermin yang merekam pola kekuasaan dan harapan rakyat. Ketika masyarakat Ponorogo meyakini bahwa tak ada bupati yang bisa dua kali menjabat, sejatinya itu refleksi atas rasa ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan yang terlalu lama berkuasa, terhadap kekhawatiran bahwa kekuasaan yang bertahan lama akan menimbulkan penyimpangan. Dengan kata lain, mitos dua periode adalah bentuk “kearifan lokal” yang lahir dari pengalaman sosial, sebuah peringatan halus bahwa kekuasaan terlalu lama di tangan orang yang sama cenderung membawa petaka.
Namun, alih-alih menjadikannya pelajaran moral, banyak elite politik justru menganggap mitos itu tantangan untuk ditaklukkan, bukan peringatan untuk direnungkan. Ketika petahana berhasil melanjutkan kekuasaan ke periode kedua, yang muncul bukan semangat memperkuat tata kelola pemerintahan, tetapi euforia politik dan upaya mengonsolidasikan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, ruang-ruang moral dan etika birokrasi sering kali dikorbankan. Rotasi jabatan, mutasi, dan promosi yang seharusnya menjadi instrumen meritokrasi malah disulap menjadi alat transaksi politik. OTT KPK di Ponorogo seolah menjadi penanda bahwa demokrasi lokal masih terjebak pada mentalitas lama, bahwa kekuasaan adalah ruang dagang, bukan ruang pengabdian.
Ironi ini menampar wajah demokrasi kita. Demokrasi lokal yang seharusnya menjadi fondasi bagi lahirnya pemerintahan bersih justru berubah menjadi arena perebutan kepentingan. Pilkada langsung yang dimaksudkan untuk mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya malah melahirkan politik biaya tinggi, yang pada akhirnya memaksa pejabat terpilih mencari “balik modal”. Mitos dua periode mungkin terlihat klenik, tetapi justru menjadi metafora dari siklus kegagalan moral para penguasa daerah: setiap pergantian rezim membawa janji perubahan, namun selalu berakhir dengan kekecewaan.
Ponorogo kini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, publik tentu lelah dengan stigma “kabupaten kutukan dua periode”. Disisi lain, peristiwa OTT ini memperlihatkan bahwa mitos tersebut masih hidup karena realitasnya tak pernah berubah. Untuk keluar dari lingkaran ini, dibutuhkan lebih dari sekadar pemimpin baru. Diperlukan sistem pengawasan yang kuat, transparansi dalam birokrasi, serta partisipasi publik yang aktif. Demokrasi lokal hanya akan sehat jika rakyat tidak hanya memilih setiap lima tahun, tetapi juga mengawasi setiap hari.
Kasus OTT Bupati Ponorogo harus menjadi pelajaran kolektif bahwa kekuasaan tanpa integritas adalah jalan cepat menuju kehancuran. Rakyat Ponorogo tidak hanya butuh pemimpin yang mampu menaklukkan mitos, melainkan pemimpin yang mampu menegakkan kepercayaan. Karena pada akhirnya, mitos bisa saja dipatahkan, tetapi luka integritas terhadap amanah publik akan sulit disembuhkan.
Penulis adalah Mohammad Iqbalul Rizal Nadif. S. Sos., MPA., Pengurus PB PMII.
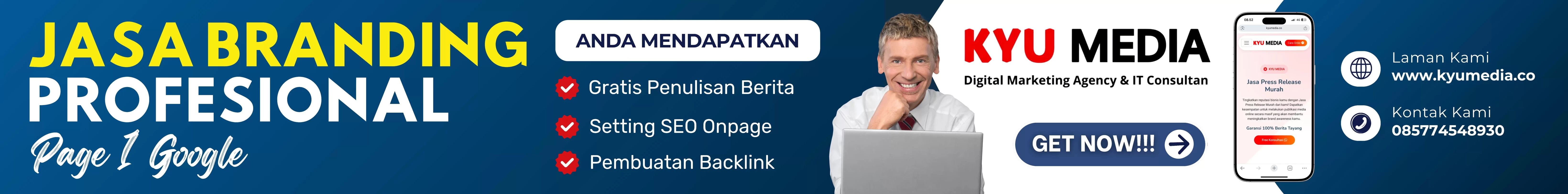

 Insight NTB
Insight NTB Suara Time
Suara Time Lens IDN
Lens IDN Daily Jogja
Daily Jogja Jalan Rakyat
Jalan Rakyat Idealita News
Idealita News AYO Nusantara
AYO Nusantara Seedbacklink
Seedbacklink