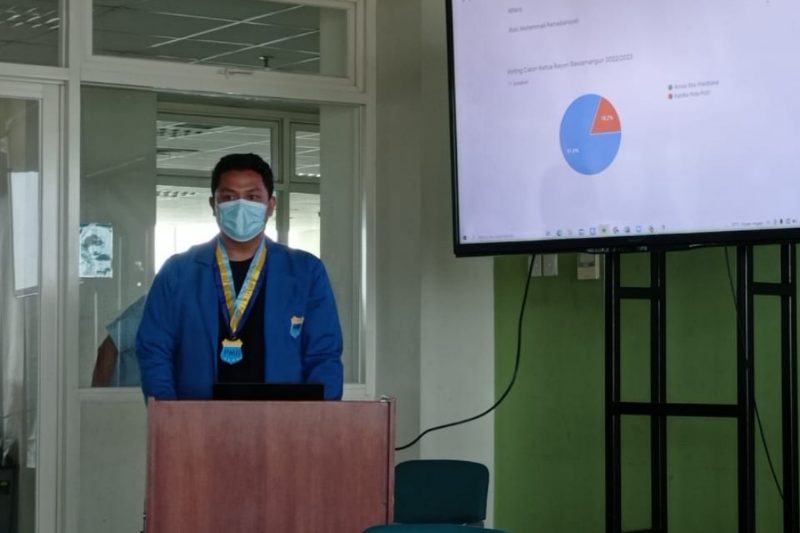Iran Menendang Meja, Israel Porak Poranda, Amerika Terpaksa Mengelus Dada

Jurnalis: Bagaskara Dwy Pamungkas
Oleh: Adil Satria Putra (KETUM PC PMII JEMBER 2017-2018)
Kabarbaru – Ada kalanya dunia ini mirip pasar malam: gemerlap lampu warna-warni, dentuman musik, tawa anak-anak, dan pedagang teriak-teriak memikat pembeli. Tapi seperti biasa, di balik tenda sirkus dan pertunjukan akrobatik, ada yang sedang mengasah pedang, merangkai amarah, dan menulis ulang skenario konflik dunia. Timur Tengah adalah panggung sirkus yang tak pernah benar-benar selesai dengan dramanya—dan Iran, baru saja memutuskan bahwa kali ini, mereka tidak lagi jadi penonton atau badut. Mereka ingin jadi pemain utama.
Perang dua belas hari antara Iran dan Israel, dengan Amerika duduk di bangku sutradara yang gelisah, adalah episode terbaru dari serial panjang konflik penuh kepalsuan, retorika suci, dan darah warga sipil. Namun yang menarik, episode kali ini punya plot twist: sang jagoan tua—Israel—tampil ngos-ngosan. Rudal-rudal Iran yang selama ini diremehkan sebagai “kembang api negara terisolasi”, kini berubah jadi pesan balistik yang tak bisa diabaikan. Mereka meluncur ke jantung-jantung strategis Israel, bukan sekadar untuk menggertak, tapi untuk berkata: “Kami sudah cukup bersabar.”
Dan memang, Iran tidak datang dengan mulut berbusa atau spanduk revolusioner. Mereka datang dengan kalkulasi, presisi, dan kepercayaan diri. Sementara itu, Israel yang biasanya lihai memoles citra sebagai korban sambil memegang senjata paling canggih di kawasan, kali ini terlihat repot sendiri—berlari-lari antara ruang bunker dan ruang siaran pers. Mereka meradang, tapi ragu. Marah, tapi mengintip respons Washington. Dan Amerika? Ah, negeri Paman Sam itu mendadak berubah jadi paman yang canggung di tengah pesta keluarga: ingin menengahi, tapi kehilangan wibawa.
Kita tahu, jika Amerika bersuara tentang “de-eskalasi”, itu bukan karena mereka tiba-tiba jadi pecinta damai. Mereka hanya menghitung ulang ongkos politik dan ekonomi. Satu rudal Iran ke pangkalan AS bisa membuat harga minyak naik lebih cepat dari cuitan Elon Musk. Satu pesawat tak dikenal jatuh di Tel Aviv, dan pasar saham New York bisa demam semalaman. Dunia bukan lagi sesederhana dua kutub. Dan ini yang mulai disadari oleh semua pihak, meski terlambat.
Washington berusaha tetap elegan. “Kami mendukung stabilitas kawasan,” kata mereka sambil membisikkan persenjataan tambahan ke Tel Aviv. Mereka bicara soal perlindungan warga sipil, padahal laporan Human Rights Watch belum kering soal bom yang dijatuhkan Israel ke kawasan padat penduduk. Hipokrisi sudah bukan barang baru, tapi kali ini terlihat telanjang. Dunia menonton, dan banyak yang tidak lagi membeli narasi lama.
Iran, yang selama ini dicap sebagai “negara nakal”, ternyata masih punya stok kesabaran sekaligus kekuatan. Mereka dihina karena embargo, dicibir karena ekonomi mereka babak belur, tapi tetap saja mampu menyiapkan kejutan strategis. Dan ini bukan sekadar soal senjata—ini soal keberanian menantang tata dunia yang timpang. Israel yang terbiasa main dua peran—korban dan algojo—tiba-tiba kehilangan panggung. Mereka jadi tokoh tragedi dalam naskah yang mulai ditulis ulang.
Dan mari kita tidak naif. Serangan balasan Iran bukan soal moralitas atau kebaikan versus kejahatan. Ini soal harga diri, geopolitik, dan keinginan menunjukkan bahwa tatanan global bukan monopoli blok barat. Iran bukan pahlawan, tapi mereka sedang mengingatkan: kalau aturan main selalu berat sebelah, maka akan selalu ada yang memilih untuk melempar papan permainan.
Di sisi lain, Amerika terlihat lelah. Perang Ukraina belum kelar, ketegangan di Asia Pasifik mengintip dari balik tirai, dan kini Timur Tengah kembali menyala. Satu sisi ingin tetap jadi polisi dunia, sisi lain mereka tahu betul bahwa jadi polisi itu mahal: biaya operasional besar, kredibilitas merosot, dan warganya sendiri sudah bosan dengan perang yang tak kunjung dimenangkan. Amerika bukan lagi negara super yang tak terbantahkan. Mereka kini seperti CEO perusahaan raksasa yang masih tampil elegan di konferensi pers, tapi di ruang rapat sedang panik memikirkan kebangkrutan.
Sementara itu, di jalan-jalan Teheran, orang-orang bersorak. Di lorong Gaza, orang-orang berdoa. Di Tel Aviv, sirine meraung. Dan di Washington, para jenderal dan analis keamanan nasional mulai menyusun skenario baru: bagaimana menjaga pengaruh tanpa terjun terlalu dalam. Tapi mungkin sudah terlambat. Dunia sudah berubah. Negara-negara yang dulu dianggap pemain figuran kini punya naskah sendiri. Dan skenario dominasi lama mulai terlihat rapuh.
Kita, di Nusantara ini, memang jauh dari Gaza atau Golan. Tapi jangan terlalu cepat menganggap ini bukan urusan kita. Dunia global bukan lagi soal jarak geografis, tapi soal efek domino. Ketika harga minyak melonjak, pangan kita pun ikut bergejolak. Ketika satu kawasan meledak, ekonomi dunia ikut demam. Dan yang paling bahaya: ketika satu negara sukses melawan hegemoni, negara-negara lain akan mulai berani.
Iran menendang meja, bukan karena iseng. Mereka ingin menunjukkan bahwa meja itu tak selamanya milik Barat. Israel porak-poranda, karena terlalu lama percaya bahwa pagar besinya tak tertembus. Dan Amerika mengelus dada—mungkin bukan karena sedih, tapi karena sadar: mereka tak lagi punya tangan cukup panjang untuk merangkul sekaligus mencengkram.
Dunia memang tak pernah benar-benar adil. Tapi kini, ia juga tak lagi sepenuhnya takut. Dan seperti kata orang tua kita dulu: kalau tak bisa jadi api, setidaknya jangan jadi bensin. Tapi siapa tahu, dalam zaman begini, jadi air juga tak cukup. Mungkin, saatnya belajar jadi angin—mengalir bebas, tapi bisa berubah jadi badai kapan saja.


 Insight NTB
Insight NTB Suara Time
Suara Time Lens IDN
Lens IDN Daily Jogja
Daily Jogja Jalan Rakyat
Jalan Rakyat Idealita News
Idealita News AYO Nusantara
AYO Nusantara Seedbacklink
Seedbacklink