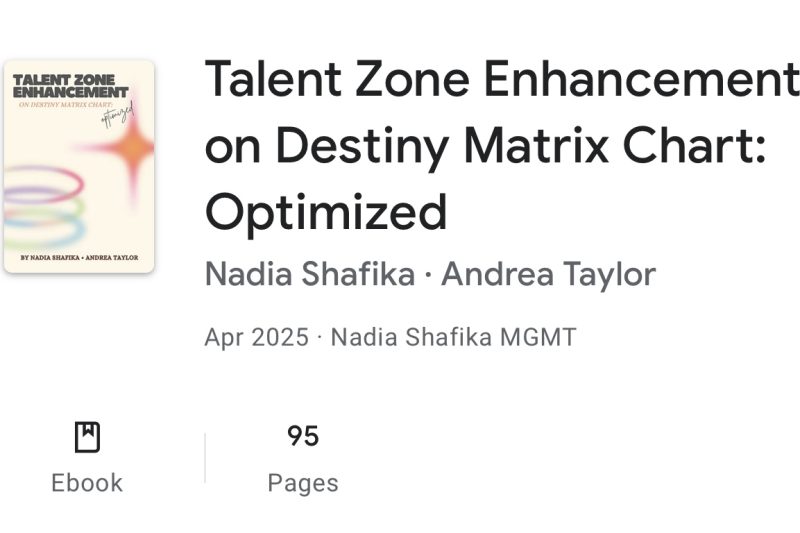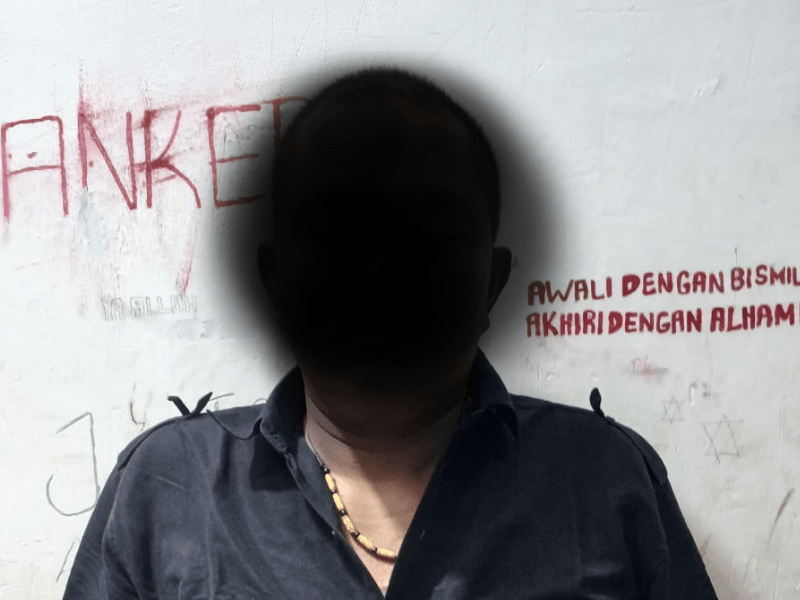Revitalisasi Pemahaman Keislaman dan Kebangsaan

Editor: Ahmad Arsyad
(Nasionalisme Kaum Sarungan Karya A. Helmy Faishal Zaini)
Kabar Baru, Resensi Buku-Helmy Faishal Zaini merupakan salah satu public figure yang konsisten mengampanyekan semangat nasionalisme, spirit Islam dan kemanusiaan. Hal tersebut terekam jelas dalam karyanya Nasionalisme Kaum Sarungan, buku yang akan teramat sayang untuk dilewati tanpa pengkajian dan pendalaman sebagai bekal berbangsa, bernegara dan tentu pula beragama di hari ini dan di kemudian hari. Alasannya jelas, Mantan Sekjen PBNU masa khidmat 2015-2021 tak hanya pandai dalam membangun logika argumen kebangsaan, keislaman dan kemanusiaan melainkan juga jeli menukil referensi mulai dari para pemikir Timur hingga kalangan pemikir Barat, dari kutipan buku hingga ke lirik lagu.
Dan yang tak kalah menarik, kumpulan esai tersebut juga diracik dari khazanah pemikiran ulama Nusantara hingga penyair Indonesia, dari yang berbentuk tembang hingga kutipan puisi yang mendebarkan. Maka, pantas bila buku tersebut dinilai sebagai kumpulan esai yang tak lupa alamat rumah untuk berpulang sebab membicarakan Indonesia dan segala pernak perniknya tanpa mendasarinya dengan dawuh para sesepuh hanya akan terasa hambar meskipun tidak hampa. Secara garis besar, buku tersebut terbagi ke dalam tiga ranah pembahasan, yakni; Nasionalisme Islam Nusantara, Mengikis Radikalisme dan Dakwah yang Merangkul.
Nasionalisme Islam Nusantara
Di bagian ini, Helmy Faishal Zaini hendak menegaskan kembali pada khalayak publik bahwa nasionalisme, cinta tanah air adalah hal yang tak boleh ditukar dengan apa pun. Rasa itu haruslah senantiasa bermukim di relung terdalam hati bangsa Indonesia, apa dan bagaimana pun keadaannya sebab tak ada yang lebih penting dari menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam balutan jubah Indonesia. Hal yang demikian tentulah senada dengan apa yang telah digagas oleh K.H. A Wahab Hasbullah, hubbul wathan minal iman (mencintai Tanah Air adalah sebagian dari iman).
Bila nasionalisme itu merupakan bagian dari iman maka mempertentangkan negara dengan agama hanya karena sistem yang dianutnya berbentuk barang impor dari Barat (demokrasi) bukan barang impor dari Arab yang berbentuk khilafah hanyalah tindakan ceroboh yang hanya dikemas dengan simbol-simbol Islam. Lantas, di sinilah pentingnya revitalisasi pemahaman keislaman dan kebangsaan, mengingat perpaduan Islam dan demokrasi di Indonesia merupakan pencapaian yang luar biasa. Sebab, nyatanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim sebagaimana negara-negara Arab dan negara-negara Teluk, demokrasi sampai saat ini berujung pada anarkisme dan kerusuhan (hlm. 44).
Melihat kenyataan yang demikian di negara-negara Arab, masih perlukah kita berkiblat pada Arab perihal berbangsa dan beragama? Dan meyakini sistem khilafah sebagai solusi untuk negeri ini? Big no untuk pertanyaan tersebut.
Sebab sejatinya Islam yang tersebar luas di bumi Nusantara tak pernah menempuh jalan yang berdarah-darah, penuh kekejaman, permusuhan dan pertempuran. Wali Songo mendakwahkan Islam dengan pendekatan kebudayaan, laku-lampah, serta metode hikmah atau kebijaksanaan, nasihat dan penyampaian yang baik (bilmauidzatil hasanah) serta perdebatan yang harus dilakukan dengan cara yang baik pula. Oleh karenanyalah Islam berhasil termanifestasikan sebagai Islam yang ramah, lentur, merangkul, penuh kasih sayang hingga pada akhirnya paripurna sebagai Islam yang rahmatan lil alamin.
Di tataran praksisnya, Islam yang rahmatan lil alamin harus termanifestasikan ke dalam tiga model ukhuwah demi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dalam pandangan Kiai Ahmad Shiddiq (1926-1991) ketiga hal itu adalah ukhuwah islamiyyah (persaudaraan umat Islam), ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan bangsa) dan ukhuwah basyariyyah (persaudaraan umat manusia).
Tentu Islam yang rahmatan lil alamin inilah yang senantiasa menjadi misi besar NU dalam bingkai Islam Nusantaranya, yakni Islam yang tak hanya bisa hidup berdampingan dengan agama dan keyakinan lain, tetapi juga melebur, memeluk, dan bersenyawa dengan budaya, nilai-nilai keluhuran dan kearifan, serta sistem pemerintahan yang demokratis. Sebab di Indonesia, memeluk Islam berarti harus rela memeluk kebinekaan jua. Lantas, masih adakah ekspresi yang lebih agung dari cinta selain memeluk, merangkul, dan merawat? Sejatinya, seperti inilah wajah Islam yang rahmatan lil alamin, tiada Islam tanpa adanya cinta. Cinta yang mampu memeluk, merangkul, dan merawat yang (ber)beda.
Mengikis Radikalisme
Di bagian kedua ini saya hendak mengawalinya dengan kalimat penulis berikut, “saat engkau melihat awan di langit membentuk lafaz Allah, engkau berkata: inilah tanda kebesaran Allah. Namun, saat engkau melihat manusia yang berbeda-beda suku, ras, agama, golongan, engkau malah menganggap mereka musuh yang harus dibunuh dan diperangi. Mengapa tak kau lihat tanda kebesaran-Nya?” (hlm. 111)
Hidup di negara yang penuh dengan keberagaman tanpa balutan kelapangan psikologis, teologis serta toleransi yang tinggi sungguh akan teramat mustahil untuk menerima segala bentuk perbedaan, apalagi sampai dapat mengolahnya menjadi energi yang positif, perbedaan yang menjadi rahmat, sabda Rasulullah Saw. Maka, menjadi bangsa Indonesia harusnya menjadi manusia yang lapang dada dengan segala bentuk perbedaanya. Di titik inilah pemahaman keislaman serta keindonesiaan yang mendalam menemukan titik urgensinya.
Faktor utama menjamurnya radikalisme terletak pada pemahaman keislaman yang dangkal. Term jihad merupakan kata dan ajaran yang mudah disalahpahami dan disalahgunakan. Setiap yang berbeda, yang ada di luar kelompok dan golongan mereka adalah sesat, kafir, thagut, yang wajib dimusuhi, diperangi, bahkan dibumihanguskan. Lantas, sedemikian menyeramkankah perintah jihad yang diajarkan Islam yang sesungguhnya?
Muhammad Ad-Dawoody (2016) membagi jihad menjadi dua kategori, yakni jihad difa’i (defensif) dan jihad thalabi (ofensif). Sedangkan di kalangan Nahdliyin, term jihad harus direlevansikan sekaligus dikontekstualisasikan dengan latar sosial kemasyarakatan. Bagi NU, jihad bukanlah berperang mengangkat senjata semata, jihad kekinian adalah berperang melawan kebodohan dan kemiskinan (hlm. 127).
Dengan demikian, sebagai upaya untuk mengikis radikalisme, jihad yang berkarakter defensif atau bertahan dapat diterjemahkan ke dalam pola tindakan seperti bela negara, transformasi bidang pendidikan, ekonomi, politik, kebudayaan, kedaulatan militer, melestarikan tradisi baik dan mengembangkan pelbagai temuan baru lainnya sedangkan jihad yang berkarakter ofensif atau menyerang, cenderung melihat dunia dengan kacamata hitam-putih, salah-benar, minna wa minkum serta gemar menempatkan pihak lain sebagai oposisi, lawan yang harus diserang.
Padahal makna dasar jihad dalam Islam adalah untuk mempertahankan diri, bukan menyerang (defensif) dan membuat kerusuhan. Dalam hal jihad kisah Rasulullah Saw, merupakan contoh dan teladan yang sempurna, beliau tidak pernah sekalipun memulai perang kecuali terlebih dahulu diserang dan dianiaya atau perjanjiannya dikhianati. Dan jihad defensif atau mempertahan diri inilah yang menjadi ajaran dalam Islam yang sebenarnya. Perang atau jihad ala Rasulullah bukan memulai perang, tetapi membela diri (defensif). So, masih pantaskah Islam sebagai agama mereka yang suka memulai perang, membuat kerusuhan dan menciptakan kegaduhan sosial atas nama bela Tuhan dan bela Islam?
Dakwah yang Merangkul
Yang terakhir, Helmy Faishal Zaini lebih menekankan pada titik pentingnya bentuk kesalehan sosial sebagai buah dari kesalehan spiritual. Ramadan atau bulan puasa merupakan tema yang kerap dihadirkan dari satu halaman ke halaman yang lain. Maka, dalam rangka menumbuhkembangkan dakwah yang merangkul, Ramadan yang memiliki nama lain Syahr al-judd (bulan kedermawanan) dalam pandangan Helmy Faishal Zaini harus bisa kita ketengahkan dalam konteks kekinian mengingat kondisi kebangsaan kita semakin hari semakin menunjukkan tren ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam sektor ekonomi (hlm. 158).
Dengan demikian, Ramadan tak hanya menjadi momentum makan bersama dengan beragam menu makanan di meja keluarga setiap sahur dan menjelang berbuka puasa. Namun, ia juga dapat dijadikan momentum terbaik untuk mengangkat harkat serta meringankan beban kaum fakir miskin di sekitar kita.
Ali Al-Jurjawi, seorang ulama terkemuka alumni Al-Azhar, Mesir mengungkapkan bahwa di antara hikmah disyariatkannya puasa yakni karena di dalamnya terkandung hikmah ijtimaiah atau dimensi sosial kemasyarakatan. Dengan kata lain, sebab berpuasa, upaya menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kita diharapkan juga mampu memupuk rasa simpati dan empati terhadap mereka yang kekurangan sandang, pangan, dan papan.
Dari keseluruhan esai-esai Helmy Faishal Zaini yang terangkum dalam Nasionalisme Kaum Sarungan, kita akan merasakan bahwa poin utama kerangka pemikirannya terletak pada moderasi Islam dan inklusi agama, yakni kerangka berpikir yang harus senantiasa kita rawat demi keamanan dan ketenteraman hidup di negara majemuk Indonesia. Wallahu a’lam bishawab.

Data Buku
Judul Buku: Nasionalisme Kaum Sarungan
Penulis: A. Helmy Faishal Zaini
Penerbit: Penerbit Buku Kompas
Cetakan: 2018
Tebal: 256 Halaman
ISBN: 978-602-412-392-5
*) Moh. Husain, Alumni PP. Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura.


 Beritabaru.co
Beritabaru.co Serikatnews.com
Serikatnews.com Suaratime.com
Suaratime.com Kabartren.com
Kabartren.com Sabdaguru.com
Sabdaguru.com Dailynusantara.com
Dailynusantara.com Portaldemokrasi.com
Portaldemokrasi.com Seedbacklink.com
Seedbacklink.com