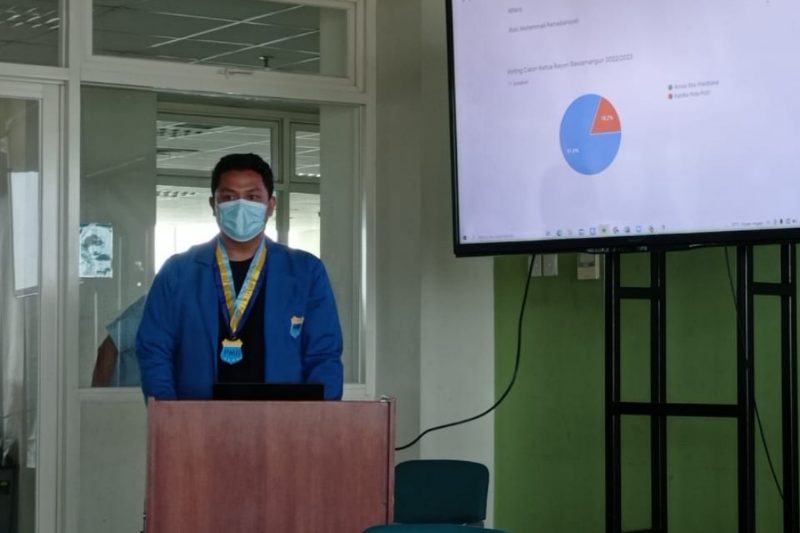Hajatan Gosip Selangkangan

Editor: Ahmad Arsyad
KABARBARU, OPINI– Ini bukan bagian wacana dokter Boyke yang kesohor dengan narasi blak-blakan soal seks dan seksualitas. Paling tidak ini hanya kesah dari cawan massa yang terlanjur menguras akal sehat publik mengenai persoalan tindak-tanduk seksualitas di ruang publik itu. Tanpa menghindari tudingan moralis manapun, bahasan selangkangan merupakan budaya keseharian pembicacaraan dan puncak dari siklus pembicaraan mengenai kosmetika yang cenderung rasis itu. Kita mestinya tidak perlu untuk menghadirkan kasus asusila dan rudapaksa untuk menguatkan bahasan mengenai seksualitas. Karena hal itu sudah sedemikian melekat dan menjadi penentu ukuran kedewasaan dalam kaca mata kalangan psikologis.
Pertama, saya yang dhaif ini ingin melempar jari telunjuk mengapa saat ini begitu haru birunya kecap seksualitas di ruang publik kita. Tetapi sangat “buas” menghardik perilaku yang “a-moral”. Kira-kira di manakah perbedaan antara seks sebagai wacana dan seks sebagai kesangsian. Saat seorang ustad menggagahi santrinya, kita lebih banyak memakai prakti hitam putih dan sedemikian adanya jika perbedaan pendapat yang tak sama persitiwa itu dianggap menjadi bagian dari kepanjangan pelaku.
Ketidakramahan ruang publik belakangan ini bukan karena syiar pendidikan seksualitas tidak ditransmisikan sempurna, tetapi ternyata kecerdasan pengentahuan seksual menjadi senjata justifikasi diri, di sana tidak boleh dan di sini boleh. Sebelum dibenturkan kepada ajaran agama, perdebatan seksualitas seolah menjadi agenda kalangan feminis. Tak dinyana, paradigma emansipatoris yang dipakai kadangkala menjadi alat memukul golongan yang tidak satu ide di antara kelompok perempuan.
Lagi pula bincang-bincang kelamin sudah bagian iklan bebas yang mengundang like dan follower. Kanal-kanal youtube tidak kalah gebyarnya, obrolan panas non-privasi menjadi tontontan dan kawah berlumuran birahi. Saat bintang tamu atau host menampilkan bagian tubuh yang dia anggap superioritas sebagai alat diplomasi dirinya bagi orang lain. Di sanalah masalah baru dimulai. Pada akhirnya seksualitas muskil menjadi tema pokok gerakan sosial. Sebagaimana kita mencoba pahamialasan Tolman (2002) bahwa subjektivitas seksual merupakan pengalaman atas dirinya sendiri sebagai mahluk seksual, yang berhak mendapatkan kenikmanatan serta keamanan seksual. Artinya, spektrum pemaknaan seksualitas makin rapuh bergeser dari arena seksual sebagai reprodukusi menuju seks sebagai hiburan, dan perebutan dominasi.
Keberadaan moral agama menjadi tidak lantas begitu tajam dalam memberikan telunjuk penyadaran pada persoalan ini. Ditambah lagi, kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama semakin menyempitkan ruang gerakan. Pengemasan bahasa seksualitas di ruang publik kita tidak menekankan posisi seks sebagai penghargaan tertinggi. Seks diberitakan dan disampaikan seperti sebuah dongeng tentang kebaikan dan kenikmatan. Curhat Publik figur pada kisah ranjangnya menjadi pengalihan dari tontonan “ruang biru” kepada kanal publik yang berjejaring penuh keasikan. Sebagai zaman Victoria silam di mana perumpamaan perempuan harus memainkan peran “the drawing room, and a monkey in the bedroom”, mengimplikasikan adanya kepentingan perempuan untuk menjadi “jalang” dalam konteks hubungan seksualnya, dalam konteks hubungan suami dan pasangannya. Masihkan kekerasan seksualitas hanya alasan birahi nan salah tempat?
Komedi Putar Kenikmatan
Seoarang perempuan belia mengaku terang-terangan di televisi swasta harus “menjajakan diri” lewat aplikasi daring untuk menutupi keperluan ekonominya. Begitu pula lelaki 21 tahun yang masih kuliah memamerkan diri dengan bangga sebagai simpanan seorang perempuan paruh baya kaya raya. Keduanya tontonan ketercapaian kenikmatan seksualitas yang dibungkus dalam narasi realitas hidup masing-masing. Sekalipun beda latar belakang kisah, keduanya sama dalam mendefinisikan dirinya sebagai mahluk yang tidak habisnya membutuhkan kepuasan seks.
Eksibisionis seks semakin aktif dan menemukan ruang ekspresi lebih luas. Sekalipun itu tetap berbau hukum positif yang tidak lumrah di kaca mata sosial kita. tetapi apa yang dilakukan oleh seorang perempuan beinisial “S” di sebuah bandara nasional dan dintoton ratusan ribu kali itu diakui atau tidak memiliki jemaat penonton yang aktif. Kita juga ingat saat kasus video syur penyanyi dan artis cantik “A” dan “L” tersebar luas. Bahkan seorang pemain bulutangkis tampan “J” menabuh riak histeria penonton perempuan di lapangan sambil berkelakar “rahimku panas”. Publik berkedok rasa curiga tetapi sebenarnya menikmatinya seperti menghardik pelaku tetapi seketika menjadi konsumen dan kepanjangan desas-desusnya.
Ketelanjangan bab “selangkangan” di kehidupan kita menjadi semangat memangsa kaum bejat yang sekarang mendapatkan “visa” gratis dari tonton menggiurkan dan didukung semangat massa yang menganggap seks sebuah hiburan pasar murah. Sebagaimana hajatan besar, kekebasan bersuara perempuan nyatanya tidak mewariskan keberaniannya pada persoalan dirinya. Padahal, kita tidak mengalami perubahan bahwa baiknya perempuan diukur dari baiknya kemulyaan “rahimnya” dalam mengasuh anak dan menyenangkan keluarga. Definisi diskredit ini masih dipertahankan dan menyesakkan akal sehat. Saat ini, di bawah pijar digitalisasi yang gemerlap, pada diri perempuan hampir tak ada lagi kamus “perempuan” dalam hidupnya sebagai sebuah vision du monde (bahasnya De Beauvoir) menjadi tujuan utama. Anak-anak gadis juga banyak diliputi cinderella complex yang masih mengawan-ngawangi lelaki untuk menikahi, membuahi, dan menjadikannya bahagia. Dengan kata lain, kebahagian diberikan dengan sebuah tanda pernikahan. Di dalam gebyar kebebasan bersuara, hal lain juga menimpa kaum perempuan dalam perasaan penuh histeria dalam bahasa psikoanalis dikenal sebagai queen drama. Ada semacam keinginan menjadi paling cantik, kurus, putih, dan kaya sehingga menghasilan drama-drama sosial yang mengerikan.
Gejala keterbukaan media yang mengakomodasi wacana seks menjadi pembelahan kelompok tajam antara “femimis porno” dan “feminis anti-porno”. Bagi feminis yang melihat hal “porno” sebagai sebuah pelepasan diri dari cengkraman kuasa tubuh dan melihat seks sebagai kesahajaan dan tanggung jawab maksimal perempuan atas tubuhnya. Feminis yang kontra hal itu, dianggap sebagai persepsi kebablasan karena bermuara pada relaksasi ketakutan tubuh untuk lebih diekploitasi.
Kini kita akan sampai pada jeda gosip yang menyenangkan mengenai alat kelamin dan peradabannya. Sampai di titik ini, kekerasan seksual sebanding lurus dengan peminatnya yang diam-diam menaikkan libido namun ikut mengutuk. Padahal seks sudah tidak lagi soal keintiman, dia berubah menjadi kenikmatan, pertunjukan, dan hiburan yang murah didapat. Keliyanan seseoarang dalam perilaku dan kecenderungan seksnya menjadi terwadahi karena publik kita juga sama-sama berani menampilkannya ke publik, tinggal bagaimana pasar membaca dan mengemasnya sebagai hiburan moral mengasikkan.
*) Penulis adalah Milki Amirus Sholeh, Pegiat Persoalan Sosial
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kabarbaru.co


 Beritabaru.co
Beritabaru.co Serikatnews.com
Serikatnews.com Suaratime.com
Suaratime.com Kabartren.com
Kabartren.com Sabdaguru.com
Sabdaguru.com Dailynusantara.com
Dailynusantara.com Portaldemokrasi.com
Portaldemokrasi.com Seedbacklink.com
Seedbacklink.com