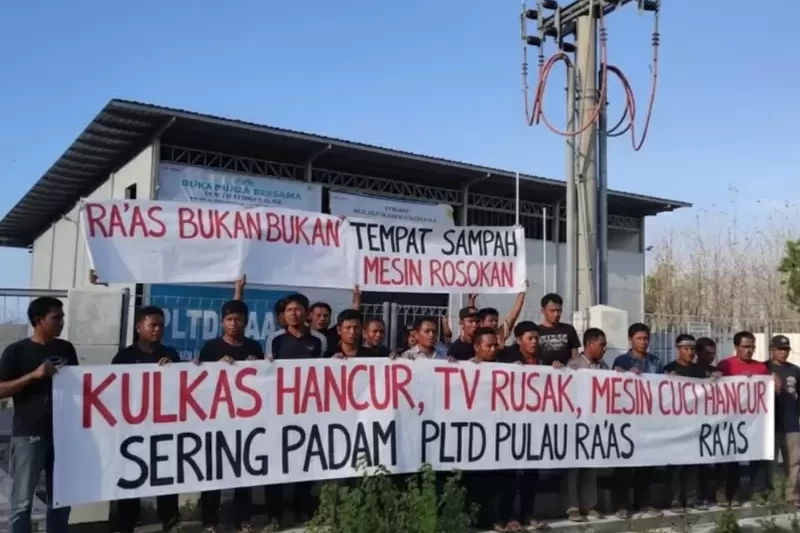Nyalakan Tanda Bahaya, Selamatkan Anak Indonesia dari Jebakan AI, Sekarang!

Editor: Khansa Nadira
Opini—Perayaan Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini (23 Juli 2025) mungkin kembali diisi dengan tawa riang, pidato penuh harapan, dan lagu-lagu tentang masa depan cerah. Sebuah ritual tahunan yang penting untuk mengingatkan kita semua akan sentralitas anak dalam narasi kebangsaan.
Sayangnya, di balik semarak seremoni itu, ada sebuah kenyataan sunyi yang berlangsung di genggaman tangan jutaan anak Indonesia; sebuah portal menuju dunia lain, dunia virtual yang kini semakin cerdas, semakin personal, dan semakin tak terduga berkat kehadiran Kecerdasan Buatan (AI).
Tentu, kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa tantangan terbesar anak-anak kita hanyalah stunting, akses pendidikan, atau perundungan di halaman sekolah.
Tantangan terbesar, yang paling subtil sekaligus paling transformatif, adalah bagaimana kita menyiapkan mereka menjadi warga negara di dua dunia sekaligus; dunia nyata dan dunia digital yang arsitekturnya kini dibangun oleh AI.
Kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah generasi yang kemampuan kognitif, identitas diri, dan interaksi sosialnya dimediasi oleh algoritma. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka siap, melainkan apakah kita orang tua, pendidik, dan negara siap untuk memandu mereka di persimpangan jalan yang penuh paradoks ini.
Paradoks pertama adalah antara akselerasi dan atrofi. Tidak bisa dimungkiri, AI generatif adalah katalisator pengetahuan yang luar biasa. Seorang siswa di pelosok Papua, dengan akses internet yang memadai, kini bisa bertanya tentang fisika kuantum kepada chatbot AI dan mendapatkan penjelasan dalam hitungan detik.
Mereka bisa membuat presentasi visual yang memukau untuk tugas sekolahnya hanya dengan beberapa perintah teks. Sebuah lompatan demokratisasi akses informasi yang puluhan tahun lalu hanya menjadi mimpi. Peluang untuk mengakselerasi kemampuan belajar dan kreativitas anak terbuka begitu lebar, menjanjikan generasi yang lebih cerdas dan inovatif.
Namun, di sisi lain mata uang yang sama, terdapat risiko atrofi kognitif yang mengkhawatirkan. Kemudahan mendapatkan jawaban instan berpotensi menggerus kemampuan berpikir kritis, analisis mendalam, dan proses trial and error yang merupakan fondasi dari pembelajaran sejati.
Ketika AI sudahbisa menyelesaikan soal matematika, dan bahkan membuat karya seni, apa insentif bagi seorang anak untuk melalui proses berpikir yang “melelahkan”?
Kita berisiko menciptakan generasi yang terampil dalam “memerintah” mesin, tetapi gagap dalam memahami proses di baliknya; generasi yang cepat mendapatkan jawaban, tetapi lambat dalam mengajukan pertanyaan yang tepat. Ini adalah bentuk baru dari ketergantungan yang tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa permanen pada arsitektur nalar mereka.
Paradoks kedua, dan mungkin yang paling berbahaya, adalah antara koneksi dan alienasi. Dunia digital yang diperkuat AI menjanjikan konektivitas tanpa batas. Anak-anak bisa berinteraksi dengan teman sebaya dari belahan dunia lain, bergabung dalam komunitas berbasis minat, dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, realitasnya seringkali lebih kelam.
Algoritma media sosial, yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement), cenderung menciptakan “gelembung filter” (filter bubble) dan “ruang gema” (echo chamber). Anak-anak hanya disuguhi konten yang mengonfirmasi keyakinan mereka, membuat mereka semakin tidak toleran terhadap perbedaan pandangan.
Lebih jauh lagi, interaksi yang termediasi ini seringkali dangkal. Standar kesempurnaan wajah yang tanpa cela, kehidupan yang selalu bahagia, pencapaian yang tak henti yang dihasilkan dan disebarluaskan oleh AI menciptakan tekanan mental yang luar biasa.
Angka kecemasan, depresi, dan kasus perundungan siber (cyberbullying) yang kian brutal menunjukkan bahwa konektivitas ini justru seringkali berujung pada perasaan alienasi dan kesepian yang mendalam. Anak-anak kita mungkin memiliki ribuan teman online, tetapi merasa tidak punya satu orang pun untuk diajak bicara saat mereka berada di titik terendah.
Menghadapi problem di atas, pilar-pilar perlindungan anak keluarga, sekolah, dan negara terlihat gamang. Banyak orang tua berada dalam posisi yang sulit. Mereka adalah imigran digital yang mencoba mengasuh penduduk asli digital.
Nasihat konvensional seperti batasi waktu layar terasa tidak lagi memadai. Melarang sepenuhnya adalah mustahil dan kontraproduktif. Namun, membiarkan tanpa panduan sama saja dengan melepas anak di tengah hutan belantara digital tanpa peta dan kompas. Kesenjangan literasi digital antara orang tua dan anak ini adalah celah keamanan paling fundamental yang harus segera kita atasi.
Di sisi lain, institusi pendidikan kita masih berlari maraton untuk mengejar kereta cepat teknologi. Kurikulum yang ada mungkin sudah mulai menyisipkan literasi digital, tetapi seringkali terbatas pada kemampuan teknis operasional cara menggunakan aplikasi atau software.
Padahal, yang dibutuhkan saat ini adalah literasi kritis digital”, sebuah kemampuan untuk memahami cara kerja algoritma, mengidentifikasi misinformasi dan disinformasi (termasuk deepfake yang makin sulit dibedakan), memahami jejak digital dan privasi data, serta membangun etika berinteraksi di ruang virtual. Sekolah harus bertransformasi dari sekadar tempat transfer ilmu menjadi pusat pengembangan nalar kritis untuk menavigasi kompleksitas informasi.
Pilar terakhir, negara, tampak paling lamban bereaksi. Misal, Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) atau UU ITE memang ada, tetapi implementasi dan pengawasannya dalam konteks perlindungan anak di era AI masih jauh dari optimal.
Fokus pada pemblokiran konten seringkali menjadi solusi permukaan yang reaktif, bukan proaktif. Negara, bersama dengan raksasa teknologi, harusnya mendorong pendekatan “safety by design”, di mana platform digital sejak awal dirancang dengan fitur keamanan dan perlindungan anak yang kuat sebagai standar, bukan sebagai pilihan. Akuntabilitas platform harus ditegakkan secara lebih tegas.
Lantas, apa jalan keluarnya? Meratapi perkembangan teknologi adalah sikap yang sia-sia. Kunci untuk keluar dari dilema ini bukanlah dengan menarik rem darurat teknologi, melainkan dengan meningkatkan kapasitas kita semua. Hari Anak Nasional 2025 harus menjadi momentum untuk mendeklarasikan sebuah agenda nasional baru berupa “Membangun Kewarganegaraan Digital yang Tangguh bagi Anak Indonesia.”
Agenda ini harus bertumpu pada tiga gerakan simultan. Pertama, gerakan di tingkat keluarga. Orang tua perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi “mentor digital” bagi anak-anak mereka. Ini bukan tentang menjadi ahli teknologi, tetapi tentang membangun komunikasi terbuka, menetapkan batasan yang sehat bersama-sama, dan yang terpenting, menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijaksana.
Kedua, gerakan di tingkat pendidikan. Literasi kritis digital harus menjadi komponen wajib dalam kurikulum, terintegrasi di semua mata pelajaran, bukan hanya sebagai muatan lokal atau pelajaran tambahan. Guru harus terus-menerus ditingkatkan kapasitasnya agar tidak hanya mengajar dengan teknologi, tetapi mengajar tentang teknologi dan dampaknya secara kritis.
Ketiga, gerakan di tingkat kebijakan. Negara harus lebih berani dalam meregulasi platform digital, menuntut transparansi algoritma, dan memastikan perlindungan data anak menjadi prioritas tertinggi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan industri teknologi mutlak diperlukan untuk merumuskan standar etika dan keamanan AI yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Waba’dhu. Merayakan Hari Anak Nasional adalah merayakan masa depan. Di tahun 2025 ini, masa depan itu tidak lagi bisa dilepaskan dari dunia digital yang ditenagai AI.
Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia tidak menjadi korban pasif dari teknologi, melainkan menjadi subjek yang berdaya, kritis, dan bijaksana dalam menggunakannya.
Kita tidak sedang melindungi mereka dari masa depan, kita sedang mempersiapkan mereka untuk masa depan. Sebuah masa depan di mana mereka tidak hanya selamat, tetapi juga mampu berkembang menjadi warga negara yang utuh, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Inilah tantangan terbesar kita, dan inilah tanggung jawab sejarah kita. Wallahu A’lam.
Penulis adalah Ahmad Ulul Albab, Kepala Sekolah SDN 5 Ampelgading, Tirtoyudo Kabupaten Malang.
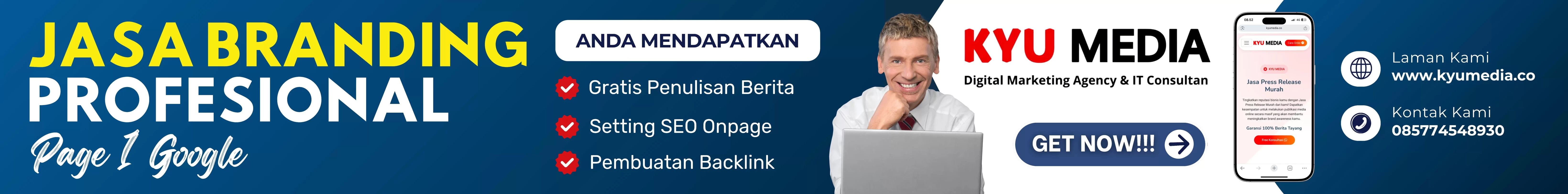

 Insight NTB
Insight NTB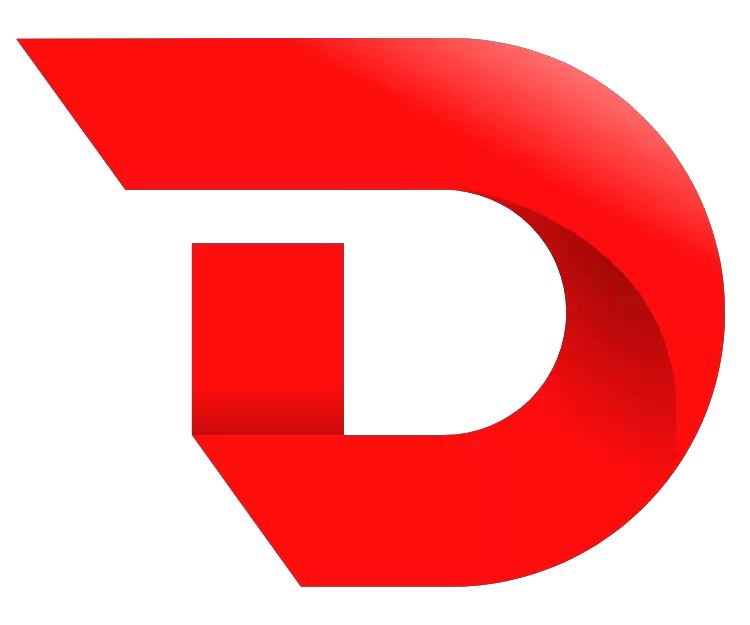 Daily Nusantara
Daily Nusantara Suara Time
Suara Time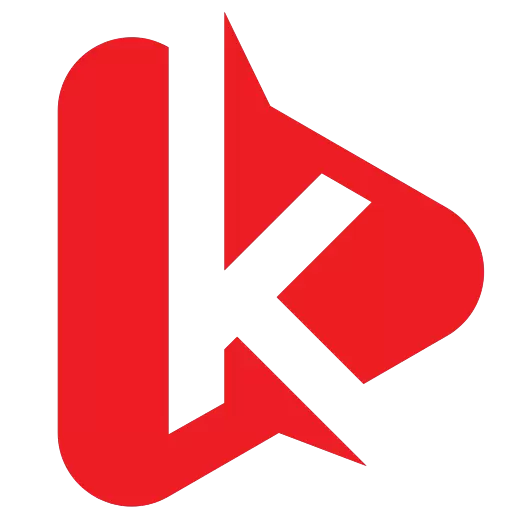 Kabar Tren
Kabar Tren Portal Demokrasi
Portal Demokrasi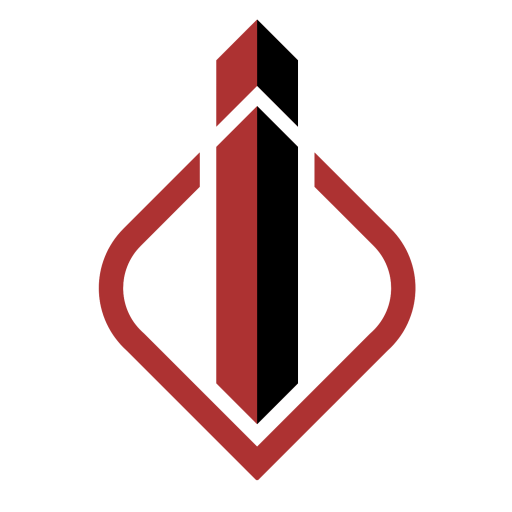 IDN Vox
IDN Vox Lens IDN
Lens IDN Seedbacklink
Seedbacklink