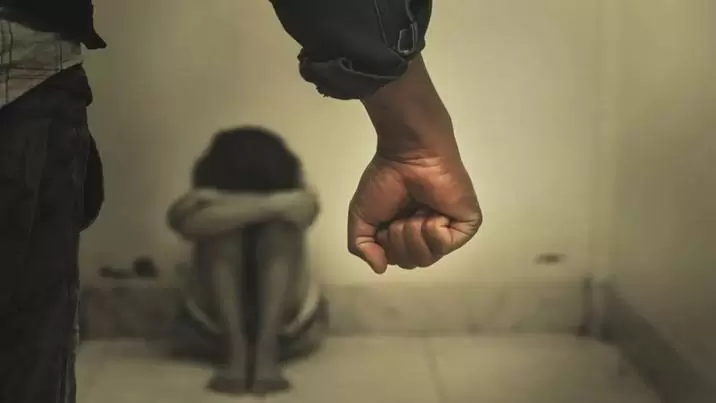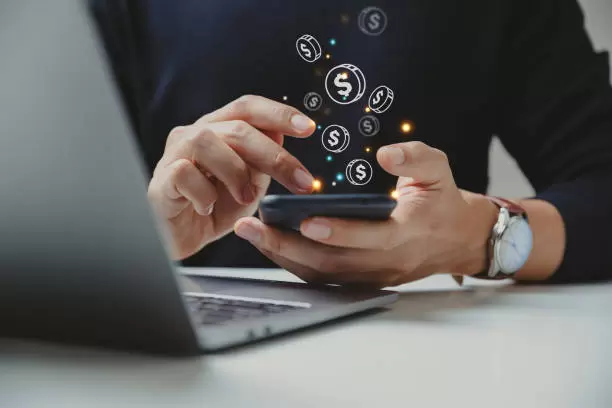Pelatihan Olahan Mangrove Desa Cemara Tingkatkan Ekonomi dan Kelestarian Pesisir

Jurnalis: Azzahra Bahiyyah
Kabar Baru, Pendidikan – Dari hutan mangrove yang selama ini hanya dipandang sebagai penghalang ombak dan ekosistem yang rapuh, kini lahir sebuah terobosan pemberdayaan yang menginspirasi. Dr. Sodikin dosen Magister Studi Lingkungan (MSL) Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka yang juga seorang pakar ekosistem mangrove, hadir membawa angin segar bagi masyarakat pesisir dengan menggagas pelatihan pengolahan mangrove menjadi produk pangan bernilai ekonomi tinggi. Kegiatan ini diinisiasi atas dasar potensi besar kawasan Desa Cemara yang dikelilingi hutan mangrove melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga sebagai sumber pangan maupun penghasilan.
Melalui kolaborasi yang hangat dan penuh semangat, Dr. Sodikin menggandeng 17 ibu-ibu PKK untuk mengikuti pelatihan yang digelar di Kantor Desa Cemara Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu, membuka mata mereka bahwa apa yang selama ini tumbuh liar di sekitar rumah bisa diubah menjadi makanan lezat dan minuman menyegarkan yang bisa dipasarkan. Dalam sesi edukatif, ia tidak hanya menjelaskan fungsi ekologis mangrove sebagai penahan abrasi dan penyerap karbon, tetapi juga menekankan potensi ekonominya.
“Kita harus mengubah cara pandang masyarakat terhadap mangrove. Bukan hanya sebagai penghalang ombak, tapi sebagai sumber pangan, sumber penghasilan, dan simbol ketahanan pesisir. Pelestarian mangrove harus dikaitkan langsung dengan peningkatan kesejahteraan. Kalau masyarakat merasakan manfaatnya, mereka akan menjaganya dengan sukarela,” ujar Dr. Sodikin dengan penuh semangat.
Pelatihan berlangsung dalam dua sesi yang saling melengkapi. Sesi pertama bersifat edukatif, di mana Dr. Sodikin menjelaskan secara mendalam peran dan fungsi ekosistem mangrove—mulai dari penahan abrasi, penyerap karbon, hingga sebagai habitat berbagai biota laut. Ia juga mengenalkan berbagai jenis mangrove yang tumbuh di wilayah pesisir Indramayu, menekankan bahwa tidak semua mangrove bisa diolah, tetapi ada spesies tertentu yang aman dan bernutrisi tinggi jika diolah dengan benar. Dalam sesi ini, peserta tampak sangat antusias, banyak yang mulai menyadari bahwa menjaga hutan bakau bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal masa depan ekonomi keluarga mereka.
Sesi kedua langsung menuju praktik—wujud nyata dari ilmu yang didapat. Dibantu oleh Bapak Abdul Latif, aktivis lingkungan senior asal Indramayu yang telah puluhan tahun konsisten dalam pelestarian pesisir, para ibu diajarkan cara mengolah tiga jenis mangrove menjadi produk pangan yang inovatif dan menarik pasar. Buah dari Sonneratia caseolaris, yang dikenal secara lokal sebagai lindur, diolah menjadi dodol mangrove yang legit dan sirup yang menyegarkan. Berdasarkan penelitian, buah lindur kaya akan karbohidrat kompleks, serat, dan antioksidan, menjadikannya alternatif pangan sehat yang mampu mendukung ketahanan pangan lokal.
Begitu pula dengan Bruguiera gymnorhiza, yang bagian propagulnya diolah menjadi bolu mangrove—kue lembut dengan warna cokelat alami yang unik dan rasa yang khas. Sementara itu, Acrostichum aureum, sejenis pakis pesisir, diolah menjadi keripik renyah yang kemudian dikenal sebagai “krispy mangrove”, dibuat dengan penggorengan rendah minyak dan bumbu alami.
Antusiasme peserta begitu terasa selama pelatihan. Banyak dari mereka mengungkapkan bahwa selama ini mereka hanya memandang mangrove sebagai tanaman biasa, bahkan terkadang menganggapnya penghalang. Namun kini, mereka melihatnya sebagai berkah yang bisa dikonversi menjadi penghasilan. “Kami merasa mendapat ilmu baru yang langsung bisa kami praktekkan di rumah. Ini bisa jadi tambahan penghasilan buat keluarga,” ujar salah seorang peserta dengan penuh semangat.
Harapan mereka kini bertumpu pada pengembangan sentra produk olahan mangrove di Desa Cemara, yang tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga menjadi daya tarik wisata edukasi lingkungan. Lebih dari sekadar pelatihan, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam membangun ekonomi berbasis ekosistem. Dengan memberi nilai ekonomi pada mangrove, masyarakat secara tidak langsung didorong untuk melestarikannya. “Keberhasilan di Desa Cemara bisa menjadi contoh bagi wilayah pesisir lain di Indonesia. Ini adalah model pemberdayaan yang berkelanjutan: lingkungan terjaga, ekonomi tumbuh, dan perempuan menjadi aktor utama perubahan,” tandas Dr. Sodikin.
Dukungan dari tokoh lokal seperti Bapak Abdul Latif juga menjadi kunci keberhasilan, karena kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang sudah lama dikenal membuat proses edukasi lebih efektif. Ke depan, diperlukan pendampingan lanjutan, pelabelan produk, hingga pemasaran digital agar produk-produk olahan mangrove ini bisa menembus pasar yang lebih luas. Dengan kolaborasi antara akademisi, aktivis, pemerintah desa, dan masyarakat, Desa Cemara berpotensi menjadi pioneer ekowisata dan ekonomi biru di Jawa Barat. Dari hutan bakau, tumbuhlah harapan untuk lingkungan yang lestari dan masyarakat yang mandiri.
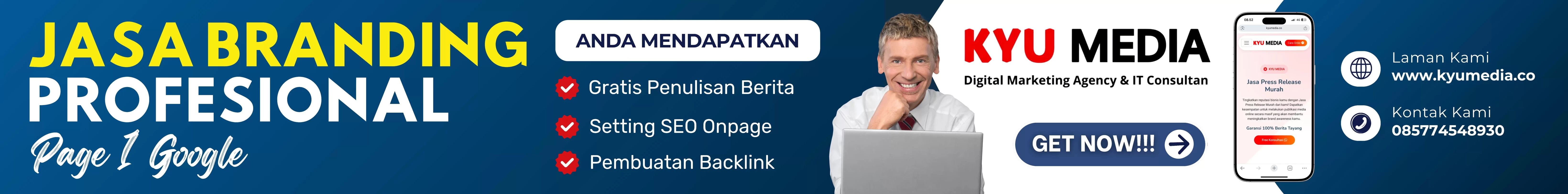

 Insight NTB
Insight NTB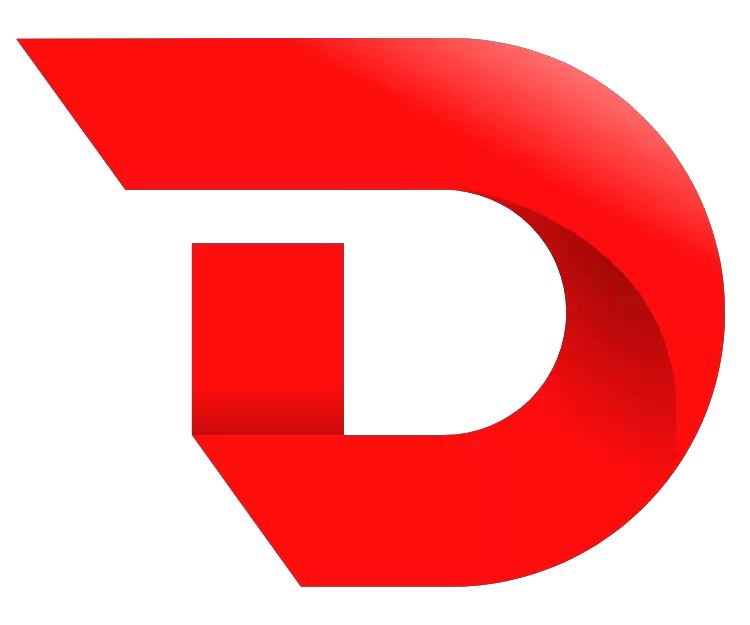 Daily Nusantara
Daily Nusantara Suara Time
Suara Time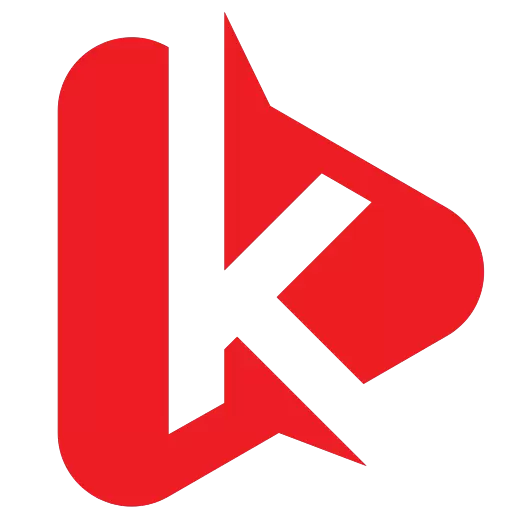 Kabar Tren
Kabar Tren Portal Demokrasi
Portal Demokrasi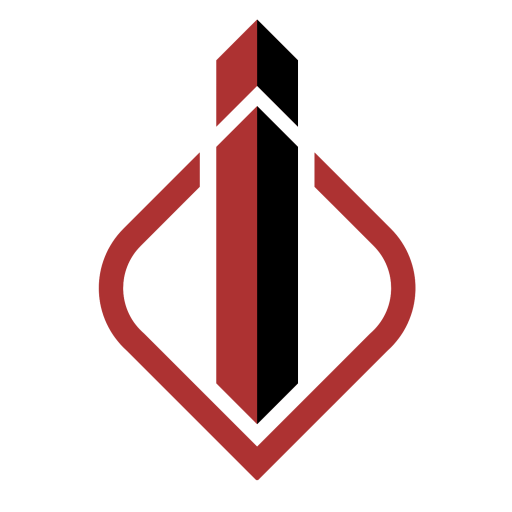 IDN Vox
IDN Vox Lens IDN
Lens IDN Seedbacklink
Seedbacklink