Izin Usaha Pertambangan Kepada Perguruan Tinggi, Inovasi atau Intervensi?

Editor: Ahmad Arsyad
Kabar Baru, Opini – Isu pertambangan kembali mencuri perhatian publik setelah pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi kemasyarakatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Kini, perdebatan baru muncul terkait rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi yang dipicu oleh usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dengan rencana pengaturan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melalui lelang atau prioritas kepada perguruan tinggi.
Isu tersebut mengundang perhatian publik mengingat dua opsi yang diusulkan, yakni izin kelola tambang diberikan langsung kepada perguruan tinggi atau melalui BUMN yang hasilnya akan dibagikan kepada perguruan tinggi. Pada satu sisi, kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan pendanaan bagi institusi pendidikan tinggi, yang selama ini tergantung pada anggaran pemerintah. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi bisa berisiko besar, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun tata kelola.
Usulan revisi Undang-Undang Minerba oleh DPR RI, yang kemudian direspon oleh pemerintah dengan menawarkan dua opsi terkait tata cara pemberian izin, sejatinya mencerminkan perubahan signifikan dalam cara pandang terhadap perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang seharusnya diposisikan sebagai entitas pendidikan, kini lebih dilihat sebagai korporasi yang dapat dikontrol langsung oleh pemerintah. Langkah ini, meskipun berpotensi memberikan keuntungan finansial, juga berisiko besar dalam mereduksi peran fundamental perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Apabila perguruan tinggi mulai dikelola sebagai entitas bisnis yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam seperti tambang, maka esensi Tri Dharma Perguruan Tinggi – Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat – akan tergerus. Selama ini, Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi dasar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki komitmen terhadap kemajuan bangsa dan keberlanjutan negara. Perguruan tinggi seharusnya tetap menjadi lembaga yang mendidik generasi muda dengan nilai-nilai kebangsaan, memajukan riset yang berbasis pada keilmuan dan etika, serta memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat melalui pengabdian, bukan malah ikut serta dalam mengelola tambang yang selama ini berkontribusi secara signifikan terhadap kerusakan lingkungan.
Usulan pemberian IUP kepada perguruan tinggi tidak hanya berisiko menggerus fungsi utama perguruan tinggi sebagai entitas pendidikan. Setelah mempertimbangkan dan menimbang berbagai potensi risiko yang mungkin timbul jika perguruan tinggi terlibat dalam pengelolaan tambang, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga, penulis menemukan sejumlah risiko lain yang mungkin sulit untuk dihindari. Pertama, adanya potensi konflik kepentingan. Keterlibatan perguruan tinggi dalam industri tambang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang tidak mudah dihindari. Dalam situasi tersebut, keputusan yang diambil oleh perguruan tinggi bisa saja lebih mengutamakan aspek keuntungan finansial ketimbang mempertahankan prinsip-prinsip dasar akademik, integritas ilmiah, serta keberlanjutan sosial dan lingkungan. Perguruan tinggi, sebagai institusi yang seharusnya mengedepankan pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi positif bagi masyarakat, berisiko mengabaikan tanggung jawab etis dan sosialnya jika lebih fokus pada pencapaian laba. Konflik kepentingan ini dapat mengganggu objektivitas dalam proses pengambilan keputusan dan merusak reputasi akademik perguruan tinggi sebagai lembaga yang independen dan berintegritas.
Kedua, pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Pengelolaan dalam sektor pertambangan dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan. Industri pertambangan dikenal dengan potensi kerusakan ekosistem, polusi udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Perguruan tinggi, meskipun memiliki keahlian dalam bidang akademik dan riset, mungkin tidak memiliki pengalaman praktis yang cukup dalam mengelola industri pertambangan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Tanpa pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan, perguruan tinggi berisiko memperburuk dampak negatif terhadap ekosistem dan mempercepat kerusakan lingkungan.
Ketiga, pengalihan sumber daya yang tidak efisien. Keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang akan memerlukan alokasi sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur yang cukup besar. Hal ini berpotensi mengalihkan fokus dan prioritas perguruan tinggi dari tugas utamanya dalam pengembangan kurikulum, peningkatan fasilitas pendidikan, dan pelaksanaan riset yang lebih mendesak. Jika perhatian dan sumber daya terlalu difokuskan pada pengelolaan industri tambang, kualitas pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa bisa terpengaruh. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat menghadapi kesulitan dalam menjaga standar akademik dan inovasi, yang pada gilirannya dapat merugikan mutu pendidikan dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan risiko-risiko di atas, maka sudah selayaknya seluruh perguruan tinggi di Indonesia menolak klausul pemberian IUP kepada perguruan tinggi dalam UU Minerba dan mempertanyakan kembali niatan terselubung DPR RI dan pemerintah sehingga memiliki inisiatif memberikan IUP kepada perguruan tinggi. Karena pemberian IUP tersebut sudah secara jelas dan terang benderang dapat menggeser fungsi utama perguruan tinggi dari entitas pendidikan ke entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata. Jika perguruan tinggi dengan riang gembira menerima atau tidak memiliki sikap atas problematika tersebut, maka sudah jelas bahwa institusi pendidikan kita hari ini lebih mengutamakan finansial daripada kualitas sumber daya manusia Indonesia.
*) Penulis adalah Ainia Fany Nur Khofifah, Mahasiswa Magister Kebijakan Publik UNAIR Surabaya.
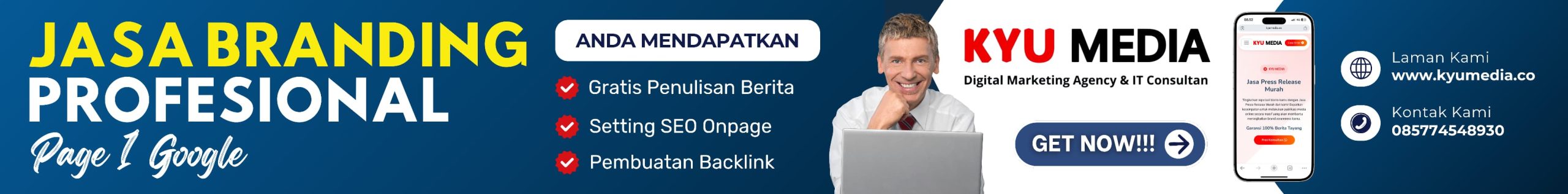

 Beritabaru.co
Beritabaru.co Serikatnews.com
Serikatnews.com Suaratime.com
Suaratime.com Kabartren.com
Kabartren.com Sabdaguru.com
Sabdaguru.com Dailynusantara.com
Dailynusantara.com Portaldemokrasi.com
Portaldemokrasi.com Seedbacklink.com
Seedbacklink.com

























