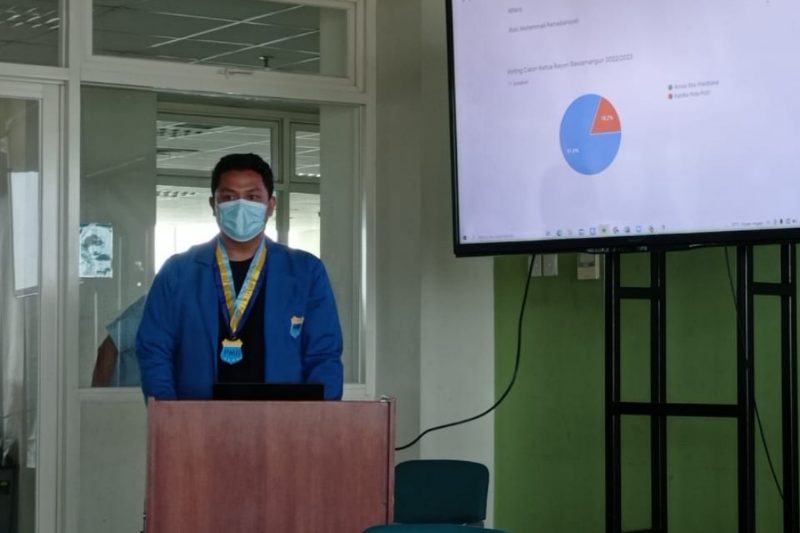DANGDUT TAHUN POLITIK

Editor: Ahmad Arsyad
“Barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan-permainan. Bermainlah untuk bahagia, tetapi janganlah mempermainkan bahagia.” Driyarkara
Kabar Baru, Opini- Musik menjadi tone jiwa yang mudah diterima semua kalangan. Tak heran hajatan tanpa musik seperti kurang kemeriahannya. Musik dalam politik pun tidak sungkan telah menjadi sarana komunikasi simbol visi partai pada pemilih politik. Meski selera musik kita sudah tidak perlu kelamin ideologis. Di tangan parpol, musik kian berharga untuk menyentuh kegundahan dan kebosanan rakyat bernegara.
Di tengah kelompok ekonomi menengah ke bawah, relasi musik dangdut menjadi pamungkas untuk menyatukan perhatian. Cak Imin ketua parpol PKB itu, bahkan keliling mengadakan fesitival musik di luar wilayah ibu kota, menandu artis kawakan ibu kota masuk kabupaten dan kota di Pulau Jawa. Dangdut berdaya pikat untuk mengumpulkan masyarakat. Hari-hari kampanye menjadi musim panen pendapatan lebih bagi penyanyi dangdut.
Dangdut memberi nafas bagi kehidupan politik. Sejarah politik negeri ini kemudian tak jauh dari narasi goyangan sensual di atas panggung dangdut. Tak jarang di ruang itu, ekspresi erotika dijual dan pertontonkan.
Kalau kita lihat dalam masa Orde Baru, para penyanyi dangdut diperalat meski dibayar oleh para penguasa untuk menjadi pengumpul massa dalam kampanye-kampanye (Partai) Golkar. Kalau kita pernah menyaksikan pentas dangdut yang diselenggarakan oleh Golkar pasti kita akan melihat penyanyi dangdut yang ternama seperti Camelia Malik, Iis Dahlia.
Selepas era reformasi, penyanyi dangdut tidak terkutub dikontrak oleh Golkar namun semua partai mencoba mendekati penyanyi dangdut. Setiap acara kampanye, entah itu kampanye Pilkada, Pileg, Pilpres, pasti ada dendangan dan goyangan penyanyi dangdut.
Penyanyi dangdut tak sekadar dijadikan pengumpul massa namun mereka sudah diangkat naik pada taraf yang lebih tinggi, jadi caleg, cabup, cagub, cawalkot bahkan capres. Mereka diposisikan pada calon-calon itu bukan karena kualitas namun lebih pada popularitas.
Bagi para pesohor grup atau artis musik dangdut, agenda kampanye parpol menjadi mutual meniakkan pamor lebih luas. Selain peluang rezeki, penggunaan jasa mereka telah mengubah citra dangdut ke pangsa pasar yang lebih berkelas.
Biduanita dangdut tidak perlu lagi memikirkan opsi untuk pindah pekerjaan jika terlalu sepi manggung. Lagi pula mereka kini akan memiliki daya tawar lebih menjanjikan daripada menunggu pesta hajatan hari panen raya atau sukuran nelayan sebagai mana umumnya di wilayah Pantura.
Sesedih apa pun lagu dangdut, hampir mustahil tak dapat digoyangi. Dengan demikian, dangdut menjadi musik yang mengisahkan goyang. Unsur pesan politik tidak perlu dominan bahkan sering bertabrakan dengan irama musik sedih dan kecewa dalam lagu dangdut. Kemeriahan adalah pesan utamanya. Massa yang hadir akan bertautan erat dengan potensi dukungan dan pengetahuan publik pada parpol atau calon politik.
Di kala musik-musik lain hanya menempatkan publik sebagai penikmat dan penonton, dangdut bisa melibatkan publik sebagai subjek, laksana aktor atau pemeran utama. Jangan heran kemudian jika lagu-lagu penyanyi tertentu begitu digemari. Bukan semata karena lagunya enak didengar, namun kekuatan liriknya turut mengisahkan kehidupan kelas bawah.
Tak heran jika Philip Yampolsky lewat Smithsonian Folkways (1991) menempatkan dangdut sebagai musik “kebangsaan” Indonesia. Berbeda dengan musik pop yang terkesan lebih menunjukkan kelas dan usia sekalipun sama-sama memakai langgam pasar. Dangdut masih lebih mudah meraba kantong kecil dan nuansa kebersamaan masyarakat.
Gema Tahun Politik
Kita akan mulai bertanya, apa yang menarik dari panggung-panggung dangdut di musim politik? Jawabannya sederhana yakni kenaturalan dari ekpresi panggung dangdut. Catatan khusunya karena telah mengambil jarak yang berbeda dari dangdung di televisi yang menampilkan ekpresi santun dan tidak banyak gerak mimik (goyang).
Meski tergilas oleh musik pop di arena televisi, parpol menggaris bawahi personafikasi biduan dangdut lebih menggairahkan pemilih. Belum lagi penyanyi tersebut sudah mimiliki nama dan menarik usia remaja nimbrung bersama. Paduan irama dan massa adalah resonansi yang diharapkan guna memudahkan naiknya citra parpol atau sosok. Kesempatan itu tidak selalu bersamaan ada, dan hanya pada musim politik keduanya diikat dalam dimensi histeria kenikmatan dan politik kepentingan.
Dangdut menjadi ruang ideal dalam misi propaganda politik, terutama lewat erotika. Wajar kemudian jika jadwal pementasan kelompok dangdut di Jawa Timur dan Pantai Utara Jawa (Pantura) penuh menjelang pemilu.
Erotika menjadi pemandangan lumrah. Para politikus disemai dari hasil goyang. Walaupun kadang mereka lupa, setelah menjadi birokrat sibuk mengurusi tentang undang-undang pornografi dalam musik dangdut. Tak sadar bahwa lewat dangdut dan erotikalah politisi itu dibentuk.
Politik karenanya menjadi “the only game in town”. Seolah-olah hanya yang berpolitiklah yang akan muncul dan diperhitungkan. Sementara kegiatan berekonomi, berbudaya, dan berkesenian dianggap sebagai pekerjaan sampingan,yang sifatnya pinggiran dan karenanya tak bergengsi.
Warisan lama dari politik “executive heavy” tidak mudah dihilangkan dalam waktu yang singkat. Penyalahgunaan kekuasaan dan uang untuk kepentingan diri dan golongannya masih terus berlanjut. Pelayanan publik masih tetap mahal dan jauh dari mudah.
Seriusnya, bahwa dangdut bisa menjadi kamuflase yang ditutupi lewat gebyar panggung musik. Mesti dicatat bahwa, frase tahun politik tidak lahir dari imajinasi kerakyatan. Dengan kata lain, ketika aktivitas politik sedang dirumuskan, rakyat tidak hadir dalam ingatan. Rakyat hanya ditempatkan sebagai kerumunan massa yang akan menonton sebuah kontes ketika calon pemimpin yang dikirim partai politik tadi menjadi kontestannya. Dalam pola pikir ini jelas rakyat tidak perlu dilibatkan dari awal. Rakyat adalah para pembeli barang jadi yang instan, pemilih yang dipilihkan. Rakyat dianggap tak perlu tahu-menahu soal proses. Yang penting dilakukan adalah bagaimana memoles para kontestan supaya tampak seksi di atas panggung.
Mengikuti logika ini, apa yang disebut Allan Goldstein sebagai the politics of show menjadi niscaya. Dalam terminologi ini, politik dan politisi memang merupakan sebuah”panggung modern” yang berjarak dari penontonnya (rakyat). Di atas panggung, para pemain jelas harus memakai ”gaun pentas” yang mampu menyihir penonton. Gaun itu tak lain selubung citra.
*) Penulis adalah Milki Amirus Sholeh, Pegiat Persoalan Sosial.


 Beritabaru.co
Beritabaru.co Serikatnews.com
Serikatnews.com Suaratime.com
Suaratime.com Kabartren.com
Kabartren.com Sabdaguru.com
Sabdaguru.com Dailynusantara.com
Dailynusantara.com Portaldemokrasi.com
Portaldemokrasi.com Seedbacklink.com
Seedbacklink.com