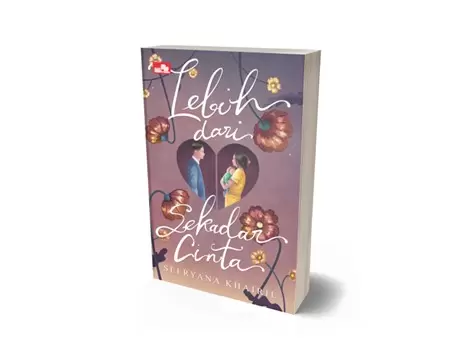Katastrofi Ekologis: Penundukan Demokrasi di Raja Ampat
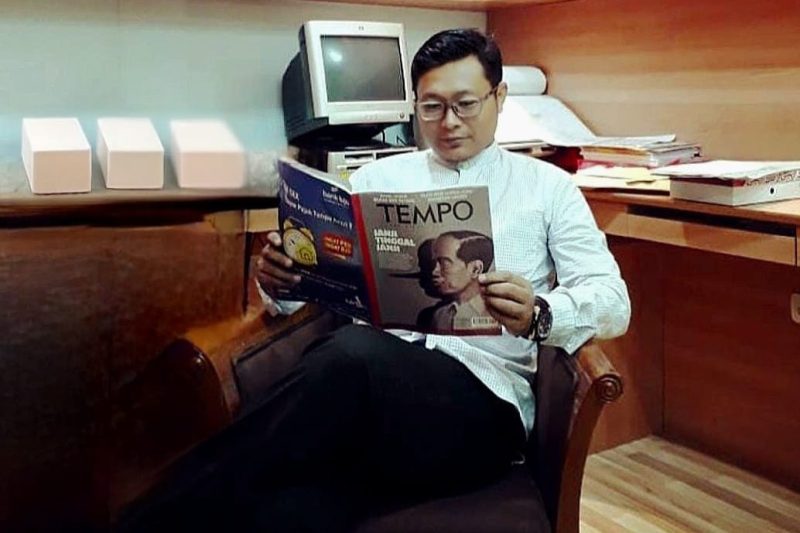
Editor: Ahmad Arsyad
Kabar Baru, Opini- Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pijakan fundamental dan strategis bagi arah pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Kalimat ini tidak hanya sekadar menjadi hiasan normatif konstitusi, tetapi merupakan visi besar tentang arah pembangunan ekonomi Indonesia: bukan ekonomi pasar bebas ala kapitalisme Barat, dan bukan pula ekonomi komando ala sosialisme klasik, melainkan jalan tengah khas Indonesia yakni pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi Pancasila.
Sebuah tawaran peta jalan demokrasi yang ideal, berisi antara keseimbangan kekuasaan dan keseimbangan ekologis untuk menghadirkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disini demokrasi diletakkan untuk memproduksi dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.
Namun dalam praktiknya, demokrasi acapkali gagal mencegah katastrofi ekologis akibat dominasi kepentingan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan lemahnya penegakan hukum lingkungan. Disini negara seolah hadir hanya untuk mengamankan investasi, tetapi absen saat masyarakat mempertanyakan dampaknya. Alih-alih masyarakat menjadi subyek dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, justru seringkali terabaikan.
Laporan LBH Papua dan JATAM menyebut, pertemuan-pertemuan formal diberbagai kampung diselenggarakan di bawah pengawasan aparat keamanan bahkan beberapa tokoh adat yang vokal mengalami tekanan dan intimidasi. Inilah wajah baru ekstraktivisme: bukan sekadar penggalian sumber daya alam, melainkan juga penundukan ruang demokrasi di tingkat lokal.
Masuknya aktivitas ekstraktif nikel ke wilayah Raja Ampat disebut-sebut untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, karena nikel kini sudah menjadi komoditas strategis dunia. Permintaan global melonjak akibat transisi energi dan meningkatnya produksi baterai kendaraan Listrik. Namun narasi tentang “nilai tambah” dan “industrialisasi nikel” seringkali mengabaikan nilai sesungguhnya: hutan ditebang, laut tercemar, dan komunitas adat disingkirkan. Dibalik janji investasi dan pertumbuhan ekonomi ada wilayah konservasi alam dan budaya yang diluluhlantakkan.
Hutan Raja Ampat yang seharusnya menjadi kawasan lindung dan situs warisan dunia berubah jadi area konsesi. Sedimentasi meningkat, terumbu karang rusak, dan mata pencaharian warga pesisir terganggu. Ironisnya, semua ini terjadi di negara dengan sistem demokrasi yang seharusnya melindungi hak masyarakat dan lingkungan. Namun ketika aktivitas ekstraktif “tambang nikel” mulai menancapkan mesin penggeruknya, lingkungan jadi rusak, suara warga menghilang, dan demokrasi nyaris tak bersuara demi kepentingan ekonomi dan politik.
Katastrofi ekologis di Raja Ampat bukan hanya tentang rusaknya terumbu karang atau hilangnya hutan. Melainkan juga hilangnya nilai spiritual dan budaya masyarakat adat, demokrasi yang kehilangan arah serta menurunnya kualitas hidup masyarakat lokal akibat pencemaran lingkungan. Ini adalah cerminan dari krisis demokrasi dimana kekuasaan dan keuntungan mengalahkan keadilan, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.
Ambisi untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global tidak boleh dibayar dengan kehancuran lingkungan dan hilangnya suara rakyat. Karena demokrasi tanpa keberpihakan pada masyarakat dan alam, hanya akan menjadi instrumen legitimasi bagi kekuasaan dan korporasi. Raja Ampat sudah kaya jadi tidak butuh tambang untuk jadi kaya. yang dibutuhkan hanyalah perlindungan, keberanian untuk menjaga, dan demokrasi yang benar-benar mendengar serta negara yang berpihak kepada masa depan bukan kepada pemodal.
Karena demokrasi bukan hanya soal mekanisme politik, tetapi juga soal nilai dan arah yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi bukan hanya sekadar prosedur politik seperti pemilu dan pergantian kekuasaan, tetapi memiliki arah dan tujuan tertentu yang ingin dicapai, seperti keadilan, kesejahteraan, kebebasan, atau keberlanjutan ekologi.
Surga yang Terkikis Nikel
Langit Raja Ampat yang biru nan jernih, merefleksikan gugusan pulau karst yang memukau dan perairan kristal. Sulit mencari padanan kata yang cukup untuk menggambarkan keindahan alam Raja Ampat. Di bawahnya, terumbu karang warna-warni menjadi rumah bagi ribuan spesies laut, magnet bagi penyelam dan peneliti dari seluruh penjuru dunia. Raja Ampat bukan hanya kebanggaan Papua dan Indonesia tapi juga mahkota ekologi dunia.
Namun, surga itu kini berhadapan dengan bulldozer yang merayap, sebuah ironi yang pahit: nikel, mineral yang digadang-gadang sebagai kunci transisi energi global, justru mulai menggerogotinya. Masuknya industri tambang nikel ke kawasan ini telah mengusik keseimbangan ekologis dan menyingkap wajah ekonomi Indonesia yang masih berpihak pada aktivitas ekstraktif, bukan pelestarian.
Hingga kini sistem ekonomi Indonesia masih mengikuti model lama dan sudah usang “business as usual” yang dibangun berdasarkan pola ekstraktif dengan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis, dengan memberikan prioritas pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Praktik ini hanya menumpuk keuntungan pada segelintir orang, sementara kerugian ditanggung bersama oleh rakyat, oleh lingkungan, dan generasi mendatang.
Disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Alih-alih membawa perbaikan dalam tata kelola sektor pertambangan, revisi ini justru memperkuat dominasi industri ekstraktif, mengabaikan hak masyarakat terdampak, serta semakin menjauhkan Indonesia dari agenda transisi energi yang berkeadilan.
Meskipun demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berdalih pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang UU Minerba menjadi langkah pemerintah sebagai upaya mengembalikan esensi Pasal 33 UUD 1945. Bahlil menyebut regulasi ini sebagai “jihad konstitusi” demi memastikan pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Namun jika telisik lebih dalam lagi, UU Minerba ini seakan makin mengukuhkan model pembangunan berbasis ekstraktivisme, yaitu model pembangunan yang menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar, tanpa mempertimbangkan keberlangsungan ekologis dan keadilan sosial.
Nampaknya “Jihad konstitusi” versi Bahlil Lahadalia ini lebih berakar pada logika investasi dan efisiensi kapital ketimbang pada keadilan sosial dan ekologis seperti dimandatkan UUD 1945. Karena apa yang disebut ekonomi hijau dalam narasi negara sejauh ini masih dibangun di atas pondasi lama yang ekstraktif dan sentralistik.
Laporan Greenpeace, Juni 2025, membuktikan 500 hektar hutan Raja Ampat dibabat, pola perusakannya mirip dengan yang terjadi sebelumnya di Pulau Gebe. Mangrove di Raja Ampat, yang sebelumnya menjadi pelindung alami garis pantai dan berperan sebagai penyangga karena menyerap karbon, sekarang banyak ditebangi untuk membuka lahan proyek nikel.
Raja Ampat merupakan salah satu cermin buram kegagalan negara menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian, seakan membiarkan permata ini tercemar demi nikel. Namun bilamana pemerintah terus abai, dunia akan mengenang Indonesia bukan sebagai negeri surga, melainkan sebagai contoh klasik katastrofi ekologis, kuburan beraneka ragam spesies dari ambisi yang salah kaprah akibat kerakusan aktivitas ekstraktif dan kegagalan demokrasi.
Merumuskan Kembali Arah Pembangunan
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 adalah warisan adiluhung para pendiri bangsa. Peta jalan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur secara hakiki. Kompas moral dan arah politik ekonomi. Namun bilamana ini terus diabaikan, bukan hanya hukum yang dilanggar tetapi masa depan bangsa yang pertaruhkan.
Sesungguhnya pasal ini telah menawarkan arah pembangunan yang visioner: demokrasi ekonomi yang menekankan kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Nilai-nilai ini bukan sekadar hiasan konstitusional, melainkan prinsip dasar untuk merumuskan ulang bagaimana pembangunan seharusnya dilakukan.
Pembangunan sejati bukan yang membangun gedung tinggi, tetapi yang meninggikan martabat manusia. Bukan yang memperkaya segelintir elit, tetapi yang memberdayakan rakyat kecil. Bukan yang memperluas kuasa negara atas tanah dan air, tetapi yang mengakui dan menghormati hak masyarakat adat.
Memaknai kembali pembangunan ekonomi bukan sekadar soal teknologi ramah lingkungan, namun juga soal politik yang ramah kehidupan dan ekonomi yang adil bagi manusia dan alam. menerapkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Memastikan setiap kebijakan investasi tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan merata dan keberlanjutan ekologi.
Pembangunan mesti diarahkan pada transformasi paradigma dengan menempatkan pasal 33 UUD 1945 sebagai pilar utama untuk membangun ekonomi yang tidak hanya bertumbuh, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada rakyat. Dan reformasi hukum bukan hanya soal mengganti pasal, namun mengubah arah pembangunan: dari ekstraksi ke regenerasi, dari pertumbuhan ke perawatan, dari elitis ke partisipatif.
Penulis adalah Miftahul Arifin, Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi
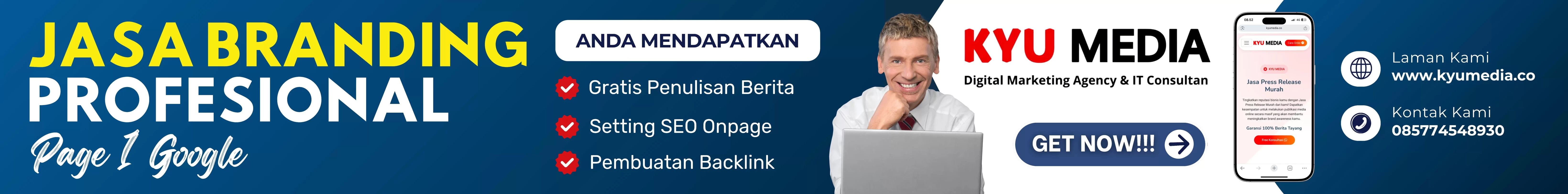

 Insight NTB
Insight NTB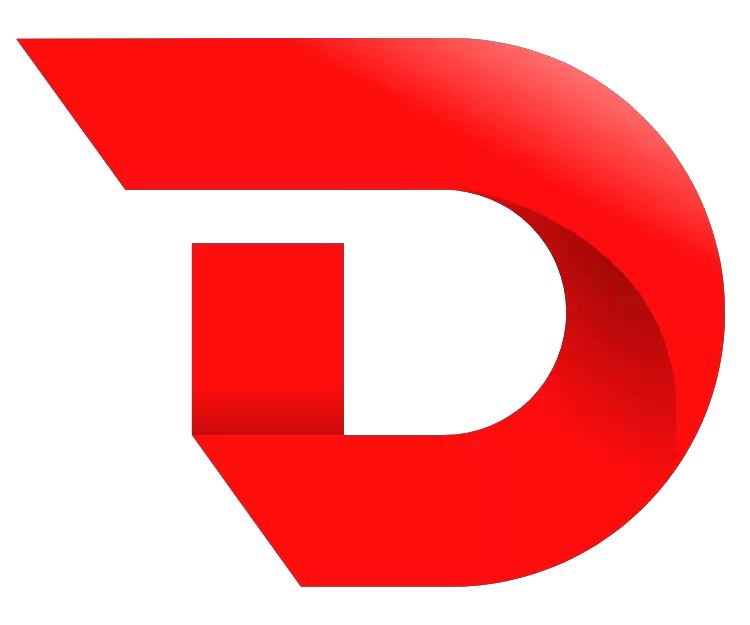 Daily Nusantara
Daily Nusantara Suara Time
Suara Time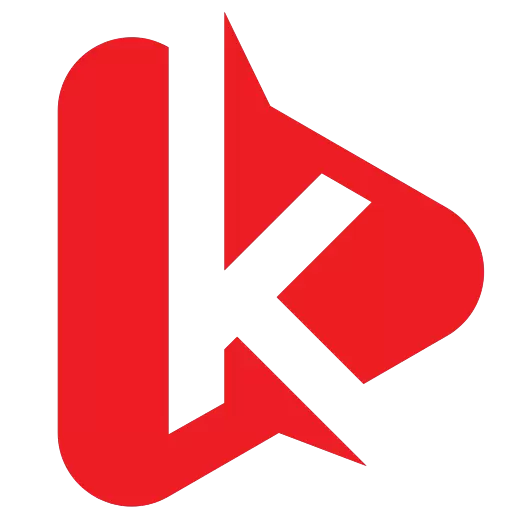 Kabar Tren
Kabar Tren Portal Demokrasi
Portal Demokrasi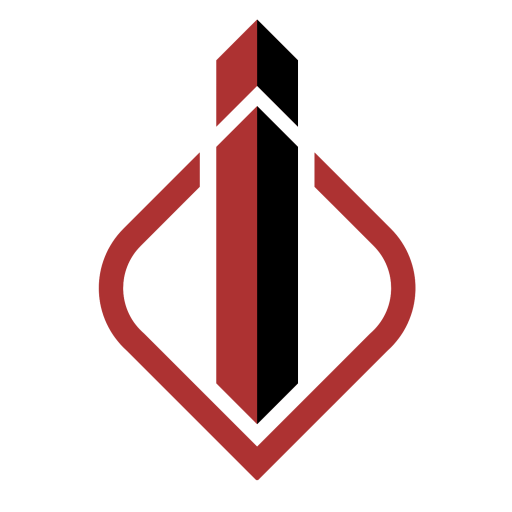 IDN Vox
IDN Vox Lens IDN
Lens IDN Seedbacklink
Seedbacklink