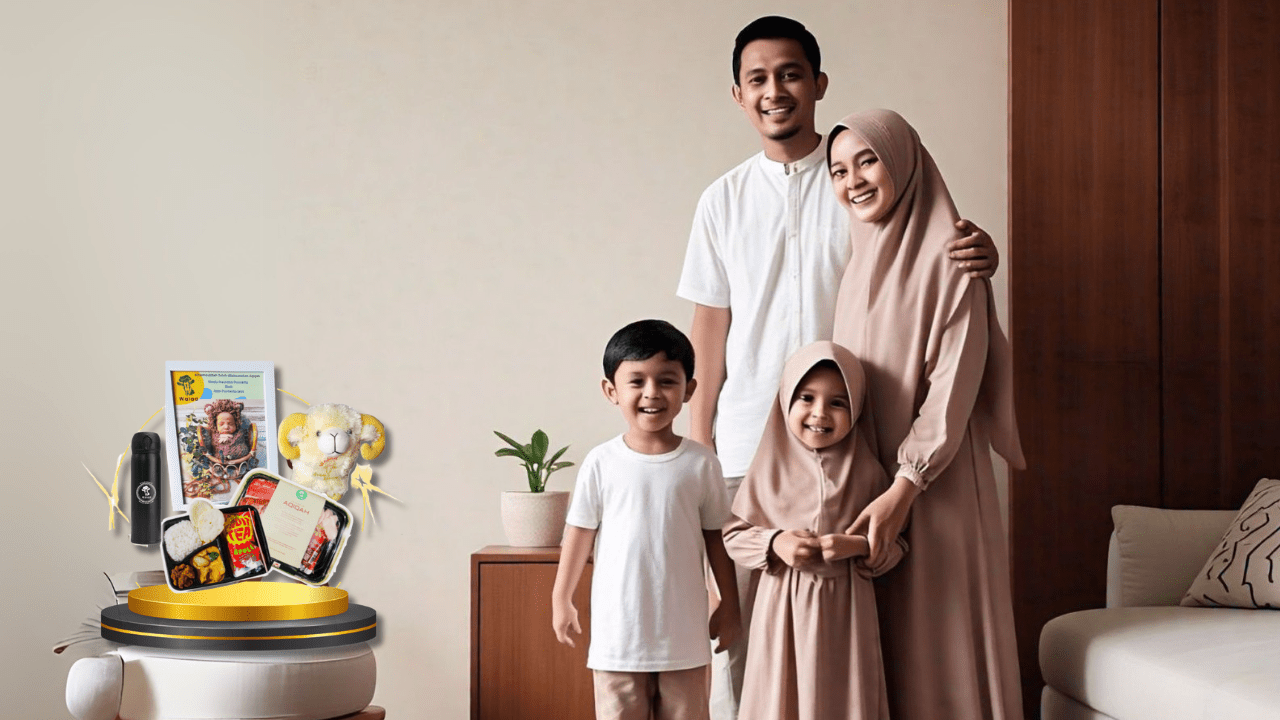Jamet adalah Kita di Waktu yang Lain

Editor: Ahmad Arsyad
KABARBARU, OPINI– Terlepas dari definisi lokal mengenai identitas Jawa Metal (Jamet) dan historia sosialnya. Keberadaanya kini menjadi tema bincang menarik, siapa mereka, kegilaan macam apa yang mendasarinya berperilaku demikian. Kanal media sosial baru Tiktok konon menjadi rahim trend anti-fashion, tarian, dan irama musik mereka untuk merebut perhatian publik. Saat diperhatikan tidak ada menarik, tetapi kita yang terlanjur memiliki budaya rasa yang sama yakni konsumen budaya konsumtif. Jamet kini telah dituduh merusak selera pasar yang menohok dengan merek dan pameran mewah itu karena norak bahkan berbau rasisme. Reel mereka menjadi jeda yang tidak mengenakkan jika tayang di beranda kita. Namun, sesekali saya heran kenapa begitu konsistennya mereka dengan gayanya, serta keunikan cara kerja mereka merespon teknologi masa kini itu.
Konon manusia gila dikerdilkan karena mereka minoritas secara jumlah, tetapi berapa banyak jumlah hasrat mematikan yang tidak tertahan dalam diri kita sehingga kadang menciptakan situasi tidak tenang. Orang Jakarta harus ke Puncak Bogor, melarikan diri dari penat frustasi tugas kerjaan. Guru sekolah melupakan lagu Balonku ada Lima, dengan musik pop mereka merawat jiwanya sebelum habis dimakan rutinitas. Dua perbandingan ini merupakan dimensi yang saya lihat dimainkan oleh Jamet. Mereka rata-rata pemuda lajang yang lebih banyak menjadi korban struktural tanpa akses. Dari mereka, dijumpai buruh harian tanpa tuan, telat gajian, bahkan ada yang bergantung pada musim sebagai mata pencarian. Ruasan lingkungan mereka juga tidak bisa banyak diharapkan, budaya kerja telah dibunuh oleh kegiatan moral namun miskin peran pada getir hidup mereka.
Keliyanan mereka adalah kebohongan pribadi kita yang melihat dunia itu sebagai Wonderland, bahwa dunia ini hanya berisi cerita manusia dengan dimensi kebaikan, kemewahan, kemapanan. Dalam skema budaya massa tidak ada justifikasi otentik yang bisa didasarkan pada budaya adhiluhung manapun. Mulai dari menyuap makan sampai memilih pakaian kita terbiasa menerapkan sistem sosial yang tidak dikenali lewat pendidikan dalam keluarga. Jamet berusaha menyindir kita, pilihan mereka sama gilanya dengan kita. Kepastian hidup mereka dan kita di sini sama ditempuh oleh tekanan untuk tidak kalah dan ditindas oleh sesama kita. Di lingkungannya, para Jamet juga menerima pukulan telak, dianggap liyan dan tidak pernah ada dalam daftar kebiasaan setempat.
Bagi John Paul Sartre “Manusia adalah sesuatu yang dihasilkan dari kebebasan memilih (free will)”. Desklusi peradaban juga disebabkan kita yang terlalu banyak ikut campur pribadi orang. Kebiasaan ini menjadi diakronik sekaligus satire, satu sisi kita adalah prodak dari budaya elektronik yang memiliki egoisme di ruang maya masing-masing, tetapi kita juga sering menyiapkan dirinya sebagai senjata untuk orang lain. Simpati saya pada Jamet ialah bagaimana mereka menemukan dan mengelola waktu luang itu. Penemuan ini merupakan respon yang umum di manapun. Banyak mereka yang terlempar dari permainan dunia ini menemukan ritme yang menyenangkan, menjadi prekondisi pemulihan kepercayaan hidup lebih baik. Pilihan demikian saya rasa lebih baik dari pada sebuah tindakan harakiri raga karena kekalahan yang tak rasional.
Kepada Bang Jamet, Dipersilahkan!
Saya yakin mereka para Jamet tahu bahwa sistem lembur menyebabkan manusia tidak lagi mempunyai waktu luang untuk berefleksi dan memikirkan situasinya secara kritis, akhirnya terjadi fenomena desublimasi represif. Artinya manusia bisa memenuhi kebutuhan melalui produk-produk yang dihasilkan oleh teknologi. Padahal, menurut pemikir Marcuse, kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan palsu (false need) yang sengaja diciptakan dengan menggunakan dunia iklan (advertising).
Yang dimaksud dengan kebutuhan palsu adalah suatu kebutuhan yang tidak muncul dari dalam sendiri seseorang secara murni tetapi dimasukkan secara paksa (imposed) dari luar. Sementara yang dimaksud dengan hilangnya fungsi kritis adalah hilangnya kemampuan manusia untuk menindak sistem yang ada. Penyebabnya, perbedaan antara buruh dan majikan tidak selebar dulu. Dengan kemajuan teknologi, hidup ini sangat berkelimpahan. Maka, daripada melakukan perubahan, lebih baik memberlakukan sistem yang sudah enak. Berpikir yang benar diyakini sebagai berpikir sesuai dengan sistem yang ada. Bahkan bahasa tidak lagi kritis karena telah dimanfaatkan, membantu sistem yang ada, misalnya lewat bahasa iklan yang persuasif.
Saya melihat alasan mereka memiliki kegiatan itu, terbesit sikap penuh resiko dan bertanggung jawab. Secara sadar mereka menolak untuk mengacaukan budaya yang sudah ajeg di tempat tinggalnya. Mereka masih sangat bergantung dengan tradisi setempat. Ada waktu di mana mereka memproduksi konten dan membaginya dengan aktivitas lain yang menurutnya adalah modal melanjutkan hidup. Bagaimana dengan kita yang duduk di area gemerlap ini, bukankah kita juga punya masa yang ”labil”.
Situasi yang membuat kita tidak bisa tinggal sendirian, dan berusaha masuk menjadi massa. Alasan ini dorong karena kita bukan takut sendiri tapi kesepian. Jika seorang Jamet memakai alasan ini, apalah bedanya kita selama ini yang cenderung acak-acakan dalam memiliki budaya dan kebiasaan.
Dalam Eros and Civilization, Marcuse membantu menunjukkan relasi antara masyarakat dengan aspirasi individu. Menurut Freud, Marcuse menampilkan konflik antara dorongan instingtual (libido dan thanatos) atau prinsip kesenangan (id) dengan organisasi sosial atau prinsip realitas (ego). Prinsip realitas itu menindas dorongan-dorongan instingtual (prinsip kesenangan). Dalam Freudian, antagonisme ini bersifat ahistoris, sementara Marcuse sebagai sosiolog dan filsuf kebudayaan memberi dimensi historis tanpa -seperti Fromm- meminimalkan pertentangan antara keinginan dasar dengan penindasan sosial. Marcuse mengatakan bahwa represi itu perlu untuk mepertahankan ras manusia itu sendiri. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah apa yang dia sebut dengan surplus represi, yaitu situasi yang melebih-lebihkan represi ”demi suatu kepentingan kelompok tertentu”.
Kesamaan kita dan Jamet terletak pada prinsip realitas tidak lain adalah prinsip produktivitas. Prinsip ini tdiak menjamin terpenuhinya dorongan instingtual tetapi untuk mengejar produktivitas, yakni pertumbuhan ekonomi. Freud sendiri juga menganalisis bahwa kebudayaan terbentuk karena pengorbanan libido. Libido disublimasi ke dalam kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan sosial. Prinsip realitas itulah yang membentuk kebudayaan. Jamet senarai dengan digtum Marcuse, bahwa kebudayaan tidak lain hanyalah suatu sublimasi, suatu kepuasan yang ditunda. Ia dibentuk dari konflik antara individu dengan lingkungannya, antara prinsip realitas dan prinsip kesenangan sehingga kebudayaan itu bersifat represif.
Kebudayaan represif memukul posisi para Jamet, sekalipun sama-sama berdiri di bawah pengaruh Gadget, mereka tetap tertolak. Musik yang ketinggalan, baju yang tidak sesuai, wajah tidak perawatan, lingkungan tidak estetik, hingga perangkat kampungan. Di antara kata kunci di atas masih banyak persamaan lain yang tidak memanusiakan mereka. Tetapi jika mau memilih latihan kejiawaan, barangkali motivator manapun harus belajar pada mereka. Tertekan struktutal, dibabat secara kultural sudah menjadi dua ujian yang barangkali hanya mereka yang memiliki mental tempaan kuat.
Agak sulit jika berhadapan dengan masyarakat satu dimensi dan juga menghadapi kebudayaan yang represif, dalam masyarakat satu dimensi, keinginan untuk perealisasian esensi manusia yang sejati tidak lagi suatu kebutuhan yang dirasakan. Jadi, permasalahan adalah bagaimana kebutuhan untuk merealisasikan potensi manusia, suatu kebutuhan yang terekspresikan dan terjerat dalam kebudayaan borjuis klasik, dapat diaktifkan menjadi praksis, yang mempunyai daya subversif.
Bagi saya semua insan memiliki kesempatan yang sama dalam mendefinisakan perubahan. Tentu klausul sulit diterima, tetapi tidak semua sistem yang ada saat ini benar-benar membantu menjadikan kita menjadi manusia yang hanif, teladan, konsisten, justeru yang terjadi sebaliknya. Jamet adalah pertujukan kultural yang berusaha mengambil peran dari padatnya pertunjukkan yang memuakkan di sekitar kita. Sekalipun kecilnya peran mereka, itu sudah cukup membantu dirinya sendiri tidak tidak kalah pada terpaan ketidakpedulian.
*) Penulis adalah Milki Amirus Sholeh, Pegiat Persoalan Sosial
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kabarbaru.co


 Beritabaru.co
Beritabaru.co Serikatnews.com
Serikatnews.com Suaratime.com
Suaratime.com Kabartren.com
Kabartren.com Sabdaguru.com
Sabdaguru.com Dailynusantara.com
Dailynusantara.com Portaldemokrasi.com
Portaldemokrasi.com Seedbacklink.com
Seedbacklink.com