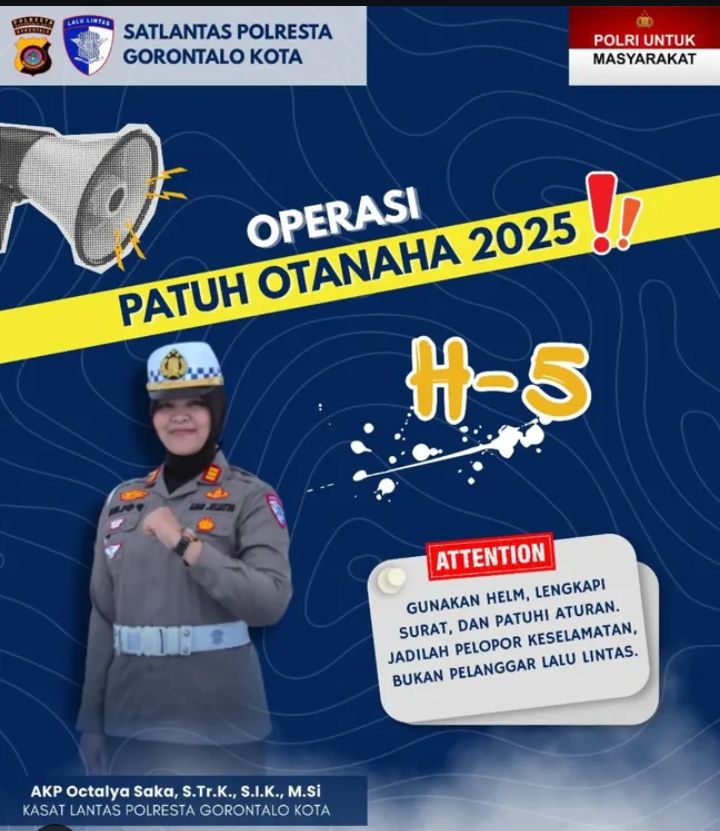Antara Milenial, Smarthphone, dan Masa Depan

Editor: Ahmad Arsyad | Jurnalis: Wafil M
KABARBARU, OPINI– Umumnya, milenial kerap diasosiasikan dengan sesuatu yang menunjuk pada batas periodik dan kemajuan teknologi. Batas periodik yang dimaksud dalam konteks ini adalah berlaku bagi generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan tahun 1995. Pada hakikatnya, asosiasi demikian hendak mengantarkan pada pemahaman bahwa, generasi milenial adalah mereka yang lahir pada saat teknologi mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat.
Karenanya tidak salah jika ada asumsi bahwa generasi milenial sering disebut sebagai generasi yang sangat akrab dengan dunia teknologi berbasis digital. Keakraban milenial dengan teknologi dan segala bentuk variannya telah menjadikan mereka tak bisa terpisah dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang semakin canggih, seperti penggunaan smartphone misalnya. Bagi milenial, smartphone telah menjadi bagian gaya hidup (lifestyle) yang dapat dengan mudah membantu segala bentuk aktivitas mereka.
Aksentuasi utama yang menjadi titik tekan dari tulisan ini bertolak dari asumsi bahwa perkembangan teknologi utamanya smartphone akan membuat milenial bisa terarah pada ranah positif yang dapat mendorong mereka mengoptimalkan secara penuh sumber daya yang mereka miliki. Asumsi demikian berbanding terbalik dengan kejadian yang ada di lapangan. Faktanya, masih banyak milenial yang menggunakan pemanfaatan teknologi, tidak kurang dan tidak lebih hanya untuk lifestyle saja.
Survei dari We Are Social pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia meningkat tajam. Dari 268,2 juta populasi masyarakat Indonesia, pengguna aktif media sosial di negara ini telah menyentuh angka 150 juta. Lebih detail, pengguna media sosial itu didominasi oleh mereka dengan rentang usia antara 18-34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang cukup intens dari mereka yang secara periodik masuk dalam kategori kaum milenial. Selain penggunaan media sosial, survei tersebut juga menunjukkan bahwa kuantifikasi pengguna smartphone dikalangan milenial berada pada angka 93,02 persen. Sebuah angka yang cukup fantastis bagi mereka dengan rentang usia yang demikian.
Penggunaan yang cukup intensif ini tentu memerlukan kajian lebih mendalam terkait efek media sosial dan smartphone bagi kaum milenial, khususnya yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan literasi, pola pikir, pola perilaku, pola sikap, dan pola sosial dalam ranah masyarakat. Bila penggunaan media sosial ataupun smartphone oleh milenial hanya digunakan untuk kebutuhan lifestyle, maka ada hal yang salah dalam paradigma mereka. Paradigma demikian dianggap salah karena mereka hanya dipacu oleh tuntutan perihal glorifikasi, yang pada kondisi tertentu akan berefek pada absennya cara untuk menyikapi persoalan-persoalan fenomena. Seperti misalnya, cara penyikapan terhadap simpang-siurnya beragam penyebaran isu di masyarakat.
Meski demikian, penting untuk segera dicatat, penggunaan media sosial yang diarahkan pada ranah yang positif tidak selamanya berefek pada absennya penangan informasi yang salah. Pada kondisi tertentu, media sosial dapat dijadikan sebagai instrumen atau medium untuk dapat bekerja secara efektif serta bertukar informasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hitungan detik, masyarakat di suatu daerah dapat mengetahui peristiwa atau kondisi yang sedang terjadi di daerah, wilayah, ataupun negara lain.
Henry Jenkis menyebut bahwa, khalayak media dapat diposisikan sebagai konsumen media sekaligus berperan sebagai produsen dari informasi yang tersebar luas di media tersebut. Lebih jauh daripada itu, Jenkis juga menyebut bahwa khalayak juga dapat menciptakan komoditas mereka dengan menguraikan dan menjelaskan hakikat makna yang termuat dalam produk media tersebut. Jika dikorelasikan dengan peran milenial dalam bermedia sosial, argumen Jenkis hendak mengantarkan pada pemahaman bahwa milineal dapat dengan sesuka hati melontarkan segala bentuk ide ataupun pemikiran yang terbesit dalam pikiran mereka.
Sebagai pihak yang memiliki posisi sebagai produsen dan agensi informasi, tentu kebebasan untuk berpendapat tak dapat dihindari. Akan tetapi, terdapat poin yang secara khusus perlu diperhatikan oleh kelompok milenial sebelum menyebarkan informasi pada ranah publik, yaitu kuatnya pengetahuan dan penguasaan literatif dari personal mereka. Meski tidak ada jaminan bahwa literasi akan membantu mereka untuk secara aktif menginformasikan hal-hal yang bersifat sensasional, namun setidaknya literasi akan menjadi instrumen untuk mengantarkan milenial untuk menyikapi hal dengan sikap yang rasional. Penguatan literasi yang cukup intens, akan menjadi perantara bagi milenial untuk memproteksi informasi hoax dalam media sosial serta membantu mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih produktif.
Penguatan Literasi
Literasi anak bangsa kita saat ini berada pada fase yang sangat mengkhawatirkan, hal ini terbukti dari hasil survei internasional oleh Most Literate Nations in the World, yang diterbitkan Central Connecticut State University (Maret, 2016). Dalam survei tersebut menyatakan bahwa Indonesia hanya mampu menduduki peringat ke-60 dari 61 negara yang dikontestasikan, atau peringkat kedua dari bawah. Artinya, berdasarkan hasil survei pemeringkatan tersebut, Indonesia hanya mampu lebih baik dari sebuah negara kecil di Afrika, Botswana. Bahkan di antara negara-negara tetangga, seperti Thailand (59), Malaysia (53), dan Singapura (36), kita berada di bawah mereka.
Tidak tertegunkah kita melihat peringkat literasi bangsa ini yang tenggelam sampai kepermukaan? Tidak malukah kita kepada negara-negara tetangga, yang secara kekayaan alam kita berada jauh di atas mereka, tapi kenapa dalam persoalan literasi kita justru malah tertinggal jauh dari mereka? Atau mungkin kita sudah tidak punya rasa malu dalam persoalan semacam ini?
Kita seolah kesulitan mencetak kader anak bangsa yang memiliki intelektualitas mempuni seperti pendahulu dan pendiri bangsa ini. Mengimajinasikan akan lahirnya tokoh semacam mereka hanyalah sebatas idealisme berlebihan terhadap sesuatu yang berada diseberang realitas transenden.
Para kaum millenial bangsa saat ini lebih disibukkan dengan budaya menonton ketimbang membaca, mereka lebih berasyik-masyuk menghatamkan sodoran konten-konten youtube ataupun film “tak bermutu” dari kaum millenial lainnya (seperti youtuber) daripada menghatamkan buku bacaannya. Eksistensi literasi kita semakin diperparah dengan razia tak berdasar yang dilakukan oleh pihak anggota milisi sektarian. Maka pantas saja kiranya bila bangsa kita saat ini tengah berada pada deretan elemen terbawah dalam diskursus literasi internasional.
Jika kaum milenial terus-menerus disibukkan dengan perihal media sosial yang hanya bersifat sensasional, tentu sulit bagi kita untuk mengimajinasikan sebuah bangsa yang memiliki jati diri yang sangat perfect seperti negara-negara yang sudah melesat jauh di depan kita. Oleh karenanya kita harus putar haluan. Yang harus dijadikan prioritas oleh milenial sekarang adalah sepak terjang pengembangan dan pendalaman letaratif. Khususnya pada ranah “pendidikan dan literasi”.
Memang benar, tidak ada yang salah ketika para milenial aktif dalam bermedia sosial ataupun memegang smartphone. Namun jauh sebelum itu, harus ada persiapan yang cukup matang dari mereka berupa penguatan budaya literatif. Penyebaran hoax yang cukup intens merupakan akibat langsung dari kurangnya filterasi yang mempuni dari kaum milenial dalam perihal literasinya. Ketika literasi sudah kuat, maka wujud media sosial yang sensasional dan rasional akan menjadi perwujudan baru bagi masa depan milenial yang lebih produktif dan progresif.
*) Penulis adalah M. Adhiya Muzaki (Founder Penggerak Milenial Indonesia)
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kabarbaru.co
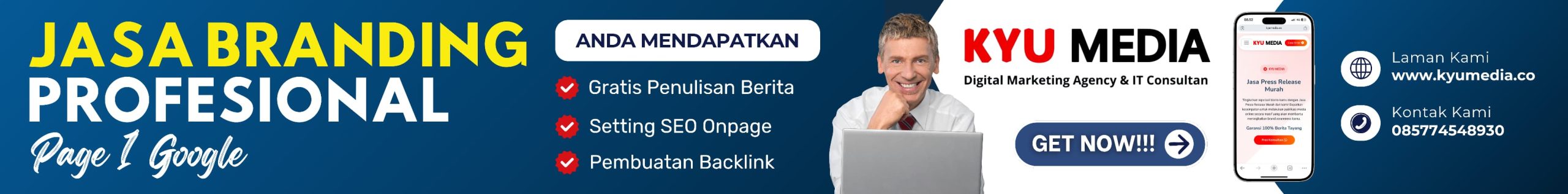

 Beritabaru.co
Beritabaru.co Serikatnews.com
Serikatnews.com Suaratime.com
Suaratime.com Kabartren.com
Kabartren.com Sabdaguru.com
Sabdaguru.com Dailynusantara.com
Dailynusantara.com Portaldemokrasi.com
Portaldemokrasi.com Seedbacklink.com
Seedbacklink.com