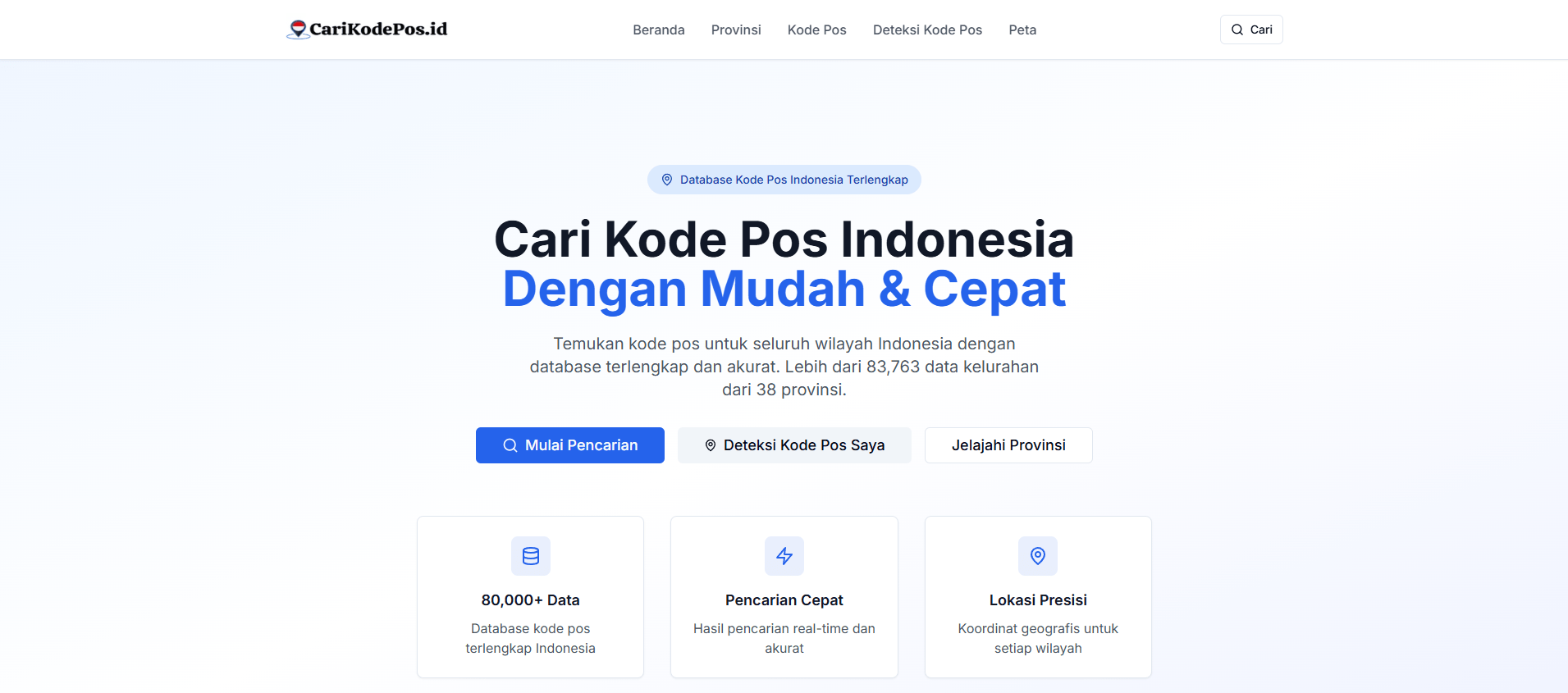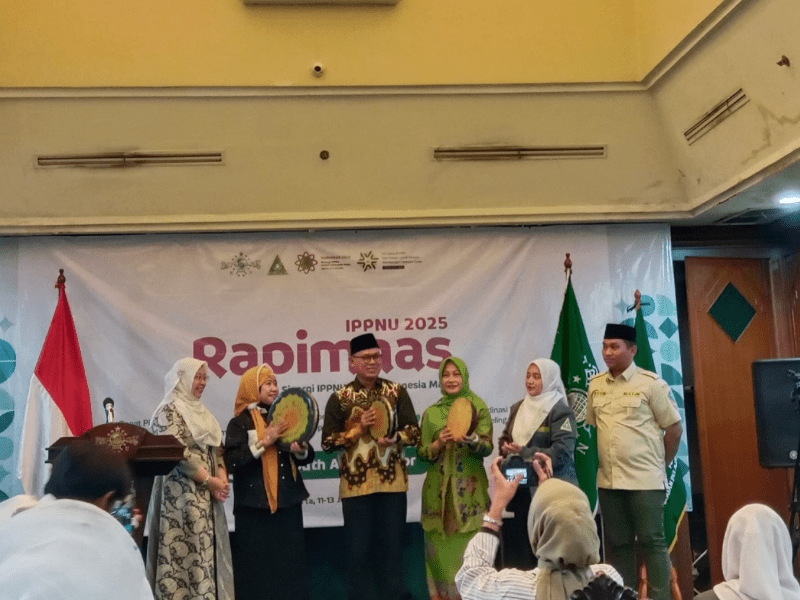Mahasiswa dalam Ambang Batas Etika dan Kritisismenya

Editor: Ahmad Arsyad
Kabar Baru, Opini – Menyebarnya berita online dalam satu minggu terakhir tentang sengkarut ijazah mahasiswa IAIN Madura sebagaimana pemberitaan di headline Media Jatim 28 Januari 2024 tentang “465 ijazah tak keluar setelah 3 bulan diwisuda, lulusan IAIN Madura mengaku kesulitan daftar kerja”, kemudian tanggal 30 Januari 2024 tentang “Ijazah alumni IAIN Madura tak terdaftar di sivil kemendibud RI, ketahuan saat gagal isi dapodik”, lalu tanggal 2 Februari 2024 tentang “Imbas ijazah tak terdaftar di kemendikbudristek RI alumni IAIN Madura kesulitan daftar PPPK”, dan beberapa berita lainnya menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi kalangan dosen, terutama dalam hal mengukur keberhasilan internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam khususnya pada aspek etika atau akhlakul karimah yang setidaknya selama empat tahun telah diajarkan dan dibangun di kampus.
Terlepas dari afirmasi pelayanan yang memang harus mahasiswa dapatkan, ada tabrakan ide antara etika dan kritisisme mahasiswa. Kenapa media yang dengan sangat cepat mudah tersebar di masyarakat menjadi pilihan tempat curhat dalam merefleksikan kekecewaannya pada layanan institusi? kenapa kekecewaan itu menjadi kritik yang tersebar liar mengganggu laju institusi yang sedang berproses alih transformasi? kenapa? Tentu masih banyak pertanyaan “kenapa” tertimbun berantakan dan belum menemukan jawabannya yang pasti.
Harus diakui terlebih dahulu bahwa mendakwa keduanya tanpa melibatkan faktor penyebab yakni pelayanan terhadap mahasiswa rasanya memang tidak adil, karena ada bagian fundamental yang terasa hilang dan mahasiswa akan menganggapnya hanya utopia. Namun demikian, tulisan ini hanya bermaksud fokus pada diskursus adanya benturan antara etika dan kritisisme mahasiswa yang bisa berposisi sebagai paradigma dalam gerakan sengkarut ini, karena apa yang dipersepsi oleh mahasiswa berpotensi menjadi kebenaran yang dibenarkan menjadi kebenarannya sendiri yang parsial. Pada titik ini buah pikiran lebih berbahaya daripada perilakunya.
Kita sama-sama menyadari bahwa etika mafhum diamini sebagai nilai peradaban yang dijadikan risalah prioritas bagi Rasulullah. Sabdanya tentang “innama bu’itstu liutammima makarimal akhlak” memutlakkan nilai etika ini harus menjadi parameter komunikasi dan interaksi ideal umat Islam, termasuk mahasiswa. Sebagai parameter, dalam konteks IAIN Madura seharusnya etika menjamin lembaga pendidikan tinggi ini memiliki rasa aman dari gangguan apapun, terutama yang menghambat pergerakannya pada kemajuan institusi. Etika harusnya juga memastikan komunikasi yang terbangun dalam lingkaran kampus lebih-lebih oleh mahasiswa dan atau alumni adalah komunikasi yang sejuk, santun, tidak menjatuhkan dan tidak mengganggu laju jalannya. Tapi di sisi yang lain, kritik atau yang penulis sebut sebagai ‘kritisisme’ merupakan faham tentang daya nalar yang sengaja dibangun untuk akal sehat, akal adil dan akal yang membebaskan. Cambridge Dictionary mendefinisikannya sebagai, “the act of giving your opinion or judgment about the good or bad qualities of something or someone or the act of saying that something or someone is bad”. Ibarat sumbu ia memang dinyalakan untuk menerangi gelapnya keadaan. Ia dirajut untuk menjadi cemeti amarasuli (meminjam bahasa mak lampir dalam film misteri gunung merapi) yang berusaha meluruskan jalan bengkok dan kembali normal sebagaimana seharusnya. Lalu pertanyaannya, Ketika dua ide ini bertabrakan kira-kira bagian mana yang harus dimenangkan?
Setidaknya ada dua hal penting yang perlu diulas dalam menjawab pertanyaan ini; pertama, bahwa jatuhnya pilihan mahasiswa pada media untuk melampiaskan kekecewaannya adalah suatu kenyataan yang sulit untuk tidak disebut sebagai kritik dan bersengaja ‘menyakiti’. Hal ini bisa dilihat dari kontinuitas terbitnya berita dengan jarak tanggal yang pendek, hanya antara 28, 30 di bulan Januari serta dilanjukan tanggal 02 di bulan Februari, jarak waktu yang sangat dekat. Terasa sangat intensif sekali.
Di sisi yang lain, pihak kampus termasuk para dosen merasakannya sebagai kenyataan yang pahit. Kenyataan yang kalau boleh memilih diharapkan tidak terjadi karena sangat mengganggu terhadap citra kampus IAIN itu sendiri. Bagi mahasiswa, pertaruhannya mau bersabar menunggu waktu atau menyakiti orang-orang yang sesungguhnya berposisi sebagai guru bagi mereka, orang yang kata sayyidina Ali telah mengajarkan mereka ilmu walaupun hanya satu huruf. Dalam konteks ini, Rasulullah memberikan catatan melalui sabdanya; “Belajarlah kalian ilmu untuk ketenteraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya.” (HR. Ath-Thabrani).
Kalau kita mencoba sedikit berfikir bijaksana dan menjadikan al-Quran sebagai landasan, maka surat al-Hujurat ayat 12 setidaknya sudah cukup menjadi acuan bahwa berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjingnya dianalogikan dengan seseorang yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Al-Quran kemudian mempertegas dengan menyebut bahwa kita pasti akan merasakan jijik terhadapnya. Apa yang disampaikan al-Quran tentu tidak berbatas waktu. Tidak ada deadline yang ditargetkan untuk membatasi nilai kebijaksanaan ini. Sampai kapanpun dan selamanya akan tetap seperti ini. Lebih dari itu, al-Quran surat An-Nahl ayat 125 bahkan secara gamblang mengajarkan kita untuk mengutamakan kebijaksanaan dan kebaikan sebagai satu-satunya cara yang baik untuk menyampaikan kebaikan dengan baik.
Kedua, secara epistemologis, kritisisme sesungguhnya merupakan konsep filosofis yang memadukan perselisihan teori antara empirisme dan rasionalisme. Empirisme yang meyakini bahwa pengetahuan bersumber pada pengalaman, ditentang oleh rasionalisme yang lebih memilih akal sebagai sumbernya. Perselisihan ini kemudian didamaikan dengan kritisisme sebagai sintesa yang meyakini konvergensi dan mempertemukan keduanya. Sebagai titik temu ia mencoba merajut benang kusut yang pada awalnya sulit dipertemukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini berarti bahwa kritisisme harusnya tidak boleh liar, tidak boleh menyakiti dan tidak boleh menjatuhkan, bahkan sebagai konsep yang mempertemukan kritisisme layak menjadi patron bukan dalam pengertiannya yang menyerang, tapi mendamaikan. Apalagi Immanuel Kant sebagai perintis teori ini menyebutnya sebagai pemikiran transendental, pemikiran yang bersifat beyond, bukan berhenti pada bagian yang inderawi saja. Bahkan dalam imperative categoris-nya ia menyandarkan perilaku pada moral/etika dan memposisikan nya sebagai kewajiban.
Oleh karena itu, dalam konteks ini etika atau akhlakul karimah adalah beyond itu sendiri, dan kritisisme mahasiswa idealnya harus berdiri di atas kaki etika, karena membiarkannya ibarat membiarkan singa menerkam tuannya sendiri. Insyaallah begitu, wait and see!
*) Penulis: Maimun, Dosen Institut Agama Islam Negri (IAIN) Madura.
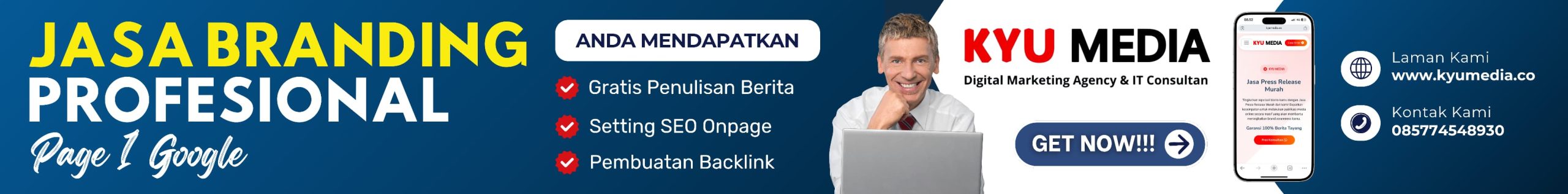

 Beritabaru.co
Beritabaru.co Serikatnews.com
Serikatnews.com Suaratime.com
Suaratime.com Kabartren.com
Kabartren.com Sabdaguru.com
Sabdaguru.com Dailynusantara.com
Dailynusantara.com Portaldemokrasi.com
Portaldemokrasi.com Seedbacklink.com
Seedbacklink.com