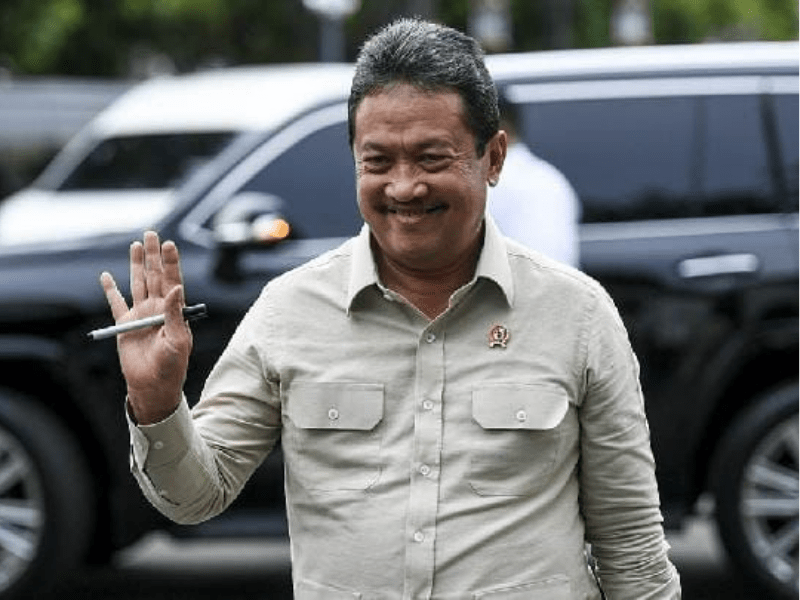Macapat: Seni Menikmati Lengkingan Suara Toa Semalam Suntuk

Editor: Ahmad Arsyad
KABARBARU, OPINI- Salah satu tradisi keislaman yang masih eksis dan berkembang di kampung saya (Desa Batukerbuy, Pasean, Pamekasan, Madura) hingga era milenial ini adalah macapat. Sebagian orang menyebutnya dengan mamâcah, dan terkadang juga disebut tembhâng. Tradisi macapat (mamâcah) ini merupakan salah satu warisan berharga para Wali Sanga yang berdakwah secara arif dan bijak. Mereka memanfaatkan kesenian masyarakat sebagai media (wasîlah) untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, baik berupa wayang, macapat, suluk, gamelan, benda pusaka, arsitektur, maupun lainnya. Sehingga masyarakat merasa asyik dan tidak sadar bahwa mereka sedang didakwahi, padahal para Wali Sanga sejatinya sedang mendakwahi mereka.
Menurut Zahra Haidar, banyak para Wali Sanga yang menciptakan macapat, seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Drajat, Sunan Giri Kedaton, Sunan Giri Prapen, Sunan Geseng, Sunan Majagung, Sunan Muryapada, Sultan Pajang, Sultan Adi Eru Cakra, dan Adipati Nata Praja. Makanya, tidak heran jika syair-syair yang terkandung dalam menyiratkan nilai-nilai al-Qur’an (Macapat Tembang Jawa, Indah, dan Kaya Makna, 2018).
Saya pernah menghadiri acara macapat di sebuah kampung, dan sempat terbesit dalam pikiran saya bahwa para wali ternyata memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Mereka tidak terburu-buru dalam berdakwah, tetapi berdakwah secara perlahan-lahan dan berkelanjutan dengan cara menyisipkan ajaran-ajaran Islam lewat macapat. Karena memang tabiat (watak) dakwah para Wali Sanga adalah “menangkap ikan tanpa mengeruhkan airnya.”
Makanya, prinsip dan strategi dakwah mereka adalah Tut Wuri Handayani dan Tut Wuri Hangiseni, sebagaimana disampaikan oleh Fahruddin Faiz di Ngaji Filsafat. Menurutnya, para Wali Sanga menghindari sikap ekstrem, frontal, dan konfrontasi dengan masyarakat dalam berdakwah. Mereka tidak mendahului dan menggagahi masyarakat, tetapi mengikuti masyarakat dari belakang sembari memengaruhi mereka dan memberikan petunjuk sedikit demi sedikit. Inilah makna Tut Wuri Handayani. Selain itu, para Wali Sanga mengikuti masyarakat dari belakang sembari mengisi ajaran-ajaran Islam secara perlahan-lahan. Inilah makna Tut Wuri Hangiseni (lihat Ngaji Filsafat 138: Sufi Nusantara – Sunan Kalijaga dan Ngaji Filsafat 273: Sunan Bonang).
Di kampung saya sendiri ada beberapa câtôr (buku macapat) yang dibaca dalam acara INI, seperti Câtôr Pandhâbah (tentang Pandawa Lima), Câtôr Nôrbuwât (tentang Nabi Muhammad saw.), Câtôr Mi‘rât (tentang peristiwa Isrâ’-Mi‘râj), dan Câtôr Nabi Yûsuf (tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf as.). Selain itu, ada Câtôr Sunan Kâlîjâgâ (tentang perjalanan hidup Sunan Kalijaga) karya Kiai Mustari (pegiat macapat dari Desa Batukerbuy) yang dibaca di acara tertentu.
Menurut H. Muzammil (pegiat macapat dari Desa Batukerbuy), Câtôr Pandhâbah dibaca ketika acara Rôkat Pandhâbah. Câtôr Mi‘rât dibaca ketika bulan Rajab. Câtôr Nabi Yûsuf dibaca ketika acara pélét kandûngân (selamatan kandungan 7 bulan). Sedangkan Câtôr Nôrbuwât dibaca ketika acara pernikahan, dan terkadang juga dibaca di acara pélét kandûngân jika tidak ada Câtôr Nabi Yûsuf.
Dalam praktiknya, macapat dilaksanakan pada malam hari. Ada yang membaca lirik-lirik (tembang) macapat sesuai lagu masing-masing, dan ada pula yang menjelaskan maksud dari tembang tersebut. Orang yang membaca tembang (menembang) macapat disebut tôkang tembhâng/panembhâng, dan orang yang menjelaskan maksud tembang tersebut disebut tôkang tegghes/panegghes. Macapat diselenggarakan semalam suntuk menggunakan pengeras suara. Biasanya menggunakan toa, dan terkadang juga menggunakan toa sekaligus sound system ketika acara pernikahan. Menariknya, suara dan lagu orang yang membaca tembang tersebut semakin malam semakin indah dan melengking, terutama ketika sudah memasuki jam 12 ke atas.
Sebagai sebuah tradisi yang sudah mengakar dan turun temurun, sudah barang tentu masyakarat sekitar menikmati lengkingan tembang macapat yang terdengar nyaring dari toa itu hingga semalam suntuk. Mereka tidak protes―apalagi marah dan melaporkan kepada polisi―terhadap lengkingan suara orang-orang yang membaca tembang macapat tersebut.
Bahkan sebagian besar masyarakat di kampung saya dan beberapa kampung lain meyakini macapat sebagai tradisi yang harus dilaksanakan (saya pernah membersamai Fathorrahman meneliti macapat di Desa Batukerbuy untuk tugas akhir/skripsi berjudul “Estetika Religius Tradisi Rokat Pandhaba di Desa Batukerbuy Pasean Pamekasan”). Menurut H. Muzammil, masyarakat memiliki maksud beragam ketika mengadakan acara macapat. Mereka sengaja mengundang dan membayar para pegiat macapat (panembhâng dan panegghes) untuk membaca macapat semalam suntuk menggunakan toa (bahkan terkadang disertai suond system) dari jam 8 malam hingga sekitar jam setengah 4 pagi.
Beberapa maksud tersebut adalah: pertama, untuk meruwat anak tertentu dengan Rôkat Pandhâbah, seperti anak Ontang Anting (anak tunggal laki-laki atau perempuan) dan Pandawa Lima (memiliki lima anak laki-laki). Rôkat Pandhâbah ini pada umumnya dilakukan ketika anak Ontang Anting atau Pandawa Lima tersebut menikah. Salah satu isi Rôkat Pandhâbah adalah membaca Câtôr Pandhâbah. Kedua, untuk pélét kandûngân (selamatan kandungan 7 bulan). Ketiga, selamatan untuk anak yang baru disunat. Keempat, selamatan untuk acara pernikahan. Kelima, selamatan sekaligus memperingati peristiwa Isrâ’-Mi‘râj setiap bulan Rajab. Keenam, karena memiliki nazar (néyat) untuk mengadakan macapat.
Di kampung saya ada beberapa tokoh macapat yang kesohor dan sering diundang ke berbagai kampung, seperti H. Muzammil (panembhâng), H. Ahmadi (panembhâng), dan Kiai Burantah (panegghes). H. Muzammil sendiri sudah menekuni tembang macapat sekitar 30 tahun. Dia memiliki suara yang khas dan merdu, sehingga sering diundang ke berbagai daerah di Pamekasan dan Sampang, seperti Batukerbuy, Bindang, Dempo Barat, Dempo Timur, Sana Daja, Sana Tengah, Ahadan, Ponjanan, Waru Timur, Waru Barat, Bujur Timur, Bujur Barat, Bulangan Haji, Tanjung, Lesong, Tamberu, Batu Bintang, Sokobana, Bira Timur, Bulmatet, Robatal, Sreseh, dan lainnya.
Bahkan sekarang di kampung saya ada Perkumpulan Macapat Bintang Sembilan Pamekasan di bawah naungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Pasean. Perkumpulan ini diikuti oleh para pegiat macapat dari berbagai desa, seperti Batukerbuy, Bindang, Dempo Barat, Dempo Timur, Sana Daja, dan bahkan ada desa dari kecamatan lain, seperti Sotabar dan Tamberu. Menurut Kiai Mustari (salah satu penasihat Perkumpulan Macapat Bintang Sembilan Pamekasan), Perkumpulan Macapat Bintang Sembilan Pamekasan ini memiliki anggota sekitar 30 orang dari berbagai daerah tersebut. Ia diadakan setiap setengah bulan sekali secara bergiliran di rumah masing-masing anggota mulai jam 8 malam sampai jam 12 malam menggunakan toa. Wallâhu A‘lam wa A‘lâ wa Aḥkam…
*) Penulis adalah Nasrullah Ainul Yaqin, Sekretaris Lakpesdam Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pasean tahun 2020-2025, sekaligus tenaga pengajar di Madrasah Diniyah Nurul Jadid Bakong Batukerbuy Pasean Pamekasan sampai saat ini.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kabarbaru.co


 Beritabaru.co
Beritabaru.co Serikatnews.com
Serikatnews.com Suaratime.com
Suaratime.com Kabartren.com
Kabartren.com Sabdaguru.com
Sabdaguru.com Dailynusantara.com
Dailynusantara.com Portaldemokrasi.com
Portaldemokrasi.com Seedbacklink.com
Seedbacklink.com